Yang membedakan karya Zen Cho (kiri) dan Joshua Kam dari novelis Malaysia dan Asia Tenggara lainnya adalah eksplorasi orientasi seksual non konformis dan episode kontroversial dalam sejarah negara mereka. (Nikkei montase/Sumber foto milik Zen Cho dan Joshua Kam)
SuaraKita.org — Khidir, seorang tokoh Islam berusia seabad yang mengenakan jubah hijau, muncul di Masjid Jamek di Kuala Lumpur modern untuk menyadarkan tubuh seorang blogger politik yang ditemukan tenggelam di kanal, kemudian melakukan perjalanan ke Pekan, di Negara Bagian Pahang, untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat yang disebut “The Mouth”.
Di tengah perjalanan gila ini, di mana dewa dan dewi menyamar sebagai manusia, hutan bersinar dalam gelap, dan jalan raya emas halus menghubungkan bumi dengan langit, muncul bahwa penyelamat misterius yang juga gay — sesuatu yang sebagian besar masih dijauhi oleh para penulis di Malaysia, di mana tindakan seks gay dan lesbian tetap dapat dihukum di bawah hukum Islam tradisional.
“Saya ingin menggambarkan sejarah Malaysia, khususnya sejarah kiri dan queer, dengan akurasi yang saya temukan hilang dalam beberapa catatan waktu itu,” kata penulis kelahiran Kuala Lumpur, Joshua Kam.
Novel debut Joshua Kam “How the Man in Green Saved Pahang, and Possibly the World” memenangkan Epigram Books Fiction Prize yang bergengsi di Singapura pada tahun 2020 – pertama kalinya hadiah tahunan sebesar 20.000 dolar Singapura terbuka untuk novelis dari negara ASEAN.
Novel ini adalah cerita yang merupakan bagian dari petualangan dongeng, bagian dari cerita rakyat lokal yang berwawasan, dan bagian dari risalah sejarah Malaysia, dibumbui dengan realisme magis dan kisah masa depan. Namun, fitur buku yang paling mencolok adalah bahwa pahlawannya sebagian besar adalah karakter LGBTQ.
 Pahlawan dalam novel debut pemenang penghargaan Joshua Kam sebagian besar adalah karakter LGBTQ. (dok. Joshua Kam)
Pahlawan dalam novel debut pemenang penghargaan Joshua Kam sebagian besar adalah karakter LGBTQ. (dok. Joshua Kam)
Dalam hal ini Joshua Kam mengikuti karya fiksi fantastis Malaysia terbaru lainnya dalam bahasa Inggris, terutama oleh Zen Cho, penulis kelahiran Malaysia yang berbasis di Inggris. Dia menggunakan karakter non-kulit putih dan LGBTQ dalam dua novel fantasi sejarah sukses yang berlatar di Regency London, “Sorcerer to the Crown” (2015) dan “The True Queen” (2019), dan juga dalam novel wuxia- nya “The Order of the Pure Moon Reflected in Water “(2020). Wuxia berarti fiksi sejarah Tiongkok yang berfokus pada seni bela diri.
Novel baru Zen Cho “Black Water Sister,” baru saja diterbitkan secara internasional oleh Penguin Random House, juga merupakan karya pertamanya yang berlatar di Malaysia kontemporer. Bercerita tentang Jess, seorang lesbian muda Malaysia yang pindah ke pulau asal keluarganya di Penang setelah dibesarkan di Amerika Serikat. Dipandu oleh suara arwah neneknya yang sudah meninggal, Jess harus menemukan cara untuk menenangkan Black Water Sister, seorang dewi Tionghoa setempat.
Apa yang membedakan karya Zen Cho dan Joshua Kam dari novelis Malaysia dan Asia Tenggara lainnya adalah eksplorasi orientasi seksual nonkonformis mereka dan episode kontroversial sejarah negara mereka, termasuk Darurat Malaya, di mana pasukan Inggris, Malaya dan Persemakmuran mengalahkan pemberontakan komunis di kolonial Malaysia, yang dulu dikenal sebagai Malaya. Pertempuran dimulai pada tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1960, tiga tahun setelah Malaysia merdeka dari Inggris, meskipun konflik tingkat rendah kembali meletus pada tahun 1968, akhirnya berakhir pada tahun 1989.
 Novel baru Zen Cho “Black Water Sister” menceritakan kisah Jess, seorang lesbian muda Malaysia yang pindah ke pulau asal keluarganya di Penang setelah dibesarkan di Amerika Serikat. (dok. Zen Cho)
Novel baru Zen Cho “Black Water Sister” menceritakan kisah Jess, seorang lesbian muda Malaysia yang pindah ke pulau asal keluarganya di Penang setelah dibesarkan di Amerika Serikat. (dok. Zen Cho)
Kedua penulis memadukan fiksi mereka dengan sejarah multi etnis, agama, dan cerita rakyat negara itu — kelompok penduduk Melayu, Cina, India, dan pribumi yang besar tumpang tindih dengan kelompok Muslim, Buddha, Kristen, Hindu, dan agama lainnya — memperkenalkan Malaysia kepada pembaca internasional dengan keunikan mereka sendiri. merek realisme magis Asia Tenggara.
Dalam hal pilihan protagonisnya, Zen Cho mengatakan prevalensi beberapa jenis karakter dalam literatur yang didistribusikan secara global adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuatan dengan akar sejarah yang dalam. “Tapi tidak secara inheren lebih alami untuk menulis cerita tentang lelaki kulit putih yang hetero daripada tentang lelaki kulit hitam yang hetero, atau perempuan Asia yang aneh,” kata Zen Cho. “Saya pikir bahwa industri penerbitan Amerika Serikat dan Inggris semakin sadar akan pentingnya inklusivitas, meskipun jalan masih panjang.”
Joshua Kam, sebaliknya, bersyukur bahwa novel debutnya diterbitkan oleh dan untuk orang Asia Tenggara. “Seperti yang dicatat oleh rekan saya sesama finalis Epigram Fiction Prize, Sunisa Manning tentang rumahnya sendiri, Thailand, negara-negara seperti kita sering dilihat, dilirik, diteorikan oleh orang luar. Tapi jarang kita bisa membaca suara-suara Asia Tenggara lainnya yang mengklaim kembali masa lalu atau masa depan.”
Joshua Kam menyeimbangkan masa lalu dan masa depan dalam kisah pertemuan Khidir dan Gabe — seorang penerjemah Kristen Malaysia-India yang menjadi kekasih dan kaki tangannya Ling Mo Niang dan Toh Yun, dua pejuang perempuan di Tentara Pembebasan Nasional Malaya, angkatan bersenjata sayap Partai Komunis Malaya. Dipisahkan oleh Malayan Emergency, mereka mengakui cinta mereka, yang tidak dapat diterima pada saat-saat itu, dalam serangkaian surat emosional yang ditemukan Lydia, keponakan buyut Toh, yang disimpan di dalam buku harian tua setelah kematian bibi buyutnya.
 “How the Man in Green Saved Pahang, and Possibly the World” karya Joshua Kam sebagian berlatar belakang Darurat Malaya. (Foto oleh Bert Hardy)
“How the Man in Green Saved Pahang, and Possibly the World” karya Joshua Kam sebagian berlatar belakang Darurat Malaya. (Foto oleh Bert Hardy)
“Saya rasa banyak orang Malaysia yang tidak keberatan melihat karakter LGBTQ dalam cerita,” kata Joshua Kam, yang menyebut dirinya gay. “Tapi untuk benar-benar melihat tubuh queer dan orang queer sebagai sesuatu yang suci, artinya penuh cahaya ilahi seperti orang lain, mungkin itulah yang masih terasa subversif. Terkadang rasanya seperti saya menulis literatur religius hampir sama seperti saya menulis cerita rakyat queer. Bagi saya, mereka mungkin hal yang sama.”
Ditanya mengapa banyak karakter utamanya berasal dari komunitas LGBTQ, Zen Cho mengatakan dia tertarik pada gender dan seksualitas, termasuk orang heteroseksual cisgender (mereka yang mengidentifikasi identitas gender mereka saat lahir). “Saya akan mengatakan bahwa bahkan karakter cisgender saya yang heteroseksual cenderung menumbangkan peran gender tradisional dalam beberapa cara,” katanya. “Sekali lagi, tampaknya lebih alami bagi saya untuk memasukkan karakter dengan hubungan yang bervariasi dengan gender dan seksualitas yang berbeda daripada menulis secara eksklusif atau terutama tentang orang lurus.”
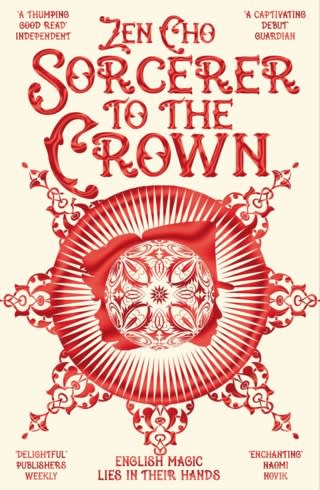 Novel fantasi sejarah Zen Cho tahun 2015 “Sorcerer to the Crown” berlatar di Regency London. (Dok. Zen Cho)
Novel fantasi sejarah Zen Cho tahun 2015 “Sorcerer to the Crown” berlatar di Regency London. (Dok. Zen Cho)
Dalam “Black Water Sister,” Jess harus menegosiasikan perbedaan antara pendidikan modernnya di Amerika dan identitas Malaysia yang baru terungkap, karena mengetahui bahwa menjadi lesbian dapat menghancurkan hubungan dengan keluarganya. Ini adalah salah satu cara Zen Cho menunjukkan bahwa kelompok etnis Malaysia perlu terlibat dengan sejarah mereka “untuk melewati komunalisme.”
“Begitu banyak wacana publik kami didasarkan pada ketakutan dan penilaian; pada menghindari nuansa; tentang menjadikan satu pihak sebagai korban dan pihak lain sebagai penindas, sambil menghapus banyak kelompok marjinal yang dieksploitasi Malaysia untuk keuntungannya,” kata Zen Cho, menambahkan bahwa penulis Malaysia menderita “terputus dari sejarah kita.”
“Ini tidak seperti sastra Malaysia dalam bahasa Inggris yang baru mulai ditulis pada tahun 2000-an, tetapi karya-karya sebelumnya relatif tidak dapat diakses,” kata Zen Cho. “Jauh lebih mudah untuk mengambil, katakanlah, seorang Jane Austen di toko buku Malaysia daripada buku lokal penting seperti ‘Green is the Colour’ Lloyd Fernando, atau karya penulis KS Maniam.”
Zen Cho juga percaya, bagaimanapun, bahwa skena sastra Inggris berkembang di Malaysia, dan prospeknya bagus. “Yang ingin saya lihat adalah lebih banyak penulis yang berbasis di Malaysia dan lebih banyak penulis non-Cina yang diterbitkan secara internasional.”
Sementara itu, Joshua Kam dan Zen Cho telah meletakkan dasar bagi penulis Malaysia dan Asia Tenggara lainnya untuk membangun penggambaran yang lebih jujur tentang sejarah dan keragaman gender mereka sendiri. “Saya memikirkan orang-orang queer pemberani di Myanmar yang dalam banyak hal memimpin aksi protes hari ini,” kata Joshua Kam. “Kami selalu di sini. Kami akan selalu begitu.” (R.A.W)
Sumber:







