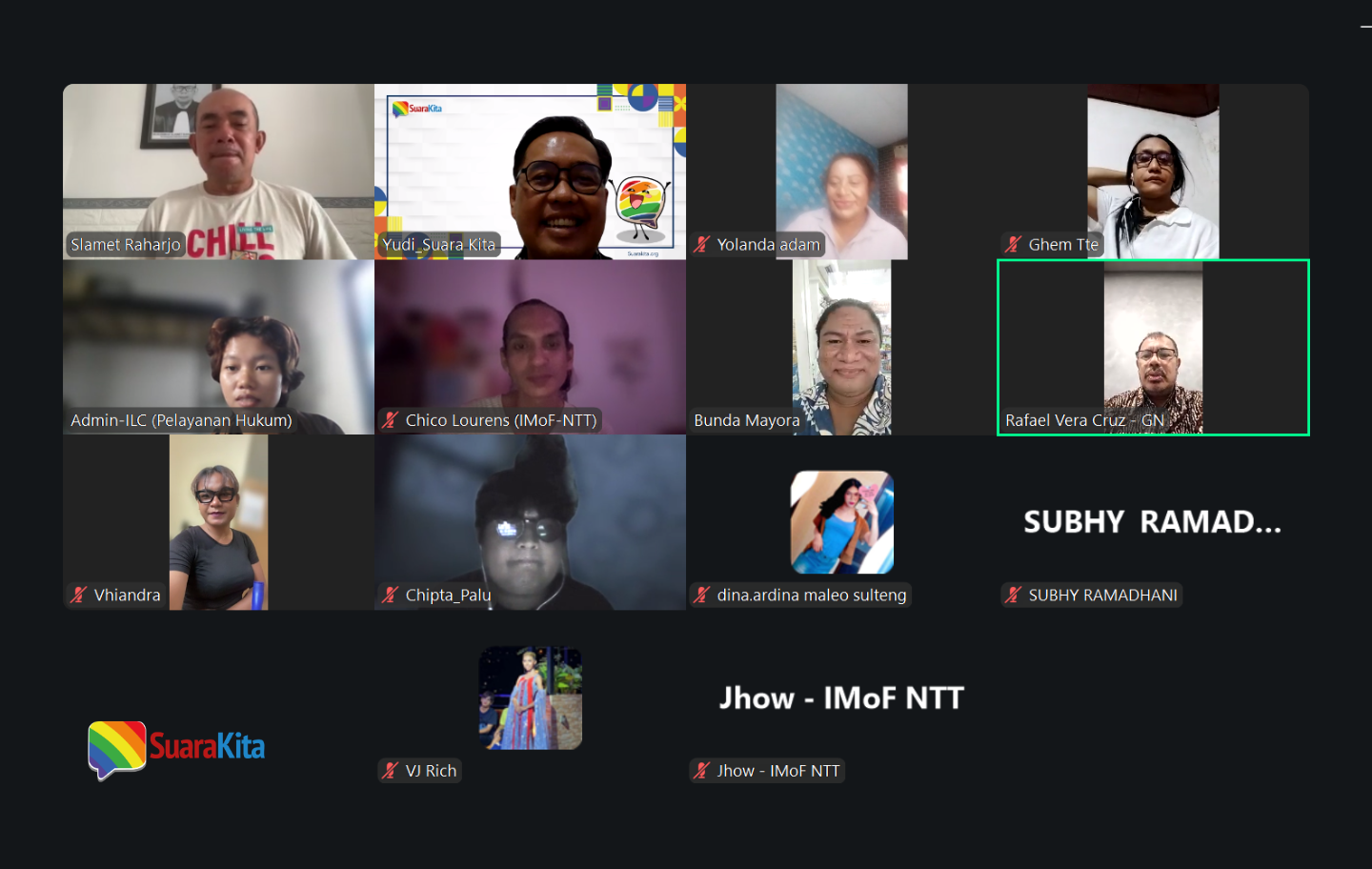SuaraKita.org – Tanggal 26 November 2016 lalu, Suara Kita menghadirkan Erasmus Napitupulu dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk membicarakan dimana posisi hukum pidana untuk kelompok minoritas, khususnya pada LGBT.
“Apakah hukum pidana kita dirancang khusus untuk melindungi hak-hak kelompok LGBT? Adakah dalam KUHP undang-undang yang secara khusus melindungi kelompok LGBT? Itu pertanyaan yang paling mendasar.” Tutur Sarjana lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Menurut analisis Erasmus, undang-undang anti diskriminasi yang kita punya sekarang masih menggunakan pola pikir kebergaman ras, “Jadi memang ada perbedaan sedikit. Jadi diskriminasi yang di undang-undang itu konteksnya ras. Bukan identitas seksual.”
“Berikutnya, apakah KUHP kita mengakui kehadiran LGBT? Pertama, saya akan bilang bahwa KUHP ini buatan Belanda. Belanda, pada saat itu, LGBT tidak dikenal sebagai golongan, melainkan hanya aktifitas seksual. Pemikiran kuno ini sebenarnya masih terbawa sampai saat ini. Orang-orang memahami konteks LGBT hanya sepanjang aktifitas seksual. Ini menjadi persoalan karena ini adalah pemikiran lama.”
“Jadi sebenarnya peraturan yang melindungi anak dari perbuatan sesama jenis itu adalah untuk melindungi anak dari perbuatan yang sifatnya non-heteroseksual. Karena logikanya dulu itu, jika cabul dengan seseorang, sudah dipastikan pencabulan itu dengan lawan jenis. Jadi undang-undang tersebut bukan melindungi anak-anak dari orang-orang dengan identitas homoseksual, tetapi dari perilaku seksual homoseksual. Sederhananya, peraturan itu tidak ditujukkan untuk ‘identitas homoseksual’ melainkan untuk ‘perilaku homoseksual’. Pertanyaan berikutnya, apakah perilaku homoseksual ini hanya dilakukan oleh orang yang homoseksual? Dan setelah itu, bagaimana cara pembuktiannya?”
Iman, salah satu peserta kita menjawab pertanyaan tersebut, “Banyak kasus mereka dipukuli terlebih dahulu supaya mengaku.”
“Di Aceh, kebanyakan kasus seperti itu. Kalo menurut saya, logika sederhananya, jika digrebek dan tidak terbukti salah, tuntut balik saja ke negara. Jadi menurut saya, mengapa pasal itu akan menjadi pasal mati karena saya gak bisa membayangkan bagaimana cara polisi dan jaksa membuktikannya. Pemerkosaan itu sulit untuk dibuktikan, kita harus benar-benar melihat adanya penetrasi yang terjadi.” Tutur Erasmus.
Penanya lain bernama Kartika mengatakan, “Penggrebekan itu sendiri kan sebenarnya mengganggu privasi kita, ya? Kita kan punya hak untuk mempunyai privasi.”
Pertanyaan berikutnya muncul dari iman lagi, “Sejauh mana sih negara itu boleh masuk ke ranah privasi seseorang?”
“Dalam hukum pidana, negara bisa menarik ruang privasi menjadi ruang publik. Caranya adalah dengan mengkriminalisasi sebuah perbuatan. Contohnya undang-undang pornografi, ketika merekam hubungan badan yang awalnya bukan pidana, dan kemudian dinyatakan sebagai pidana, maka negara punya kewenangan untuk masuk ke dalam privasi warga negara itu. Maka dari itu dalam keputusan MK disebutkan, ‘sepanjang untuk kebutuhan pribadi, maka tidak bisa dipidanakan’. Tapi kemudian pertanyaannya, sejauh mana suatu perbuatan itu sehingga bisa dikriminalisasikan? Banyak teori tentang ini, namun pada dasarnya adalah, harus ada korban. Semakin minim korbannya, maka kebutuhan mengkriminalisasi itu menajdi tidak penting. Intinya adalah, kalau misalkan perbuatan itu sifatnya sangat privasi, lalu tidak ada kebutuhan dan tidak ada tujuan untuk apa dia dikriminalisasi, maka kriminalisasi itu tidak diperlukan. Maka harus ditanya dulu, tujuan mengkriminalisasikan sebuah perbuatan itu apa? Ini yang selalu gagal dijawab oleh pemerintah.” Jawab Erasmus.
“Ketika kriminalisasi tidak dibutuhkan, maka di situ ada ruang privat yang dikembalikan. Karena semakin banyak aturan pidana, maka semakin banyak pula warga negara yang dibatasi. Banyak orang yang ingin mengkriminalkan segala hal, sebenarnya dia sedang mempertaruhkan lehernya sendiri, sadar atau tidak sadar.” (Esa)