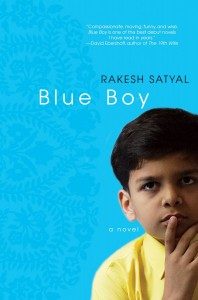
Oleh : Sebastian Partogi*
Pada umumnya, novel novel dengan genre cerita coming of age (yang menggambarkan perjalanan seseorang menuju kedewasaan emosional dan spiritual) sangat bersifat heteronormatif. Novel-novel seperti Catcher in the Rye karya J.D. Salinger dan Goats karya Mark Jude Poirier, misalnya, biasanya menampilkan tokoh laki-laki, heteroseksual dan maskulin, dan bagaimana para tokoh ini bisa mengatasi sifat kekanak-kanakan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang.
Novel-novel coming of age dengan tema yang androsentris dan heteronormatif tentu saja tidak menampilkan perjuangan tokoh yang termarjinalkan karena dalam masyarakat dunia yang cenderung bercorak patriarkal, para laki-laki muda tersebutlah yang mendapatkan semua keuntungan dan privilese dari masyarakatnya. Laki-laki ini berjuang untuk dapat mengatasi ekses-ekses dari ekspresi maskulinitas mereka yang berlebihan. Ambil contoh novel Goats. Dalam novel ini, si tokoh utama, Ellis, seorang laki-laki berusia 14 tahun berjuang untuk mengatasi perilaku-perilaku agresif dan destruktif seperti kebiasaan merokok ganja, kecenderungan untuk terlibat perkelahian fisik dengan orang lain dan kata-kata yang vulgar – semuanya merupakan cerminan hipermaskulinitas masyarakat patriarkal, untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijak.
Namun menarik untuk dicatat bahwa dalam novel ini, kedewasaan bukan berarti menanggalkan kekuasaan patriarki seutuhnya untuk dapat berpihak pada pihak yang dimarjinalkan (seperti perempuan dan kaum homoseksual). Pada akhir cerita, meskipun si tokoh sudah bisa mengatasi sifat agresif dan kekanak-kanakannya, ia tetap saja bersifat seksis dan homofobik. Jelas sekali bahwa novel coming of age yang tipikal justru melanggengkan dominasi maskulinitas dan kaum heteroseksual ketimbang berupaya menggoyang norma-norma tersebut dengan menyajikan narasi alternatif mengenai tokoh yang dimarjinalkan.
Ada angin segar bagi orang-orang yang sudah muak dengan eskpresi maskulinitas eksesif nan vulgar yang ditonjolkan dalam novel-novel coming of age tipikal: ada sebuah novel yang menggambarkan perjuangan yang harus dijalani oleh seorang laki-laki 12 tahun yang memikul beban marjinal berlapis: pertama, ia adalah seorang imigran dari India di Amerika Serikat, dan kedua, ia adalah seorang gay feminin.
Novel tersebut berjudul Blue Boy karya Rakesh Satyal (Kensington Books, 2009). Novel ini mengikuti perjalanan hidup seorang bocah laki-laki bernama Kiran Sharma. Sebagai seorang laki-laki, Kiran adalah seorang anomali: ia lenggak-lenggok saat sedang berjalan, kadang sering berjoget sendiri sambil menyanyikan lagu-lagu Whitney Houston dengan suara cempreng seperti perempuan di sekolahnya. Ia sangat payah dalam hal olahraga, ia bahkan tidak bisa bermain bola basket. Ia juga sering menggunakan perangkat make-up milik ibunya secara diam-diam saat sedang mengunci diri di kamar mandi. Intinya, ia tidak seperti anak laki-laki “normal”.
Kiran juga adalah seorang homoseksual: saat sedang membuka majalah porno Penthouse dalam acara menginap bersama dengan teman-temannya, ia menyadari bahwa dirinya lebih tertarik pada tubuh laki-laki telanjang yang digambarkan dalam majalah itu, ketimbang pada tubuh perempuan – yang di’lahap’ dengan antusias oleh teman-teman laki-lakinya yang heteroseksual. Identitas ini berusaha ia tutup-tutupi dan memang tidak pernah terbongkar ke muka umum di sepanjang cerita novel. Nonkonformitas sang tokoh utama atas peran gender yang diharapkan darinya, yaitu sifat maskulin, menjadi penyebab utama mengapa ia menjadi berbeda, kemudian dikucilkan dan didera.
Kiran sendiri tidak mengerti mengapa ia berbeda. Yang ia tahu adalah, ia bahagia menjalani peran sebagai laki-laki yang tidak konvensional. Namun, sayangnya, bocah-bocah lain, yang pada usia muda telah dicuci otaknya oleh masyarakat patriarkal yang menjunjung tinggi nilai-nilai maskulinitas, selalu mendera Kiran dengan berbagai macam hinaan menyakitkan, sebagai ‘banci’, ‘orang aneh’ dan sebagainya, dan menolak untuk berteman dengannya hanya karena ia berbeda.
Saat bocah-bocah berkulit putih menghina Kiran karena ia adalah orang India dan karena ia sangat feminin, teman-temannya sesama imigran India sama sekali tidak bisa menyediakan tempat berlindung yang aman di mana Kiran bisa merasa diterima dan dihargai secara apa adanya dan justru menunjukkan sikap sedingin es. Sesama bocah India ini pun menggunakan mulut mereka sebagai proyektil yang memuntahkan ratusan peluru tajam – berupa hinaan terhadap Kiran dan betapa aneh dirinya. Persis di sinilah konflik dalam cerita ini muncul: sifat alamiah Kiran mengalami benturan dengan masyarakat sekitarnya. Meskipun Kiran memiliki beberapa teman yang juga adalah ‘anak culun’ di sekolah, hinaan dan penolakan mayoritas anak-anak yang ia temui tersebut tetaplah menyakitkan.
Menemui dirinya sendiri tanpa pijakan yang jelas, Kiran menjadi alien di sekolahnya dan alien di komunitas imigran India dimana orangtuanya bergabung. Dalam sebuah upaya untuk mempertahankan kewarasannya di tengah benturan prasangka masyarakat yang edan, ia akhirnya menciptakan sebuah ilusi. Kiran kemudian mulai percaya bahwa kutukan yang saat ini sedang ia alami saat ini sebetulnya merupakan pertanda dari suatu hal yang lebih besar: bahwa ia sebetulnya adalah titisan dewa Krisna dan ia sedang mengalami inisiasi untuk mencapai kesempurnaan yang diperlukan oleh seorang ksatria. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari realita yang menyakitkan dan tidak dapat dimenangkan adalah dengan menciptakan dunia khayalan.
Namun, khayalannya tersebut tidak dapat menolongnya dari putaran nasib yang tidak menyenangkan: saat kedua orangtuanya mengetahui tentang kebiasaan Kiran menggunakan perangkat kosmetik perempuan, mereka betul-betul berang. Kedua orangtuanya, yang notabene telah termarjinalkan sebagai kaum imigran, merasa telah berupaya keras untuk mengangkat harkat dan martabat mereka di tanah perantauan. Perilaku anak mereka yang tidak konformis terhadap gender tersebut dianggap telah menjadi setitik racun yang telah mencemari reputasi sosial mereka.
Pada titik dimana orangtuanya sudah tidak dapat diandalkan lagi, Kiran harus mengambil pilihan dimana ia harus benar-benar melepaskan diri dari dunia sekitarnya dan menyublim dengan aktivitas yang sangat ia cintai: seni tari dan musik. Ia berlatih keras untuk tampil dalam acara pentas seni tahunan sekolah dan memukau banyak orang dengan energi yang ia tampilkan. Nahas, ia pingsan di tengah pertunjukan. Di rumah sakit diketahui bahwa Kiran menderita kelelahan fisik dan nutrisi yang tidak seimbang. Insiden sakitnya Kiran ini membantunya berdamai dengan kedua orangtuanya.
Sayangnya, kedua orangtuanya tidak serta merta merangkul Kiran dengan semua sifat femininnya. Hal tersebut hampir tidak pernah disentuh ataupun dibicarakan. Peristiwa ini senada dengan pengamatan sosiolog Steven Seidman (2002) bahwa meskipun banyak keluarga yang sudah toleran dengan nonkonformitas gender yang ditunjukkan oleh anggota keluarga mereka, namun mereka tetap memilih untuk menyapu nonkonformitas tersebut ke balik karpet. Sebagai hasilnya, meskipun mereka mungkin tidak dibuang atau disiksa oleh keluarga mereka, laki-laki feminin atau homoseksual tetap tidak bisa mengekspresikan gender mereka di dalam keluarga. Mereka hanya diterima selama aspek “tidak normal” dari diri mereka tersebut disembunyikan dan tidak ditampilkan di depan anggota keluarga.
Namun, rentetan peristiwa yang akhirnya memaksa Kiran untuk mengandalkan dirinya sendiri dalam upaya menjadi penyintas dalam lingkungan yang sangat tidak ideal kemudian telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang dan kuat. Ia tidak perlu lagi bersedih hati memikirkan pendapat orang lain tentangnya. Ia telah menemukan hasratnya, yaitu kesenian, dan bisa menciptakan kebahagiannya sendiri persetan dengan orang lain. Namun tetap saja, pengalaman di-bully, ditolak dan dikucilkan – apalagi hanya karena orang yang bersangkutan memiliki identitas seksual yang dianggap “menyimpang” – akan menjadi suatu hal yang sangat tidak menyenangkan dan akan terpatri dalam benak seorang individu seumur hidupnya.
Tahun 2001 di SMP Katolik Mater Dei, Pamulang, Tangerang Indonesia. Ada seorang bocah lelaki yang sangat feminin seperti Kiran Sharma. Sama seperti Kiran, bocah tersebut juga berusia 12 tahun, senang melenggak-lenggokkan pinggulnya sambil menyanyikan lagu-lagu Madonna. Bedanya, bocah tersebut tidak suka menggunakan make-up. Bocah tersebut selalu didera secara fisik, verbal dan sosial oleh murid-murid lain – kata kata seperti banci, bencong bertitit sudah tidak asing lagi di telinganya. Pernah juga suatu hari, genitalnya ditendang keras oleh seorang murid berbadan besar bernama Christian Halim – yang namanya sama sekali tidak mencerminkan sosok Kristus yang penuh belas kasih, terutama bagi orang yang dianggap menyimpang atau berdosa. Puji Tuhan yang maha kuasa, bocah tersebut masih hidup sampai saat ini dan telah menemukan kebahagiaan. Bocah tersebut bernama Sebastian Partogi, atau biasa dipanggil Ogi.
Semoga dengan terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan terbuka terhadap keberagaman, termasuk keberagaman ekspresi gender dan seksual, akan semakin sedikit Kiran-Kiran dan Ogi-Ogi yang harus menderita didera hanya karena mereka berbeda.
Referensi
–Poirier, M.J. (2002) Goats. New York: Hyperion Books
-Satyal, R. (2009) Blue Boy. New York: Kensington Books
-Seidman, S. (2002) Beyond the Closet: The Transformation of Gay and Lesbian Lives. London: Routledge.
*Penulis bekerja di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, dimana ia bertugas sebagai promotional copywriter dan reporter.






