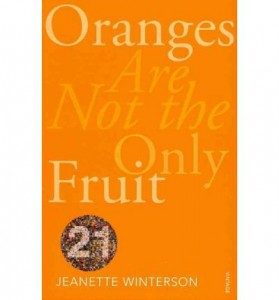
Oleh: Sebastian Partogi*
Suarakita.org- Banyak sekali individu homoseksual yang menghadapi dilema yang sulit: antara cinta dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa cinta sesama jenis adalah suatu hal yang terlarang, hina dan merupakan pengaruh Setan.
Dilema ini seringkali memaksa kaum homoseksual untuk membuat pilihan yang sulit: (1) entah harus melakukan kamuflase dengan menjalani hidup sebagai heteroseksual dengan cara menikahi lawan jenis dalam pernikahan tanpa hasrat atau (2) justru meninggalkan agama dan berpaling pada agnostisisme atau ateisme karena merasa tidak mendapatkan tempat lagi dalam agama.
Pilihan pertama, selain membuat si homoseksual tidak bahagia, juga akan membuat pasangan heteroseksualnya menderita karena dipaksa hidup di dalam kebohongan. Contohnya adalah kasus Eric Myers yang terpaksa menjalani kehidupan heteroseksual dengan seorang perempuan, lalu kemudian menghilang selama belasan tahun. Setelah dinyatakan meninggal, Eric malah muncul lagi dengan seorang pasangan sesama jenis. Bayangkanlah kalau Anda adalah anak-anak dan istri Eric, tentu saja Anda akan merasa sangat sakit hati dan dikhianati. Kepalsuan akhirnya menghancurkan semua pihak.
Dalam kasus perempuan lesbian, pernikahan heteroseksual yang dipaksakan dapat diwarnai oleh tindakan kekerasan yang mengerikan. Ingatkah Anda pada kasus orangtua seorang lesbian yang memerintahkan menantu laki-laki mereka untuk memperkosa anak mereka dalam malam pengantin agar ia kembali “normal”? Dalam masyarakat kita yang patriarkis ini, dimana laki-laki selalu diistimewakan untuk melakukan kekerasan, maka bisa dikatakan bahwa perempuan lesbian berada dalam posisi yang lebih rentan dan termarjinalkan dibandingkan lelaki gay.
Bicara tentang perempuan lesbian, novel Oranges are not the Only Fruit karya Jeanette Winterson (Pandora Press, 1985; diterbitkan kembali oleh Vintage pada tahun 2012) mengisahkan tentang seorang perempuan lesbian yang memilih opsi kedua: meninggalkan gereja (dan juga keluarganya) karena merasa tidak mampu mendamaikan antara seksualitas dan agamanya.
Jeanette adalah seorang lesbian yang berusaha menemukan jati diri dan cintanya ditengah kungkungan komunitas misionaris Protestan yang sangat konservatif dan ortodoks.
Jeanette diadopsi oleh ibunya untuk menjadi seorang misionaris yang menyebarkan ajaran Tuhan dan menyelamatkan banyak orang “sesat” dengan membuat mereka memeluk Kekristenan, agama keselamatan sejati.
Kehidupan spiritual gereja menjadi kurang indah saat kita dicekoki dengan penalaran moral yang sifatnya hitam-putih. Hal serupa juga terjadi pada Jeanette. Ibunya mengklasifikasikan semua hal ke dalam dua kutub: teman dan musuh.
Akar dari semua musuh manusia adalah Setan. Salah satu perwujudan musuh adalah seks (dalam berbagai bentuknya). Sementara teman adalah Tuhan dan hidup dalam kekudusan.
Dalam sebuah adegan novel yang lucu, ibu Jeanette menutup telinga anak angkatnya saat tetangga mereka sedang mengeluarkan suara aah aah aah yang – tebak saja sendiri – pasti merupakan suara orang yang sedang bersenggama. Beberapa saat setelah insiden tersebut, Jeanette mempertanyakan apakah seks betul-betul hina seperti yang dikatakan ibunya. Orang selalu melakukan dosa secara diam-diam, pikir Jeanette. Kalau memang seks itu dosa, mengapa orang melakukannya dengan begitu berisik?
Jeanette telah sadar sejak masih muda bahwa ia tidak pernah tertarik pada laki-laki. Ia tidak bisa membayangkan dirinya menikah dengan seorang laki-laki, sama seperti ia tidak bisa membayangkan dirinya menikahi seekor babi.
Suatu hari ia bertemu dengan Melanie, seorang perempuan yang sebelumnya tidak memeluk agama Kristen namun telah ia “selamatkan” dan bawa masuk ke dalam gereja. Ia selalu merasa ingin dekat dengan Melanie dan mengatakan pada sang ibu mengenai cinta yang ia rasakan. Ibunya langsung terkejut dan memanggil seorang pendeta ke rumah untuk “menangani” Jeanette.
Sang pendeta mengatakan bahwa cinta Jeanette adalah produk Setan. Jeanette kemudian membatin, menurutku, cinta ini bukan berasal dari Setan. Namun keyakinan sang ibu dan pendeta tidak berkurang sedikitpun. Mereka melakukan beberapa ritual pengusiran setan pada Jeanette, sang ibu bahkan mengurungnya dalam sebuah ruangan gelap. Namun demikian, seberapa keras pun mereka berusaha, si “setan” tidak pernah meninggalkan tubuh Jeanette: ia tetaplah seorang lesbian.
Sang ibu kemudian bertambah neurotik saat sadar bahwa seksualitas anaknya tidak bisa diubah. Ia kemudian mengatakan bahwa Jeanette adalah sumber penyakit yang mengotori kesucian gereja dan rumahnya. Jeanette, yang dulunya sering berkhotbah di gereja, tidak lagi diperkenankan untuk melakukan hal tersebut. Lebih jauh lagi, larangan bagi Jeanette untuk berkhotbah kemudian diberlakukan pada semua perempuan. Firman Tuhan hanya boleh disampaikan oleh laki-laki, kata sang ibu dan pak pendeta.

Jeanette, yang semakin muak dengan gereja yang semakin konservatif, kemudian mengatakan pada sang ibu dan pak pendeta, aku tidak mau lagi pergi ke gereja. Saat sang ibu bertanya padanya: apakah kau mau bertobat?, Jeanette mengatakan tidak. Saat itulah sang ibu kemudian mengusirnya dari rumah dengan alasan bahwa ia tidak mau ada setan tinggal di dalam rumahnya.
Jeanette kemudian pergi meninggalkan rumahnya, mencoba memperoleh penghasilan hidup dari berbagai pekerjaan mulai dari perias jenazah sampai tukang jualan es krim. Suatu hari ia berpapasan dengan Melanie, yang ternyata sudah tidak ingin melanjutkan hubungan cinta dengannya. Jeanette kecewa.
Suatu hari, Jeanette memutuskan untuk menjenguk ibunya di rumah. Sebelum ia mengunjungi ibunya, ia sempat merenung. Dalam perenungannya itu ia merindukan sosok Tuhan yang datang untuk membersihkan dosa-dosanya. Dalam perenungannya itulah ia menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan yang maha pengasih ternyata tidak pernah mengecewakan dirinya. Menurutnya, pelayan-pelayan Tuhanlah – mulai dari pendeta sampai ke ibunya sang misionaris – yang telah berkhianat dan memelintir ajaran Tuhan atas nama agama.
Novel ini memiliki akhir yang cukup bahagia. Jeanette pulang dan mendapati ibunya kecewa kepada perkumpulan misionaris yang ia ikuti, yang telah dicemari oleh korupsi dan pendeta yang meninggalkan istrinya untuk ‘kumpul kebo’ dengan perempuan lain. Di akhir cerita, sang ibu yang sudah meninggalkan fundamentalismenya pun menerima Jeanette kembali ke rumahnya.
Novel Oranges bercerita tentang pilihan dan keyakinan – dan tentang bagaimana kita harus siap-siap untuk dikecewakan oleh pilihan yang kita ambil. Jeanette ditinggalkan kekasihnya dan sang ibu angkat dikecewakan oleh gereja. Dalam dilema antara homoseksualitas dan agama, mungkin ada baiknya jika kita sebagai manusia tidak terlalu fanatik pada sebuah kepercayaan (entah itu terhadap agama ataupun cinta) dan selalu siap untuk menerima perubahan dan membuka pikiran kita pada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita percayai.
*Penulis adalah wartawan harian berbahasa Inggris The Jakarta Post.






