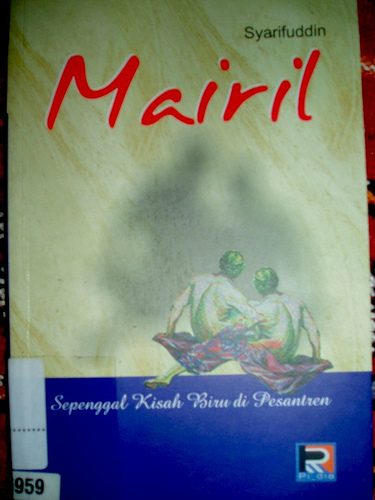Namun, siapa yang mengira di balik kentalnya nuansa agama yang ada di pesantren ternyata menyimpan cerita “lain” yang sangat berbeda dengan (doktrin) agama? Buku dengan judul Mairil, Sepenggal Kisah Biru di Pesantren yang ditulis oleh Syarifuddin ini mengungkap secara transparan homoseksualitas di dunia pesantren, terutama yang berkaitan santri.
Ibarat lokalisasi, pesantren sering dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat libido santri pada santri lain. Bedanya, kalau di lokalisasi berlaku hukum pasar, yaitu terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Di pesantren kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan umumnya dilakukan di tengah malam ketika “korban” sedang tertidur lelap.
Yang lebih menarik , praktik seperti ini dilakukan antarsesama jenis kelamin (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan). Seks antarsesama jenis kelamin inilah yang menjadi titik tekan buku ini. Di pesantren budaya ini bukanlah hal yang tabu, bahkan sudah mentradisi secara turun-temurun hingga kini. Sehingga sukar menghilangkan budaya itu karena sang pelaku dalam menjalankan aksinya sangat rapi, di luar pengetahuan orang lain.
Jangankan orang lain, kadang yang menjadi “korban” sendiri tidak menyadari kalau dirinya pernah dijadikan pelampiasan nafsu seks orang lain. Biasanya “korban” baru menyadari kalau dirinya telah menjadi pelampiasan seksual orang lain ketika bangun tidur. Karena hubungan seks ala pesantren bukan didasarkan suka sama suka tetapi secara sembunyi-sembunyi, ketika “korban” sudah terlelap.
Budaya itu kemudian dikenal dengan istilah nyempet dan mairil. Menurut penulis, nyempet merupakan jenis atau aktivitas pelampiasan seksual dengan kelamin sejenis yang dilakukan seseorang ketika hasrat seksualnya sedang memuncak, sedangkan mairil merupakan perilaku kasih sayang kepada seseorang yang sejenis (hlm. 25).
Perilaku nyempet terjadi secara insidental dan sesaat, sedangkan mairil relatif stabil dan intensitasnya panjang. Namun dalam banyak hal antara nyempet dan mairil mengandung konotasi negatif, yaitu sama-sama terlibat dalam hubungan seksual satu jenis kelamin.
Kondisi sosiologis dunia pesantren dengan pembinaan “moral” dan akhlak secara otomatis interaksi antara santri putra dan putri begitu ketat. Keseharian santri dalam komunitas sejenis, mulai bangun tidur, belajar, hingga tidur kembali. Santri bisa bertemu dengan orang lain jenis ketika sedang mendapat tamu. Itu pun jika masih ada hubungan keluarga.
Praktis, ketika ada di pesantren –terutama pesantren salaf (tradisional)– tidak ada kesempatan untuk bertemu dan bertutur sapa dengan santri beda kelamin.
Di samping tempat asrama putra dan putri berbeda, hukuman yang harus dijalankan begitu berat, bisa-bisa dikeluarkan dari pesantren, jika ada santri putra dan putri ketahuan bersama. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan perilaku nyempet di kalangan santri di pesantren begitu marak (hlm. 31).
Perilaku nyempet dan mairil biasnya dilakukan oleh santri tua (senior), tidak jarang pula para pengurus atau guru muda yang belum menikah. Dari hasil penelitian penulis, kegiatan nyempet hanya terjadi ketika masih menetap di pesantren tetapi ketika sudah lulus dari pesantren budaya seperti itu ditinggalkan.
Terbukti, kehidupan mereka “normal” dan tidak ditemukan kasus mereka menjadi homo atau lesbi. Mereka semua berkeluarga dan mempunyai anak. Karena orang yang melakukan itu hanya iseng bukan tergolong homoseksual (bagi kaum laki-laki) atau lesbian (bagi kaum wanita). Mereka melakukan seks itu sekadar menyalurkan libido seksualnya yang memuncak.
Umumnya yang menjadi “korban” nyempet dan mairil adalah santri yang memiliki wajah ganteng, tampan, imut, dan baby face. Hampir pasti santri (baru) yang memiliki wajah baby face selalu menjadi incaran dan rebutan santri-santri senior. Bahkan tidak jarang antara santri yang satu dan santri yang lain terlibat saling jotos, adu mulut, bertengkar (konflik) untuk mendapatkannya.
Di pesantren berlaku hukum tidak tertulis yang harus dijalankan bagi orang yang memiliki mairil. Misalnya jika si A sudah menjadi mairil orang, maka si mairil tersebut akan dimanja, diperhatikan, diberi uang jajan, uang makan, dicucikan pakainnya, dan sebagainya; layaknya sepasang kekasih (pacaran). Jika si mairil dekat dengan orang lain pasti orang yang merasa memiliki si mairil tersebut akan cemburu berat.
Kelebihan buku ini adalah penulis mampu menceritakan pelaku nyempet dan mairil dalam suasana santai, kocak, tetapi serius. Gaya penulisanya bertutur hampir menyerupai novel. Misalnya ketika penulis menceritakan tentang santri bernama Subadar yang akan nyempet santri lain.
Di beranda joglo masjid tanpa penerangan lampu, Subadar sambil berpura-pura tidur, terus merangsek mendekati santri yang masih kecil yang beberapa hari terakhir menjadi incarannya. “Harus bisa,” gumam Subadar dalam hati.
Namun naas nasibnya kali ini, baru saja mulai angkat sarung korban, tiba-tiba lampu beranda joglo dinyalakan petugas piket yang seketika itu membuat Subadar terkejut bukan kepalang…
Penulis buku ini tentu paham betul tentang budaya nyempet dan mairil yang ada di pesantren. Karena dia juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren Wonorejo dan Jombang, Jawa Timur.
Boleh dikatakan buku ini adalah hasil temuannya langsung saat dia hidup di dunia pesantren selama kurang lebih enam tahun lamanya. Membaca buku ini kita akan terkejut dan mengernyitkan dahi, “Ah yang bener aja.”
Meski peristiwa yang diceritakan dalam buku ini lebih mengandalkan inprovisasi penulis, pembaca bisa melacak sendiri bahwa peristiwa seperti ini dalam dunia pesantren, terutama saat malam menjelang, benar adanya. Atau boleh jadi mereka yang pernah dibesarkan di pesantren akan tersenyum kecut atau mengakui dan menyangkal peristiwa kebenaran cerita ini.
(Ditulis oleh Zamaahsari A. Ramzah, mahasiswa FISIPOL, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, alumnus Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)
Judul : Mairil, Sepenggal Kisah Biru di Pesantren
Penulis : Syarifuddin
Penerbit : P_Idea, Jogjakarta
Cetakan 1 : 2005
Tebal : viii + 254