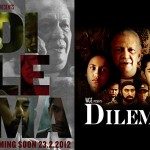 Hari ini,Kamis, 23 Februari 2012 sengaja saya mencatat untuk bisa menonton pemutaran perdana film “DILEMA”. Film ini garap oleh empat sutradara dengan menghasilkan lima film pendek, diantaranya bercerita tentang narkoba, lesbian, kelompok pro kekerasan atas nama agama, perjudian, sepak terjang polisi, broken home, pemilik modal dan kekuasaan. Kelima cerita tersebut berusaha disatukan menjadi satu cerita panjang, walau menurut penulis masih terkesan dipaksakan gabungan cerita tersebut. Film yang diproduserin oleh Wulan Guritno ini mencoba memotret kehidupan kota besar Jakarta.
Hari ini,Kamis, 23 Februari 2012 sengaja saya mencatat untuk bisa menonton pemutaran perdana film “DILEMA”. Film ini garap oleh empat sutradara dengan menghasilkan lima film pendek, diantaranya bercerita tentang narkoba, lesbian, kelompok pro kekerasan atas nama agama, perjudian, sepak terjang polisi, broken home, pemilik modal dan kekuasaan. Kelima cerita tersebut berusaha disatukan menjadi satu cerita panjang, walau menurut penulis masih terkesan dipaksakan gabungan cerita tersebut. Film yang diproduserin oleh Wulan Guritno ini mencoba memotret kehidupan kota besar Jakarta.
Seperti yang sudah saya sampaikan diawal, bahwa tujuan saya menonton film ini karena ada isu Lesbianis yang diangkat dalam film tersebut. Untuk isu kekerasan atas nama agama dan “kebobrokan” kerja kepolisian memang sangat tergambar dalam film tersebut. Dari mulai gambaran keterlibatan aksi kelompok garis keras atas nama Islam dengan kepolisian dan penguasa, sampai dilematis yang dialami oleh para anggota kelompok garis keras tersebut. Semua seperti realita yang terjadi sekarang, walau secara peran dan cerita masih “acak kadut”.
Walau film ini bertabur bintang, seperti Roy Marten, Slamet Rahardjo, Jajang C Noer, Ray Sahetapy, Tio Pakusadewo, Lukman Sardi dan Wulan Guritno, tetapi masih sangat terkesan kurang matang persiapan, baik dari segi cerita maupun pendalaman karakter. Sehingga kehadiran para bintang “besar” hanya sebatas bintang belaka, tidak kuat sama sekali karakternya.
Film memang berhasil meyampaikan pesan tentang beberapa hal, seperti kinerja polisi yang korup dan kelompok garis keras atas nama agama. Misalnya gerobak dangdut yang dianggap sebagai aksi pornografi dan kemudian dihancurkan oleh kelompok garis keras. Fenomena ini memang menjadi gambaran dari kelompok-kelompok garis keras yang ada di Jakarta, seperti Front Pembela Islam (FPI) yang selalu mengusung isu moralitas padahal sebenarnya hanya untuk kepentingan pemilik modal. Penegasan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, sehingga Tuhan tidak perlu dibela atas nama agama. Dialog-dialog seperti itu ada dalam film tersebut, termasuk juga isu Ahmadiyah tergambar dalam film tersebut.
Untuk isu Lesbian dalam film ini, saya berani katakan sangat buruk dari segi cerita dan substansi. Misalnya seorang Lesbian digambarkan sebagai perempuan yang benci atau punya trauma dengan laki-laki. Para perempuan yang mempunyai masalah terhadap narkoba, korban kekerasan rumah tangga sehingga menjadi Lesbian. Kemudian diperparah lagi kehidupan yang dekat dengan disko,narkoba, hedonisme yang dilekatkan pada perempuan Lesbian dalam film ini. Asumsi saya, film ini sepertinya kurang riset ataupun kajian mendalam tentang kehidupan Lesbian di Jakarta. Sehingga film ini sama sekali tidak punya keberpihakan pada hak-hak homoseksual khususnya Lesbian, hanya sebagai cerita “tempelan” belaka.
Berangkat dari semua cerita, mungkin menjadi refleksi bersama khususnya bagi para film maker. Bukan hanya soal uang dan teknis film yang perlu menjadi pertimbangan, tetapi substansi cerita dan pemaknaan peran menjadi sangat penting untuk membuat film bermutu. Sehingga aspek sosial,budaya, politik, ekonomi dan hak asasi manusia sangat perlu dilihat dalam sebuah film. Untuk bisa sampai kesana, harus dilakukan kajian secara mendalam, seperti mengumpulkan literatur dari tema cerita. Mulai membaca buku, diskusi fokus pada korban, aktivis ataupun pengambil kebijakan. Sehingga film yang dihasilkan mempunyai “isi”, baik dari segi cerita maupun pesan yang ingin disampaikan. Jadi tidak terkesan asal-asal atapun “galau” kata anak muda Jakarta. (Hartoyo-Ourvoice)






