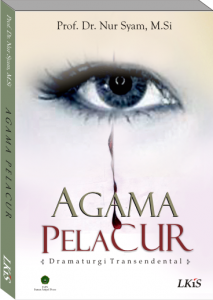 Ourvoice.or.id– Pustaka Pelangi adalah Perpustakaan yang dikelola oleh Our Voice yang memiliki koleksi buku-buku dengan berbagai tema diantaranya tentang : Gender, Seksualitas, Pluralisme, Sosial, Budaya dan lain-lain. buku berjudul “Agama dan Pelacur” merupakan satu dari sekian buku yang ada di Pustaka Pelangi. berikut ini ulasan buku yang diberi tajuk “Tuhan dibalik Pelacuran” yang dituliskan oleh : Musyafak Timur Banua koordinator komunitas Open Mind Community Semarang.
Ourvoice.or.id– Pustaka Pelangi adalah Perpustakaan yang dikelola oleh Our Voice yang memiliki koleksi buku-buku dengan berbagai tema diantaranya tentang : Gender, Seksualitas, Pluralisme, Sosial, Budaya dan lain-lain. buku berjudul “Agama dan Pelacur” merupakan satu dari sekian buku yang ada di Pustaka Pelangi. berikut ini ulasan buku yang diberi tajuk “Tuhan dibalik Pelacuran” yang dituliskan oleh : Musyafak Timur Banua koordinator komunitas Open Mind Community Semarang.
Judul : Agama Pelacur; Dramaturgi Transendental
Penulis : Prof. Dr. Nur Syam, M.Si
Penerbit : LKIS, Yogyakarta
Cetakan : I, Oktober 2010
Tebal : xvii+199
Dunia pelacuran ibarat panggung. Orang-orang yang terlibat di dalamnya hanyalah aktor yang dituntut memainkan perannya. Dan, masing-masing peran tidak diterima secara cuma-cuma, kecuali diatur oleh lingkaran kuasa yang bercokol di dalamnya. Celakanya, masyarakat terlanjur menerima panggung itu sebagai kebenaran yang nyaris mutlak, bahwa pelacuran adalah dunia kotor, lembah hitam, serta jauh dari Tuhan.
Stigma minus itu semakin memberikan represi berlapis kepada pelacur yang selama ini dicap sebagai pelaku utama. Padahal pelacur adalah subyek yang tidak berdiri sendiri, ia dibentuk dan dikendalikan oleh kekuasaan atau struktur yang multikompleks.
Di wilayah prostitusi, misalnya, pelacur dikurung oleh kuasa mucikari, broker, atau makelar. Pun ketika berhadapan dengan pengguna jasanya, pelacur hanya menjadi obyek seksual dan hanya menuruti tuntutan keinginan penggunanya. Banyaknya tuntutan, tidak hanya penampilan, tetapi juga cara melayani yang musti bervariasi sesuai kesenangan penggunanya, secara berangsur-angsur menjadikannya sebagai orang lain.
Melacur umumnya adalah sebuah keterpaksaan struktural yang terlanjur menjadi “pilihan”. Profesi ini bukanlah pilihan merdeka yang menyamankan. Keterbatasan akses ekonomi menjadi dalih utama untuk mencebur di dalamnya. Dunia pelacuran berhadap-hadapan dengan struktur-sistemik: Negara. Pelacur adalah korban dari relasi kekuasaan yang timpang, di mana ia terpinggirkan dari keterjaminan sosial-ekonomi hingga dengan terpaksa menjual tubuhnya. Selanjutnya, kapitalisme memanfaatkan tubuh perempuan sebagai komoditas sehingga pelacur tidak lebih hanyalah “buruh- budak” yang diperas untuk membubungkan keuntungan ekonomis.
Membincang pelacur dan dunia prostitusi, sama halnya mendialogkan relasi-relasi kuasa yang beragam mulai seksualitas, moralitas, religiusitas, sosialitas, feminitas, juga struktur kekuasaan formal (negara) yang menciptakan pelbagai anomali dan anomie—situasi tanpa arah, meminjam istilah Emile Durkheim.
Dramaturgi
Perlu kesadaran baru dalam memahami pelacuran. Pelacuran adalah sebuah dramaturgi yang musti ditilik dari pelbagai sisi demi memungkinkan pemahaman nostereotipikal-stigmatif yang tidak makin merugikan pelacur. Pelacuran adalah realitas yang relatif, sehingga penghakiman biner secara benar-salah menjadi kurang memadai.
Di mana-mana pelacur dicaci, tetapi juga dinanti. Sesuatu yang dianggap busuk dan kotor itu nyatanya terbukti sebagai kebutuhan masyarakat hingga berkembang menjadi terbuka dan legal, meski masih banyak yang sembunyi-sembunyi.
Buku Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental karya Nur Syam, menjadi sebuah ikhtiar untuk merumuskan kesadaran baru itu. Sebuah kajian sosiologis tentang dunia pelacur yang mengambil latar metropolitan Surabaya seperti Lokalisasi Dolly, Jagir Wonokromo, Moroseneng, Bangunsari, Bangunrejo, Kremil, dsb. Buku ini hendak menekankan fakta spiritualitas dan keberagamaan para pelacur, seraya menepis anggapan masyarakat bahwa pelacuran adalah wilayah yang jauh, bahkan terceraikan, dari Tuhan.
Erving Goffman, sosiolog asal Canada, mengembangkan teori dramaturgi untuk menyingkap interaksi simbolik individu dan masyarakat. Goffman merumuskan subyek sebagai ketegangan antara “I” dan “Me”, yakni ketidaksesuaian antara “diri manusiawi” dengan “diri hasil sosialisasi”. Perbedaan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang diharapkan orang lain secara terus-menerus menggandakan ketegangan diri. Dalam pada itu, subyek memiliki pilihan untuk bertindak di panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage).
Di panggung depan, pelacur tampak tidak mempersoalkan urusan moral, agama, maupun Tuhan. Sebab panggung depan itu memang tidak ramah untuk kehadiran Tuhan, apalagi mengekspresikan keberagamaan. Namun, panggung belakang bisa jadi adalah antitesis dari semua itu. Ibarat ruang ganti yang tidak boleh diintip oleh siapa saja, di panggung belakang itu pelacur berusaha menemui dirinya sendiri: merefleksikan kehendak diri dan keinginan pelanggan. Dan, di antara dua panggung itu sebenarnya ada ruang ketiga, sebuah ruang residual yang memungkinkan pelacur menjadi dirinya sendiri.
Di ruang residual itulah Tuhan hadir. Nama Tuhan masih kerap didaras, meski lirih dan sayup, di bilik-bilik pelacuran di waktu senggang. Tuhan hadir dalam bentuk yang subjektif dan impersonal. Spiritualitas dan keberagamaan pelacur sudah lepas dari simbol-simbol normatif agama seperti masjid, gereja, kuil, dsb. Tuhan diperam dalam jiwanya sendiri sehingga tertutup kemungkinan bagi orang lain untuk memahaminya. Dan, Tuhan lebih kerap hadir di dalam diri pelacur seolah bayangannya sendiri yang hitam. Semacam perasaan dina dan rasa dikejar-kejar dosa. Di sisi lain, Tuhan juga hadir membawa kedamaian dan rasa aman: pelacur mengimani Tuhan sebagai dzat Mahakasih yang selalu bisa mengampuni dosa-dosanya.
Kiranya, dunia pelacuran yang kasat mata adalah dunia anonim. Pelacur tidak hadir dengan dirinya, melainkan berperan sesuai tuntutan yang tidak semata-mata keinginan diri sendiri. Dan, Tuhan lebih tahu segalanya!






