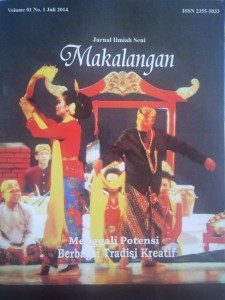
(Foto : Wisesa/Suara Kita)
Oleh: Wisesa Wirayuda*
Suarakita.org- Kita tidak bisa menyangkal, masyarakat sekarang ini masih saja beranggapan bahwa waria hanya bisa mencari nafkah di malam hari (nyebong), sebuah pekerjaan yang dianggap tidak “layak” oleh masyarakat. “Disebutkan bagian terbesar kaum waria menggantungkan diri pada kehidupan malam, hal itu maka menimbulkan satu anggapan bahwa dunia waria diidentikkan dengan pelacuran (Moerthika, t.t:172-175).
Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada juga waria yang lebih memilih bekerja di jalanan. Faktornya bisa bermacam-macam, pendidikan salah satunya, yang menurut hemat saya itu juga terjadi dikarenakan kurangnya penerimaan dari masyarakat itu sendiri. Atau bisa disimpulkan, masyarakat menuntut seorang waria untuk tidak bekerja di jalanan namun mereka juga tidak ingin menerima waria-waria ini untuk bekerja. Sungguh anekdot yang keterlaluan.
Dalam tesisnya ini, Yayat menyampaikan hal yang senada. “Di dunia pelacuran itu pula mereka menemukan dirinya sendiri untuk kemudian terus menjadi pelacur atau berhenti untuk beralih pekerjaan non pelacuran.” (Halaman 67)
Namun apa jadinya jika seorang waria merasa bahwa kehidupan malamnya harus ditinggalkan dan mencari pekerjaan lain yang dianggap “layak” di mata masyarakat?
Melalui tesisnya yang berupa karya tari dengan judul Panggil Aku Yessy ini, Yayat Hidayat membagikan pengalaman empirik dirinya yang pernah “menjadi” waria dan bekerja di jalanan sebelum kini dirinya menjadi dosen, perias pengantin, dan pemilik sanggar busana.
Sungguh sangat disayangkan, Yayat menggunakan sumber-sumber lama. Sehingga data yang diperoleh masih bias dan justru menjatuhkan martabat waria itu sendiri. Salah satunya, “Seperti yang dikatakan Tony S. Djadja Kusumah (1994), secara biologis psikologis, waria adalah seorang yang mengalami gender identity disorder atau gangguan identitas jenis kelamin; merasa sebagai wanita yang terperangkap dalam tubuh pria. Hal itu menyebabkan hingga saat ini dunia waria masih sulit diterima di dalam masyarakat.” (Halaman 66)
Saya menggaris bawahi kata “Identity Disorder”. WHO sendiri dalam penjelasannya mengenai Transgender tidak sama sekali mengatakan bahwa itu adalah sebuah gangguan identitas. Melainkan, “Orang-orang yang identitas gendernya dan ekspresinya tidak sesuai dengan norma dan ekspetasi, biasanya berkaitan dengan jenis kelamin yang diberikan kepada mereka pada saat mereka lahir.”[1]
Kemudian Yayat juga menggunakan kata “normal” dalam penjelasnnya mengenai konflik psikologis yang dialami oleh waria, “Hal ini menimbulkan konflik psikologis dalam dirinya. Mereka mempresentasikan perilaku yang jauh berbeda dengan pria normal, tetapi bukan sebagai wanita yang normal pula.” (Halaman 66)
Banyak sekali yang saya garis bawahi, terutama penjelasan mengenai waria itu sendiri yang menurut saya sangat bias, namun dikarenakan tesis ini berdasarkan pengalaman pribadi dari Yayat, sehingga saya juga tidak bisa mengatakan bahwa “ini salah” atau “itu benar” dikarenakan memang fakta di lapangan, atau khususnya yang dialami Yayat, memang seperti demikian.
Sajian yang ditampilkan oleh Yayat adalah berupa teater tari, dimana ada garapan koreografinya dan juga ada garapan teatrikalnya. Dalam garapan teatrikalnya, Yayat memasukkan dialog-dialog yang sekaligus mengkritik masyarakat. Salah satu dialog itu berbunyi:
Yessy : ….. Eh denger-denger lelekong sekarang pada Munawir sajali yey.
Ara : Apa Munawir sajali teh?
Yessy : Itu tuh munafik alias muna yey!
Nadya : Ember! Jangankan yang sudah punya istri, punya anak, guru agama, tetep sukria sama kita-kita.
Yessy/Ara : Ya ialah habis kaum kita-kita mah serfisnya dari ujung rambut sampai ujung kaki!
Dalam dialog tersebut, dikatakan bahwa laki-laki zaman sekarang semuanya munafik dikarenakan ternyata masih tetap memakai jasa waria meskipun sudah memiliki istri dan anak, atau bahkan guru agama sekalipun.
Satu hal yang bisa saya ambil dari garapan tari kontemporer ini adalah pekerjaan masih menjadi kendala yang besar bagi waria. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang memaksa mereka untuk terjun ke jalan, melakukan pekerjaan yang sangat beresiko secara keamanan.
Hal ini tentu seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti yang saya sampaikan di atas, jika kita tidak menginginkan waria untuk bekerja di jalanan, alangkah baiknya kita menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka jika memang itu dibutuhkan. Bukannya melarang waria untuk di jalanan namun juga tidak mau menerima mereka untuk bekerja.
*Penulis adalah mahasiswa STSI Bandung dan kontrbutor Suara Kita untuk wilayah Bandung.
Jurnal dapat diunduh di sini
Catatan Kaki:
[1] http://www.who.int/hiv/topics/transgender/about/en/



