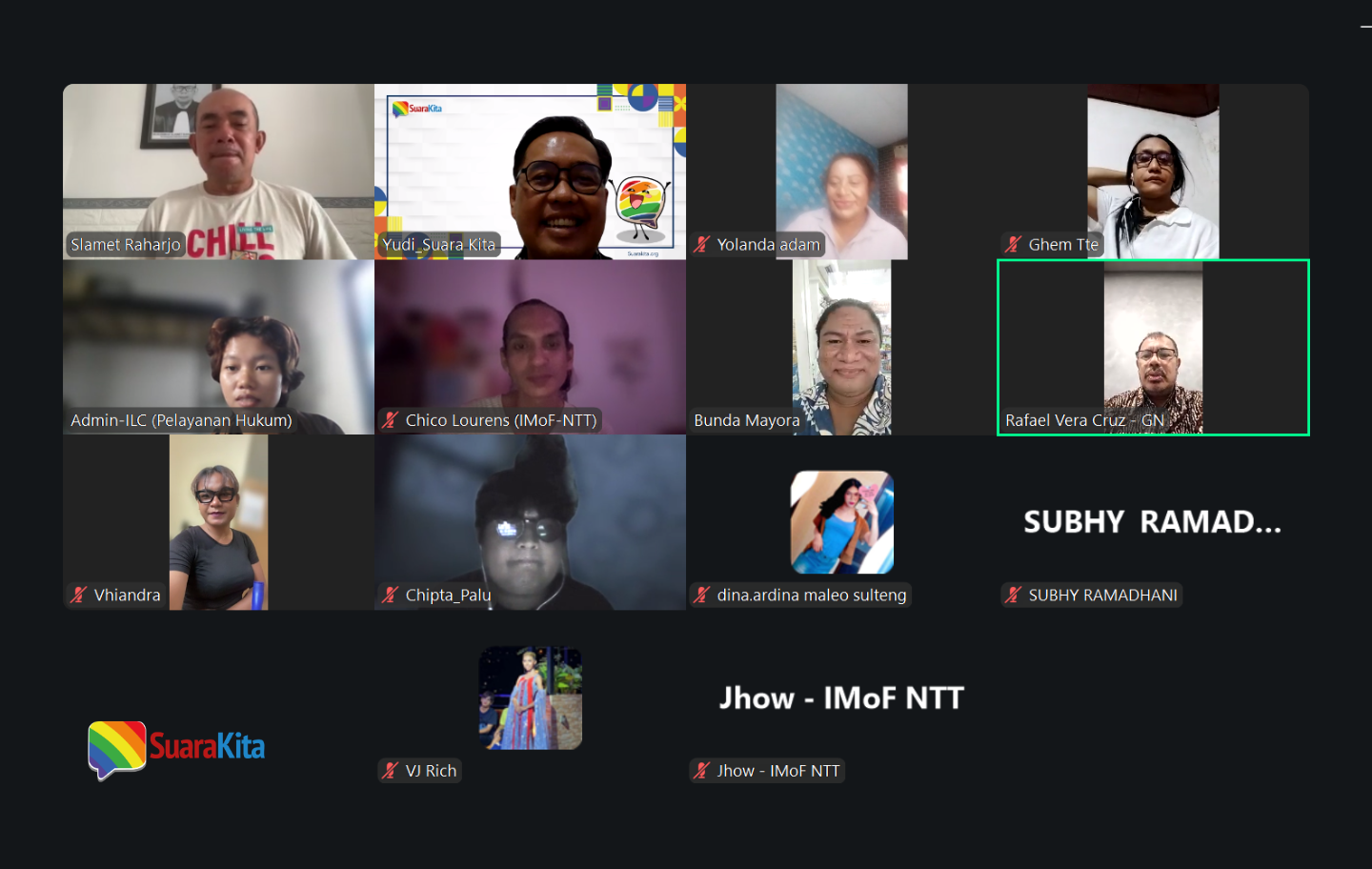Suarakita.org- Kamis 23 April 2015 bertempat di daerah Jakarta, Freedom Institut mengadakan diskusi publik dengan tema Pemblokiran Situs Radikal dan Kebebasan Berekspresi yang dihadiri oleh tiga narasumber yaitu, Ulil Abshar Abdalla (Cendikiawan Muslim), Wicaksono Ndoro Kakung (Jurnalis di Media Sosial) dan Megi Margiyono (Pakar Hukum Siber Indonesia Online Advokasi – IDOLA).
Adapun tema yang diusung tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sempat melahirkan kontroversi terhadap pemblokiran situs-situs internet yang cenderung dianggap menyebarkan ideologi radikalisme keagamaan, bahkan Ulil sendiri sebagai salah satu cendikiawan Muslim di Indonesia menuangkan buah pikirnya tentang ideologi radikalisme tersebut dan kaitannya terhadap kebebasan berekspresi dalam media harian Kompas edisi 9 April 2015, halaman 7 dengan judul “Pemblokiran Situs Radikal”.
“12 situs yang tadinya ditutup, sekarang sudah dibuka lagi…“ ujar Ulil disela-sela penjelasannya tentang radikalisme pada diskusi tersebut. Menurutnya pemblokiran itu tidak sekedar membicarakan isu HAM, akan tetapi keikutsertaan ummat Islam dalam memerangi kampanye kekerasan seperti jihad yang dilakukan oleh ISIS ataupun situs-situs spesifik lainnya perlu ditanggulangi bersama. Karena bagi Ulil ideologi jihad itu mencelakai publik secara terang-terangan.
Megi Margiyono juga mengamini bahwa aliran radikal itu cenderung menjadi pokok permasalahan. Dan perlu adanya pemahaman mendasar tentang apa itu yang disebut ideologi radikal, apalagi yang berkaitan dengan syiar kebencian, anjuran tindak kekerasan, dan permusuhan.
Megi beranggapan sejak aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dibawah pimpinan Tifatul Sembiring yang lalu telah diberlakukan pemblokiran lebih dari 300 situs yang kecenderungannya bias antara yang melanggar hukum, negatif, ataupun konten ilegal.
Megi sendiri mencontohkan bahwa arti konten negatif itu sendiri memiliki banyak sudut pandang, misal rokok itu negatif, tetapi iklan rokok tetap ada. Dan selama ini keberpihakan Menkominfo cenderung masih teknis, belum sampai pada hal yang substantif. Misalkan kata kunci “penis“ yang akhirnya salah sasaran memblokir situs-situs yang sebenarnya bukanlah bagian dari pornografi.
Menurut Megi setiap negara sebenarnya memiliki alasan berbeda dan punya tata cara tertentu terhadap pemblokiran sebuah situs. Di Vietnam, Cina, dan Korea Utara misalkan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang bisa merugikan Pemerintah. Sedangkan di Amerika lebih kepada konten ilegal yang melanggar hukum seperti kategorisasi terhadap pelanggaran hak cipta dan pornographi anak.
Menurut Megi, Indonesia belum benar-benar menguasai tentang konten ilegal yang disebut “harmful – berbahaya“ dengan yang tidak harmful. Apalagi jika diperhadapkan pada sistem blokir yang merupakan bagian dari teknologi yang sifatnya terbatas atau diistilahkan dengan adanya over-blocking (konten-konten yang seharusnya tidak terblokir ikut terblokir secara tidak sengaja) dan under-blocking (konten-konten yang seharusnya diblokir lolos dari blokir).
Wicaksono, jurnalis yang akrab disapa Ndoro Kakung dalam media twitter menambahkan apa yang diperjelas oleh Megi dan Ulil dalam diskusi tersebut tentang mekanisme sebuah situs yang terblokir. Ia juga bercerita pengalaman pribadinya ketika situs pribadi tempat ia bekerja diblokir secara tak sengaja, meskipun butuh proses yang njelimet agar situsnya tersebut aktif kembali, tetapi sangat disangsikan ketika orang awam memiliki permasalahan yang sama dengannya.
Seorang penanya yang hadir dalam diskusi itu juga menanyakan tentang bagaimana kedudukan pengguna sosial media dalam berekspresi ketika banyak kasus belakangan justru tersandung Pasal 27 IT tentang pencemaran nama baik. Dan dari jawaban yang disampaikan oleh Megi ada kecenderungan disparitas budaya yang berbeda ketika menanggapi sebuah masalah di media sosial, contohnya di Medan pada kasus-kasus serupa justru lepas dari kurungan penjara, dan akan berbeda ketika kasus itu terjadi di Yogyakarta, dimana pada kasus-kasus sejenis berakhir dipenjara. Tetapi karna bias yang cenderung terjadi akibat pasal 27 tersebut maka ke depannya perlu dipertimbangkan lagi efektifitas dari pemberlakukan pasal tesebut.
Diakhir diskusi, Ndoro Kakung memberi catatan tentang bagaimana pentingnya konten-konten kreatif dan menarik itu seharusnya dimerdekakan sebagaimana sebuah teknologi itu juga berkembang. Apalagi mengingat generasi muda sekarang sebetulnya apatis kepada hal-hal diluar dari kebutuhannya, sehingga apa yang dikatakan Ulil tentang pengadaan hukum yang objektif itu penting pada era digital sekarang ini dalam menangkal radikalisme perlu diwujudkan melalui kontesting, bukan pada pelarangan seperti yang terjadi di negara otoriter. Ulil menutup diskusi tersebut dengan metafor polisi dan perampok, dimana kehadiran mereka tetap selalu harus ada, karena hukum pun berlaku setelah ada sebuah peristiwa. (Jane Maryam)