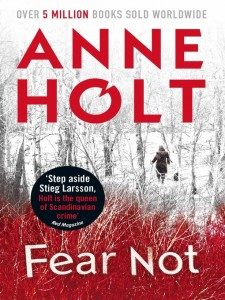 Oleh: Sebastian Partogi*
Oleh: Sebastian Partogi*
Dalam ilmu sosiologi dikenal konsep hate crimes, atau kejahatan yang berbasis kebencian. Pelaku hate crimes menyasar anggota dari kelompok sosial tertentu (baik itu agama, suku, ras, ataupun orientasi seksual) sebagai target kejahatan mereka. Berbeda dengan pelaku kejahatan lain, pelaku hate crimes tidak dimotivasi oleh dendam ataupun kebutuhan ekonomi. Mereka melakukan perbuatan keji karena didorong oleh kebencian terhadap sekelompok manusia tertentu yang mereka anggap menjijikkan atau tidak pantas hidup.
Kelompok homoseksual juga menjadi salah satu target yang empuk untuk hate crimes karena dianggap menyimpang, berdosa, menjijikkan. Dalam laporannya di tahun 2012 tentang pelanggaran hak asasi manusia kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), UNHCR (United Nation High Commissioner for Human Rights) mencantumkan banyak sekali kasus pembunuhan terhadap seorang individu hanya karena ia memiliki orientasi homoseksual. Sayangnya, belum tersedia data statistik yang akurat mengenai jumlah kasus pembunuhan / penganiayaan terhadap kaum homoseksual di Indonesia, meskipun Forum LGBTIQ Indonesia telah berupaya untuk mendokumentasikan jumlah kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT.
Contoh dari peristiwa hate crimes terhadap LGBT adalah insiden Matthew Shepard, warga Amerika Serikat yang meninggal setelah dipukuli oleh sekelompok pria homofobik pada tahun 1999. Juga pembunuhan pria gay oleh Al Qaeda di Yaman yang terjadi belakangan ini dan pemusnahan homoseksual dalam kamp holocaust oleh kelompok neo-fasis Nazi di Jerman pada tahun 1940an.
Dalam novelnya yang berjudul Fear Not (penerbit Corvus, 2012), penulis novel kriminal yang juga seorang pengacara Anne Holt mengetengahkan isu hate crimes terhadap homoseksual sebagai fokus kajiannya.
Penduduk Norwegia yang sedang bersukacita merayakan hari Natal pada 25 Desember 2008 dikejutkan oleh berita yang amat sangat tragis: polisi telah menemukan jenazah pendeta Eva Karin Lysgaard, seorang tokoh agama yang disayangi karena perilakunya yang penuh belas kasih, yang telah dibunuh pada tanggal 24 Desember 2008, pukul 11 tengah malam.
Johanne Vik, seorang pengacara sekaligus kriminolog menginvestigasi kasus pembunuhan tersebut bersama dengan Adam Stubo, suaminya yang adalah seorang detektif polisi. Mereka kesulitan menemukan titik terang yang dapat membantu memecahkan kasus pembunuhan pendeta Eva. Belum lagi, Erik dan Lukas Lysgaard, suami dan anak satu-satunya korban, menolak untuk mengungkapkan informasi apapun pada polisi mengenai apakah Eva memiliki musuh dan apa yang sedang ia lakukan di malam saat ia terbunuh.
Ternyata, kasus pembunuhan Eva Lysgaard bukanlah satu-satunya kejahatan yang terjadi di penghujung bulan Desember tersebut. Belakangan, polisi menemukan jenazah Marianne Kleive, seorang lesbian yang hidup bersama dengan kekasihnya Synnove yang adalah seorang pembuat film dokumenter terkenal, setelah yang bersangkutan menghilang selama beberapa minggu. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Marianne meninggal karena dibunuh pada tanggal 19 November 2008.
Di tanggal yang sama, Hawre Ghani, seorang gigolo homoseksual yang juga adalah seorang pencari suaka politik dari negara Timur Tengah, ditemukan telah tewas terbunuh.
Pada tanggal 27 November, seorang seniman gay bernama Niclas Winter ditemukan tewas karena overdosis di rumahnya. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata overdosis yang dialami oleh Winter bukanlah disebabkan oleh kegemarannya mengkonsumsi narkoba. Seseorang telah membunuh Winter dengan cara menyuntikkan cairan calcite (kapur) dengan dosis tinggi ke tubuhnya, sehingga kematiannya seolah-olah tidak disebabkan oleh pembunuhan.
Johanne dan Adam sudah mulai menemukan pola tindak kejahatan ini setelah melihat bahwa hampir semua korbannya adalah gay dan lesbian. Namun mereka mempertanyakan: lalu, mengapa Eva Lysgaard turut menjadi korban dari pembunuhan berantai ini? Eva memang dikenal sebagai seorang tokoh agama yang berpihak pada kelompok homoseksual, tetapi bukankah dia seorang hetero? Buktinya ia menikah dan memiliki anak.
Di saat itulah sebuah rahasia keluarga terbongkar. Lukas menemukan foto Eva bersama dengan seorang perempuan. Kemudian Erik, sang suami, membeberkan bahwa perempuan di foto tersebut adalah Martine, kekasih Eva. Erik sendiri adalah seorang gay dan ia setuju menikah dengan Eva untuk saling menutupi orientasi seksual mereka. Selama menikah dengan Erik, Eva masih berhubungan dengan Martine.
Saat rahasia keluarga ini terungkap, Johanne dan Adam menyadari bahwa mereka harus bergerak cepat untuk menemukan sang pembunuh, yang ternyata bergabung dalam kelompok fundamentalis lintas-agama yang disebut sebagai kelompok 25. 25 sendiri adalah hasil penjumlahan digit dari angka 19, 24 dan 27. Angka 19 dianggap sebagai angka suci dalam al-Qur’an sementara 24 dan 27 mengacu pada surat Roma 24 dan 27 dalam Alkitab yang mengutuki homoseksual sebagai perilaku berdosa.
Kelompok tersebut mempersatukan agama Kristen dan Islam – dua agama yang seringkali berseteru karena berebut pengikut – dalam kebencian terhadap kaum homoseksual. Bersama, mereka menganggap bahwa kaum homoseksual pantas dibunuh – “halal darahnya” – karena mereka adalah pendosa, titik. Oleh karena itulah, para pengikut kelompok 25 merasa bahwa membunuh kaum homoseksual merupakan titah Tuhan yang wajib dilakukan. Adam dan Johanne harus bergerak cepat sebelum sang pembunuh menghabisi korban berikutnya…
Mungkin saat ini kita bisa menarik napas lega karena kelompok 25 adalah sebuah geng fiktif ciptaan Holt, sang novelis yang juga adalah seorang lesbian. Namun, kisah yang diungkapkan dalam novel Fear Not adalah sebuah peringatan bagi Indonesia. apabila kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita untuk menghormati kaum homoseksual dan pemerintah tidak pernah menindak tegas pelaku kekerasan atas nama agama, bukannya tidak mungkin kelompok neo-fasis fiktif ini betul-betul muncul di Indonesia, seperti halnya Ku Klux Klan di Amerika dan Nazi di Jerman.
*Penulis adalah wartawan harian berbahasa Inggris The Jakarta Post.






