SuaraKita.org – Setiap ada perhelatan akbar yang dilakukan oleh umat atau organisasi berbasis agama, yang memiliki massa besar, selalu saja ada cerita bagaimana kelompok yang jumlahnya kecil, akan memberikan sumberdaya mereka untuk acara tersebut.
Misalnya saat Idul Fitri, ada komunitas Kristen yang memberikan halaman gereja mereka untuk sholat Idul Fitri.

Termasuk saat perhelatan akbar ormas agama terbesar yang baru saja berlangsung. Umat GKI Sidoarjo memberikan ruang dan tempat untuk peserta pertemuan, bahkan menurut berita ikut memberikan makanan secara gratis.
Karena ada aksi tersebut, ada pihak yang menilai bahwa aksi ini bukti gerakan “toleransi” umat beragama.
Saya kemudian berpikir, benarkah ini tindakan apa yang disebut dengan toleransi dalam beragama?
Apakah aksi-aksi yang dilakukan oleh umat agama yang berjumlah kecil, akan dilakukan juga dengan sadar dan kerelaan oleh umat atau kelompok agama yang berjumlah besar?
Misalnya saat ada pertemuan akbar agama dengan umat kecil, umat agama yang berjumlah besar akan memberikan ruang dan sumberdaya secara maksimal?
Saya ingat, pernah ada acara Pesparawi, sebuah pagelaran sejenis festival lagu-lagu gereja di seluruh Indonesia. Sebagian peserta acara tersebut menggunakan “Asrama Haji” milik negara. Tapi kemudian muncul perdebatan dan penolakan dari umat mayoritas tersebut.
Dengan alasan beragam, tapi substansi argumennya, Asrama Haji adalah tempat yang mestinya harus “suci”, bebas dari segala hal yang “berbau kekafiran dan kemurtadan”.
Bahkan untuk latihan nyanyi pun dilarang. Jangan-jangan melakukan ritual doa pagi membaca Al-Kitab juga dilarang saat berada di asrama tersebut.
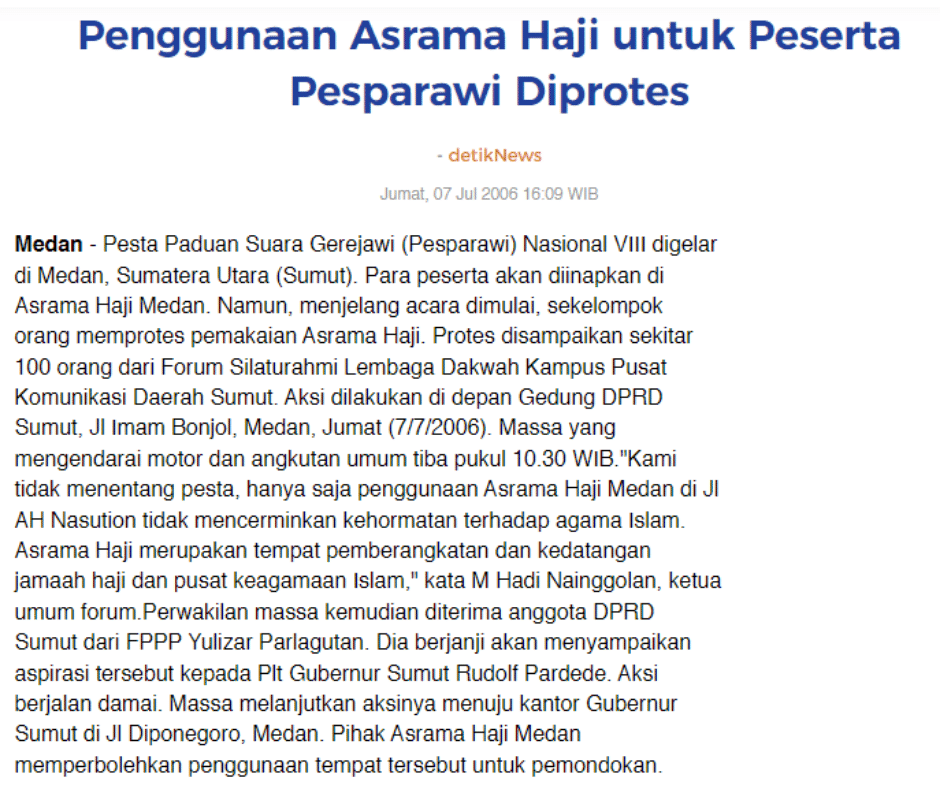
Padahal asrama itu bagian dari aset negara, kalau atas nama milik negara, artinya uang yang digunakan membangun dan merawat berasal dari uang seluruh rakyat Indonesia. Milik semua rakyat!
Dari kasus-kasus itu, menurut saya ada fenomena kelompok yang memiliki kecil kuasa dan jumlah akan terus berusaha “bertahan” dengan beragam cara.
Salah satunya dengan terus berbuat baik, berkorban, memilih mengalah pada kelompok yang lebih besar kuasa dan jumlahnya.
Ruang dan kuasa akan diberikan pada kelompok yang besar, inilah cara kelompok kecil untuk tetap hidup dan bertahan dalam situasi politik yang masih sangat diskriminatif.
Supaya kelompok yang kecil tersebut akan merasa terlindungi, tepatnya merasa aman untuk hidup sebagai warga.
Situasi ini secara pribadi (sebagai seorang yang dibesarkan dalam umat agama mayoritas dan menjadi seorang gay), membuat saya “sedih” dan mempertanyakan.
Karena pada satu “momen”, saya harus melakukan hal yang sama sebagai aktivis LGBT, karena itulah cara paling aman dan praktis. Meminta “perlindungan” dan “perwakilan” dari suara kelompok mayoritas.
Apalagi ketika situasi sangat genting, yang marginal membutuhkan “Hero” dari yang mayoritas.
Kelompok yang berjumlah kecil, beragam cara diupayakan mendekat dengan kelompok dengan massa besar, supaya ada “pelindung” bagi warga yang terpinggirkan.
Strategi ini bahkan diyakini tepat dan disarankan oleh para aktivis ketika “berjuang” untuk isu-isu yang berat bagi kelompok marginal.
Makanya, saat ada pesta demokrasi berlangsung, kelompok marginal harus menerima dengan legowo, ketika kursi kekuasaan yang strategis, menjadi milik kelompok dengan massa besar.
Pertanyaan kritis saya, apakah situasi ini layak disebut sebagai gerakan toleransi? Tidak kah ini lebih tepat sebagai gerakan “pengorbanan”, dari kelompok yang kecil untuk mereka yang besar?
Jakarta, 9 Februari 2023
Hartoyo, pendamping akses KTP dan Jamsos bagi komunitas transgender di Indonesia.






