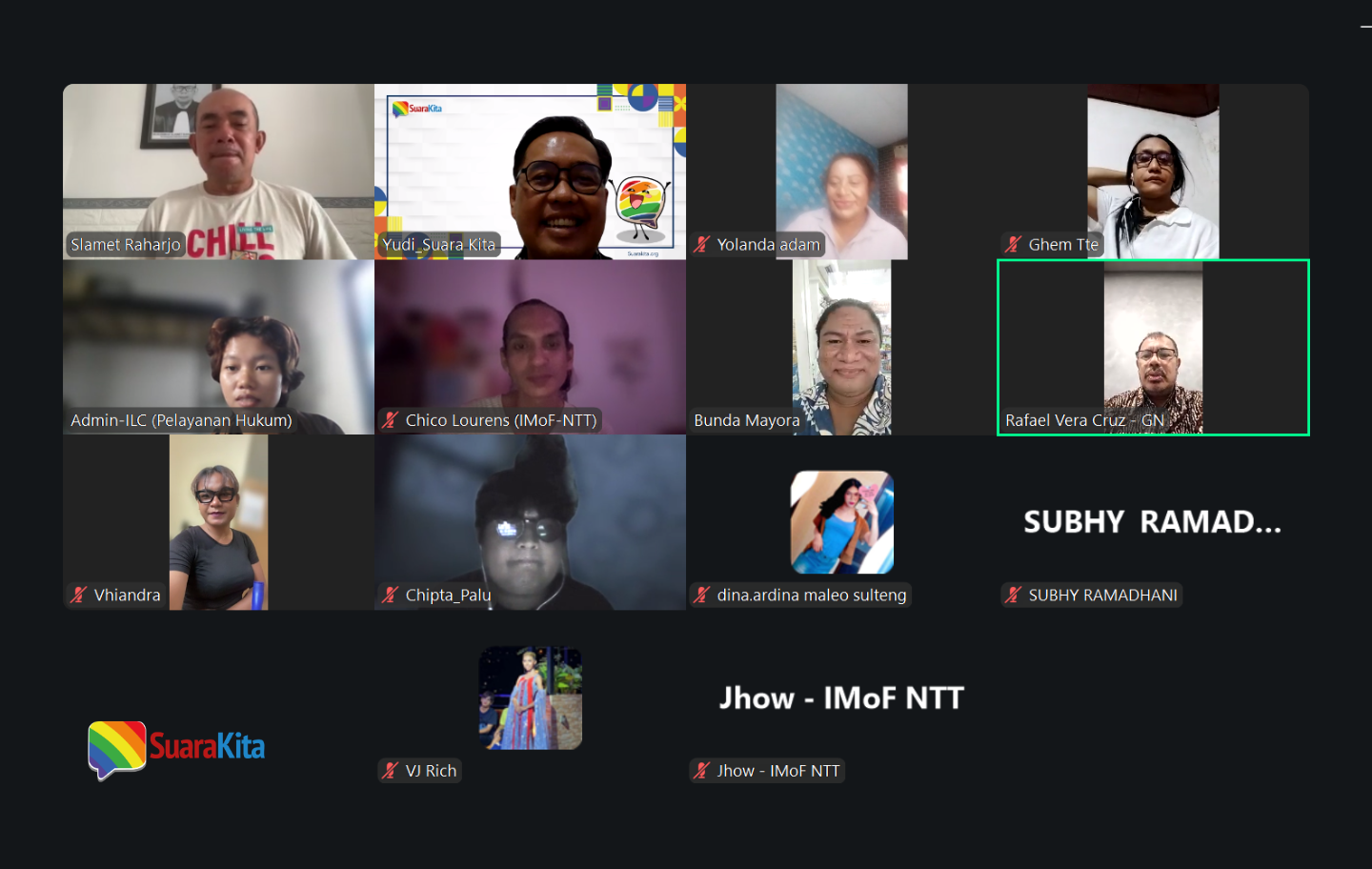Suarakita.org- Minggu, 4 Oktober 2015 Suara Kita mengadakan kuliah umum bertemakan Radikalisasi Demokrasi, dengan narasumber Agus Wahyudi, M.A, seorang pengajar Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM).
Kuliah ini ada tiga sesi. Untuk kuliah pertama kali ini Agus Wahyudi memberikan pengantar mengenai bagaimana munculnya ide radikalisasi demokrasi. Menurut beliau demokrasi sudah mulai dipraktekkan pada abad 4 SM pada zaman Yunani Kuno di Athena. Namun sangat jelas demokrasi pada saat itu tentulah sangat berbeda dengan ide demokrasi dewasa ini. Pada masa itu budak dan perempuan belum memilki suara dalam penentuan kebijakan publik.
Demokrasi kemudian, menurut Agus Wahyudi, mengalami semacam mati Suri dari abad ke-5 M hingga abad ke-17 M. Kemudian terjadi ledakan demokrasi di seluruh dunia pada abad ke-20. Menurut Agus, saat ini demokrasi masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik yang pernah dicoba dalam sejarah umat manusia, dan apa justifikasinya? Dalam hal ini menurut Agus ada dua yaitu justifikasi secara instrumental; salah satu instrumental tersebut menyebutkan bahwa riset-riset mutakhir menunjukkan bahwa negara-negara yang sejahtera dengan indeks perekonomian yang baik adalah negara-negara demokrasi.
Sedangkan justifikasi kedua adalah teori perdamaian demokratik yang hendak mengatakan bahwa demokrasi sebagai alat untuk perdamaian dunia. Namun di luar kedua justifikasi terebut, terdapat alasan instrinsik yang cukup penting, yaitu ada nilai-nilai kebaikan di dalam diri demokrasi. Nilai-nilai tersebut adalah freedom (kebebasan) dan equality (kesetaraan). “Demokrasi bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan namun pentingnya rakyat untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan. Dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mendesain institusi demokratik”, ungkap Agus.
Pemapaparan Agus kemudian berlanjut dengan model-model demokrasi yang ada di dunia pada saat ini. Model pertama adalah Agregatif, yaitu model yang mengedepankan pentingya pendapat setiap individu (one man one vote) dan Deliberatif bahwasanya setiap orang tetap bebas dan setara namun dengan memperhatikan pengalaman setiap individu. Sedangkan model agonistic seperti yang dimaksudkan oleh Chantal Mouvfe bahwasanya demokrasi tidak dapat hanya bersandar pada asumsi rasional dan individualisme tetapi tetap mempertimbangkan emosi dan afeksi.
Karena pada akhirnya tidak semua proses politik itu rasional. Dalam mempertimbangkan sesuatu terkadang kita masih terpengaruh oleh pilihan-pilihan emosional dan tidak semua pilihan politik itu pada akhirnya diputuskan seacra rasional. Oleh karenanya radikalisasi demokrasi mencoba menterjemahkan gagasan freedom dan equality menurut satu cara pandang hukum sosial yang kira-kira kurang akurat untuk mengelola kehidupan politik bersama.
Dan apabila kita memahami bahwasanya keadaan sosial adalah antagonistik maka tantangan demokrasi adalah bagaimana mentransfromasi antar antagonisme tersebut menjadi satu hubungan agonistik. Dan hubungan agonistik adalah bukan relasi antara friends and enemy, tetapi friends and adversaries.
Dalam relasi friends and enemy kita harus menyingkirkan orang- orang yang berbeda dan tidak sepakat dengan kita. Misalnya ketika kelompok fundamental agama tidak setuju dengan keberadaan LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) maka kelompok LGBT harus dibasmi dan disingkirkan.
Namun tidak dengan hubungan friends and adversaries, dalam relasi ini intinya kita boleh tidak setuju tentang sesuatu atau pilihan hidup orang lain tetapi tetap menghormati hak hidupnya sehingga mealhirkan rekognisi (pengakuan) dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun, tambah Agus, ternyata perjuangan tidak hanya sebatas pada perjuangan rekognisi tetapi ada problem lain, ada struktur tidak tampak yang opressif dan subordinatif. Hal inilah kenapa kemudian Mouffe berbicara mengenai Chain Of Equivalance, karena menurutnya perjuangan kaum lemah dan terindas, misalnya kelompok LGBT harus membentuk kerjasama dengan kelas sosial lain yang mengalami nasib yang serupa seperti minoritas agama, kelompok buruh dan kelompok feminis untuk mendobrak struktur yang tidak adil tersebut.
Jane sebagai moderator mengajukan pertanyaan dimana letak keadilan dalam teori Chain of Equivalen yang digagas oleh Mouffe terkait dengan kasus pernikahan pasangan gay yang terjadi di Bali. Agus kemudian membalikkan pertanyaan tersebut dengan pertanyaan kembali bagaimana peran dan rencana kelompok LGBT menanggapi hal-hal tersebut? Agus kemudian melanjutkan bahwasanya yang terjadi adalah kontestasi hegemonik dan bagaimana merealisasikan self ownership dan kedirian setiap orang secara bebas dalam masyarakat demokratif. Karena dalam demokrasi adalah bagaimana konflik dari berbagai kelompok tersebut dapat terselesaikan, dan mengapa konsep Chain of Equivalence itu penting. “Kita sebenarnya sedang mengidentifkasi siapa kawan dan siapa lawan kita sebenarnya meskipun bukan dalam identitas yang sama”, kata Agus. (Eddy)
Materi kuliah umum bisa diunduh di sini