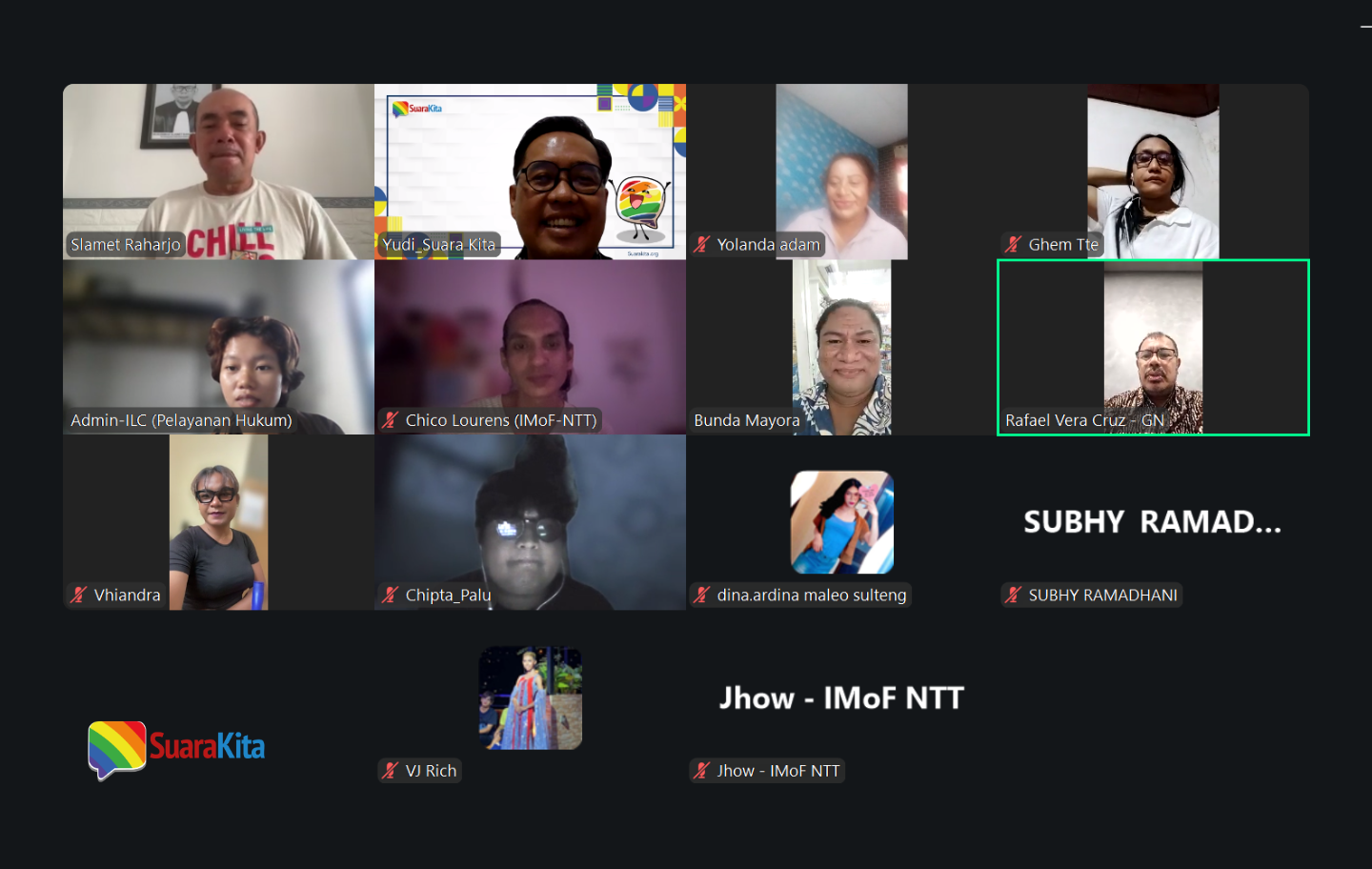Penulis : Tanti Noor Said*
Suarakita.org- Pada pekan Festival Film Asia yang diselenggarakan di Amsterdam pada tanggal 1-6 April 2014, saya mendapatkan undangan untuk menjadi moderator dalam sebuah panel yang berjudul “Being LGBT in an Asian Community.” Panel ini menyertai pemutaran sebuah film berjudul “Our Marriages”. Our Marriage mengambil setting di Cina. Kawin kontrak ini adalah sebuah jasa terbuka yang dapat ditemukan online. Fungsi dari perkawinan ini adalah untuk menghindari tuntutan dari keluarga, maupun masyarakat.
Kawin kontrak antara gay dan lesbian di Cina : Aspek sosial, budaya dan ekonomi
Film dokumenter ini bercerita mengenai perjalanan empat orang lesbian yang mencari pasangan gay laki-laki untuk mereka nikahi. Pernikahan kontrak ini berbeda dengan pernikahan tradisional layaknya karena ada perjanjian-perjanjian yang harus ditaati kedua belah pihak, seperti tidak berhubungan seks, tidak saling mencampuri urusan keuangan dan tidak mewarisi kekayaan pasangannya. Pernikahan ini memang dimaksudkan untuk menyenangkan pihak keluarga dan masyarakat saja.
Seperti juga di Indonesia, pernikahan berikut resepsinya, adalah sebuah tahapan penting dalam kehidupan seorang anak bagi orangtuanya. Pernikahan bukan saja menyangkut kedua orang yang saling mencintai, namun juga bagian dari tradisi sebuah masyarakat. Itu sebabnya pernikahan ini selalu disertai dengan resepsi yang harus disaksikan oleh keluarga dan masyarakat. Anak yang belum menikah akan membawa kekhawatiran bagi orang tuanya. Status pernikahan anak dapat berpengaruh pada status sosial dan kehormatan sebuah keluarga.
Film ini memperlihatkan dengan jelas didemonstrasikannya perangkat-perangkat yang menjadi simbol dari status sosial keluarga dan kesahihan dari cinta kedua belah pihak pasangan. Misalnya saja megahnya mobil limosine yang mereka tumpangi, juga iring-iringan mobil produk Jerman Mercedes Benz, yang ditumpangi para orangtua lengkap dengan hiasan rangkaian bunga diatasnya. Di dalam limosine tersebut duduk empat pasangan lesbian dan laki-laki gay tadi. Mereka minum sampanye bersama, saling bercanda dan mentertawakan orang-orang diluar limo yang sibuk mengambil foto limo yang mereka tumpangi dengan kamera telefon selular. Di gedung resepsi, para pasangan inipun diminta untuk melakukan adegan mesra. Adegan tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk foto.
Yang unik dari film ini adalah, ke-empat lesbian ini kemudian saling jatuh cinta dan menjadi pasangan. Mereka hidup dalam satu rumah. Namun mereka merasa lega, karena pernikahan kontrak mereka, menghindarkan mereka dari tekanan keluarga atas tanggungjawab mereka sebagai seorang anak terhadap orangtua dan masyarakat.
Diskusi pembahasan film dari perspektif LGBT Asia yang tinggal di Eropa.
Saya dan kawan baik saya Penn Ip bertindak sebagai moderator saat itu. Kami mempersiapkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anggota panel. Anggota panelnya adalah dua orang imigran professional, Salim Sander (Indonesia) dan Jen (Singapura) dan Olympia, seorang perempuan kelahiran Belanda berdarah Maluku. Satu hal yang saya sadari sejak awal adalah, bahwa acara ini dibuat dengan konsep yang sederhana dengan tidak memperhatikan banyak aspek seperti imigrasi, globalisasi, kekhususan praktek jender dan seksualitas di berbagai budaya selain Belanda dan ekonomi. Aspek-aspek ini mungkin ada disebut dalam diskusi, namun tidak secara kritis.
Penn dan saya membuat pertanyaan berdasarkan film yang kami screening dan berkaitan dengan keterangan singkat mengenai kehidupan LGBT dalam komunitas Asia. Secara garis besar pertanyaan yang kami ajukan adalah mengenai pengalaman mereka dengan keluarga, apakah mereka juga mengalami keterpaksaan untuk menikah secara heteroseksual dikarenakan keluarga. Ketiga pembicara kami ini mengaku tidak mengalami kejadian serupa. Ada yang sudah keluar dari rumah sejak usia yang sangat muda dan ada pula yang beruntung karena tinggal di Eropa dan jauh dari keluarga. Jarak membuat tekanan dan tuntutan seperti ini tidak terlalu besar.
Kemudian kamipun beranjak menuju tema mengenai “Coming Out”. Para pembicara ini mengaku sudah coming out dengan keluarga. Terutama Jen yang transgender. Karena dengan sendirinya keluarga dan teman-temannya dapat melihat perubahan di tubuhnya. Itu sebabnya, cara coming outnya tidak sama dengan teman-teman yang homoseksual dan tidak trans. Tema ini terlihat masih sangat sensitif untuk kita semua. Menurut saya, hal ini sangatlah wajar. Wacana coming out adalah salah satu wacana yang sampai saat ini menimpulkan kontroversi seperti menantang integritas dan keberanian seseorang yang tidak menganut praktek heteroseksual.
Salah seorang peserta diskusi yang berasal dari Indonesia dan belum coming out pada keluarganya pun menumpahkan kecemasannya. Ia takut sekali, jika ia mengaku gay, maka ia akan mendapatkan masalah dengan keluarganya. Saya, yang sudah beberapa tahun ini berteman dengan kawan-kawan, baik di Indonesia, maupun imigran di Belanda dan Belgia cukup mengerti akan kecemasannya. Namun ini bukan sesuatu yang khusus atau hanya terjadi di Indonesia maupun masyarakat Asia saja. Bukan juga hanya dikarenakan rigidnya praktek agama Islam, Nasrani, Hindu atau Budha. Karena tidak ada satu negara atau masyarakatpun di dunia ini yang tidak menganut heteronormativitas.
Perlu disadari, membandingkan praktek jender dan seksualitas di Indonesia atau wilayah Asia dengan praktek yang ada di Belanda ataupun wilayah Eropa Barat lainnya adalah sangat kompleks dan tidak memiliki signifikansi, baik secara ilmiah dan sosial. Kita harus sadari perbedaan latar belakang sejarah, keadaan dan kestabilan politik, nilai dan norma kebudayaan, sistem kekerabatan dan distribusi ekonomi (distribution of wealth) antara negara-negara di Eropa Barat dan negara-negara di Asia seperti halnya Indonesia.
Jika di negara-negara Eropa Barat yang kemakmurannya terdistribusi hampir merata, selama ini, anak yang berusia 18 tahun dan orang tua tidak harus memiliki ikatan ekonomi, maka tidak seperti itu di negara kita. Tentu di Indonesia juga harus dibedakan lagi berdasarkan latar belakang orangtua. Kemudian jangan lupa, krisis moneter juga saat ini melanda Eropa Barat, dengan begitu banyak anak berusia 18 tahun yang masih tinggal di rumah dan bergantung secara ekonomi dengan orangtuanya. Hal ini merupakan sebuah potensi yang akan merubah sistem kekerabatan dan ikatan antara orangtua dan anak. Dimana orangtua kembali memiliki kontrol atas perilaku anaknya tersebut.
Masih banyak hal-hal lain yang perlu ditinjau ketika kita membandingkan “kebebasan” yang ada di masyarakat Eropa Barat dan masyarakat non-Barat seperti Cina dan Indonesia. Dengan berfikir secara kritis pada banyak aspek yang tidak hanya praktek jender dan seksualnya, tetapi menitik beratkan pada dinamika, proses dan subjektivitas individu, maka kita akan mampu mengerti permasalahan dengan lebih menyeluruh.
*Penulis adalah kontributor Suara Kita dan antropolog lulusan dari Program Master Antropologi Budaya dan Sosiologi masyarakat Non Barat, Universitait van Amsterdam