Dalam gebyarnya dunia panggung hiburan di tanah air, siapa tak kenal nama Dorce? Tak seperti umumnya para artis panggung hiburan yang lengser panggung karena usia, walau usianya sudah berkepala empat sudah berkepala empat. Maklum, kebisaan Dorce menghibur penggemarnya memang sangat komplet sehingga selalu memuaskan para penonton.
Selain membawa acara dan melawak, ia mampu membawakan lagu dalam berbagai irama, seperti jazz, pop, dangdut, rock, dan sebagainya. Ia juga fasih membawakan berbagai lagu berbahasa asing, seperti Inggris, Belanda, Prancis, Arab, dan Cina. Wajar kalau kemudian ia beberapa kali diundang tampil di luar negeri, seperti di Amerika, negara-negara di Eropa, Asia, Australia, dan sebagainya. Penggemarnya pun sangat beragam, dari kampung-kampung kumuh sampai hotel berbintang dan Istana Negara.
Di tengah kesibukannya yang padat, Dorce, yang dulu bernama Dedi Yuliardi Ashadi, masih berusaha memberikan perhatian untuk pergi ke pengajian dan mengurus Yayasan Dorce Halimatussa’diyah yang menyantuni sekitar 1.600 anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Berikut tuturan kisah hidup Dorce yang ditulis oleh Agoes MD. Tulisan ini dibuat berdasarkan wawancara dengan Dorce dan orang-orang terdekatnya, juga sebagian mencuplik dari buku Perjalanan Kehidupan Dorce yang disusun dan diterbitkan oleh Massardi Communications.

Kowe luwe yo, Le? Rono nang pawon kono (kamu lapar ya, Le –panggilan untuk anak lelaki – pergi ke dapur sana) !” kata Titiek Puspa kepada seorang bocah yang merunduk-runduk di depan pintu rumahnya di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat. Bocah itu mengaku bernama Dedi Ashadi dan hidup sebatang kara di Jakarta. Bersama suaminya, Mus Mualim, penyanyi kenamaan itu tahu persis bahwa setiap kali datang ke rumahnya, anak itu tengah kelaparan dan perlu makan. Oleh Titiek atau suaminya, anak itu pasti langsung disuruh pergi ke dapur rumahnya, untuk mencari dan mengambil makanan sendiri.
Sesekali bocah itu bersedia menginap selama beberapa hari. Sambil bersekolah, ia membantu merapikan rumah itu, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, atau bahkan memasak. Itu terjadi sekitar tahun 1972, ketika bocah itu berusia sekitar sembilan tahun.
Kini, bocah itu tidak hanya bisa hidup mandiri, tapi bahkan berhasil menjadi artis yang sangat terkenal. Ia pun sudah berganti kelamin dan berganti nama. Dia adalah Dorce Gamalama, artis panggung serba bisa. Selain mampu menyanyikan berbagai lagu dalam berbagai bahasa dan aliran musik, Dorce juga mampu menjadi seorang presenter, pelawak, dan pemain sinetron.
Tak seperti di panggung yang gemerlap dan penuh senyum, sejatinya kehidupan Dorce sangat memelas dan penuh tangis. Sejak usia satu tahun sudah tak beribu-bapak, masa kanak-kanaknya terlunta-lunta, dan hingga kini pun ia masih bersimbah duka. Meski kariernya sukses, ia acap kali menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari keluarganya.
DISUSUI NENEK
Kehidupan masa kanak-kanak Dorce sangat memelas. Dilahirkan di Solok, Sumatra Barat, 21 Juli 1963, sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara, Dorce yang masih bayi itu harus berpisah dengan ibunya, Hj. Dalifah. Usianya baru tiga bulan ketika ibundanya berpulang. Sejak itu, ayahnya, H. Achmad, mengalami tekanan batin yang sangat berat. Ia kemudian menikah lagi dan punya seorang anak, tapi luka hati ditinggal Dalifah tak kunjung sirna. Akibatnya, seniman yang pernah bergabung dengan Sanggar Ratu Asia itu menjadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Lagi-lagi, Dorce yang baru berusia satu tahun itu harus menghadapi kenyataan yang sangat memilukan, jadi yatim piatu.
Ia kemudian diasuh oleh neneknya, ibunda dari ibu Dorce, yang kemudian menyayanginya sepenuh hati. Tumpahan kasih yang demikian besar ini, konon, mendatangkan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan Siti Darama. Menurut Hj. Solwani, adik dari ibunda Dorce, ketika mayat ibunda Dorce baru saja usai dimakamkan, Dorce yang saat itu baru berusia tiga bulan terus-menerus menangis dan meronta. Selain lapar, bayi yang masih merah itu mungkin merasa sedih karena ditinggal ibundanya. “Karena kasihan, bayi itu pun kemudian disusui oleh Mak,” kenang Solwani. “Masya Allah… suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba air susu Mak keluar, padahal saat itu usia Mak sudah 60 tahun. Sejak saat itu pula Dorce pun menyusu kepada Mak yang tiada lain adalah neneknya.”
Ditambahkan oleh Solwani, Dorce kecil pun tumbuh makin besar dan sehat. “Mak sangat bahagia melihat perkembangan cucunya yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya itu. Saat mulai bisa ngomong, ia juga makin cerewet dan lucu. Tubuhnya makin tinggi, tapi tidak pernah bisa besar. Anehnya, sebagai seorang anak laki-laki, cara berjalannya tampak sangat gemulai.”
Sayangnya, kehidupan Nenek Darama sangat mempri-hatinkan. Ia tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan sehingga ia pun harus berpindah-pindah tempat, menumpang di rumah anak-anaknya di Bukittinggi, Padang, dan sebagainya. Suatu hari ia pergi ke Jakarta bersama Dorce yang baru berusia dua tahun dan menumpang di rumah salah seorang putrinya, Hj. Dalimah, istri Endarsan, yang sehari-hari dipanggil Datuk Adur oleh Dorce.
Rumah sewa sederhana yang tidak terlalu besar di daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, ini terletak di daerah yang sangat padat penduduknya. Jumlah penghuni rumah ini juga relatif banyak. Selain suami-istri Endarsan dan Dalimah, di rumah ini tinggal juga anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya. Lantai rumahnya dari semen dan lampu penerangan di rumah ini masih mempergunakan lampu minyak tanah.
Di sinilah babak kehidupan baru Darama bersama cucunya yang masih kecil itu dimulai. Setelah sekian tahun tinggal di rumah tersebut, Dorce kecil merasa bahwa ada salah seorang anggota keluarga di situ yang kurang welcome atas kehadirannya maupun neneknya. Namun, neneknya selalu berusaha menghibur dan menasihatinya agar tidak terlalu dipikirkan. Suatu hari Dorce merasa sangat sedih ketika melihat makanan neneknya diludahi oleh orang tersebut. Saat itu ingin rasanya ia berontak dan melawan, tapi tak berdaya. Selain masih terlalu kecil, ia juga tidak punya nyali. Akhirnya, semalaman ia hanya bisa menangis di pangkuan neneknya.
DIMARAHI DAN DISIKSA
Awalnya Dorce sangat keberatan menguak masa lalunya. Ditemui saat sedang dirias untuk persiapan sebuah acara di teve swasta, Dorce sangat enggan diajak bicara tentang masa kanak-kanaknya. “Jangan bicara masa lalu, deh… saya bisa menangis dan riasan saya bisa rusak semua. Pahit… pahit… dan menyedihkan sekali,” pintanya dengan penuh harap.

Setelah beberapa kali pertemuan, barulah Dorce bersedia membuka diri. “Saya sesungguhnya tidak bermaksud menyembunyikan masa lalu saya,” katanya dengan pandangan mata menerawang. “Tapi, kalau kisah ini saya buka, ada pihak yang pasti merasa tidak senang dan merasa dipermalukan namanya. Saya tidak merasa dendam dan marah pada siapa pun.
Tapi, fakta kehidupan memang perlu diungkapkan secara jujur sebagai cermin hidup diri sendiri atau siapa pun yang merasa perlu bercermin. Hidup memang tidak selalu di bawah atau di atas, karena roda kehidupan memang terus berputar,” lanjutnya.
Ibu tiga anak angkat —Rizky (18), Fatimah (15), dan Khadijah (7)– itu berhenti bicara sebentar, lalu menarik napasnya dalam-dalam. “Saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari saudara-saudara saya,” tuturnya dengan berat hati dan mata berkaca-kaca. “Ketika ibu dan ayah saya meninggal, seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap hidup saya itu kan kakak-kakak saya. Tapi, semuanya tak ada yang peduli pada saya. Padahal, hidup mereka terbilang lumayan. Saya akhirnya tinggal bersama nenek saya, yang untuk mengurus hidupnya sendiri pun juga susah. Dari dirinyalah saya menemukan kasih sayang yang tulus dan utuh. Meski hidup kami menyedihkan, kami lalui berdua dengan tabah.”
Ketika usia lima tahun, Dorce dimasukkan ke taman kanak-kanak yang lokasinya tak jauh dari rumah bibinya di Kramat Sentiong. Setahun kemudian ia disekolahkan di SD Salmin dan sore hari ia sekolah agama di Al-Wasliyah. “Saat bersekolah, saya hanya setengah-setengah. Ketika itu sekolah bagi saya hanya untuk refreshing dari kehidupan yang menyiksa batin di rumah sekaligus memperluas pergaulan. Saya menyadari otak saya tidak pintar-pintar amat, jadi cita-cita saya pun tidak muluk-muluk. Yang penting, saya bisa membaca, menulis, dan sedikit berhitung. Bagi saya itu sudah cukup!”
Saat di SD, pelajaran yang paling disukai adalah menyanyi dan kesenian, sementara pelajaran yang paling dibenci adalah matematika. “Setiap kali ada pelajaran matematika, saya tidur atau kabur dari kelas,” kenang Dorce. “Selain tidak senang pada pelajaran itu, ditambah banyak mengalami siksaan di rumah, maka otak saya jadi makin bebal dan bodoh.”
Padahal, meski masih anak-anak, ia maklum akan posisinya. Walaupun tinggal di rumah bibinya, ia tak bisa seenaknya. Karena itu, meski boleh dibilang masih anak-anak. ia pun membantu bekerja apa saja di rumah itu. Antara lain, menyapu, mengepel, mencuci, mengambil air, atau membantu memasak di dapur. Setelah agak besar, kalau ia sudah menyelesaikan tugasnya di rumah, ia pun langsung pergi bermain atau ke jalan besar untuk mencari uang saku. Maklum, ia tentu saja tidak bisa mengharapkan pemberian uang saku dari nenek atau saudaranya karena kehidupan mereka sendiri sangat pas-pasan. Ia menjajakan kue-kue di jalan atau membantu berjualan koran.
Perjalanan hidup Dorce selanjutnya makin kelabu. Sudah sejak lama Dorce merasakan ketidaknyamanan tinggal di rumah bibinya itu. Selain beban pekerjaannya di rumah itu kian berat, ia pun hampir setiap hari dimarahi dan mendapat hukuman dari sepupunya. Setiap hari ada saja tingkah laku atau pekerjaan Dorce yang dianggap salah yang membuat sepupunya itu naik pitam. Selain mulutnya tajam setiap kali marah, tangan sepupunya itu sangat keras kalau memukul atau mencubiti tubuh dan kaki Dorce. “Kaki dan tubuh saya jadi merah-hitam kalau habis dicubiti atau dipukuli oleh kakak sepupu saya itu,” keluh Dorce.
Ia tidak bisa melawan, selain karena takut, selisih usia mereka pun sangat jauh. Saat itu usianya baru sekitar delapan tahun sementara sepupunya sudah berkeluarga dan sudah punya satu anak. “Padahal, setiap hari saya juga membantu memomong anaknya. Kenapa setiap hari dia selalu memarahi dan menghukum saya?” tanya Dorce kesal.
Ada saja kesalahan yang ditimpakan kepadanya sehingga ia pun bingung harus bersikap bagaimana. Saat belajar di malam hari pun, bisa-bisa jadi sumber petaka. Ia menyadari dirinya tidak pintar sehingga untuk mempelajari sesuatu pun menjadi sangat sulit. Akibatnya, Dorce pun menjadi sasaran kemarahan sepupunya itu. “Kalau saya tidak segera bisa menghafal sesuatu, maka kepala saya pun langsung dijedotin ke tembok,” ujar Dorce.
Tidak itu saja! Entah bagaimana, ide menjatuhkan hukuman itu jenisnya bisa bermacam-macam. Dalam kesempatan lain, saat Dorce dianggap bandel atau berbuat kesalahan, jenis hukumannya jadi lain lagi. Suatu hari ia pernah disuruh makan segenggam cabai rawit segar. Ia tentu sangat kepedasan dan perutnya pun jadi sakit. Dorce bahkan mengaku pernah akan diceburkan ke dalam sumur karena dianggap melakukan kesalahan yang fatal. “Kalau hal itu terjadi dan saya pun mati, nama saya langsung ngetop seperti Ari Anggara,” kenang Dorce pahit.
DI BUANG KE BUKITTINGGI
Dorce mengakui bahwa selain bertambah pintar, pergaulan di sekolahnya juga membuat Dorce agak nakal. Namun, ia buru-buru menggarisbawahi pengakuannya itu. “Nakal saya masih wajar, seperti nakalnya anak-anak yang lain. Saya tidak sampai melakukan tindakan kriminal, mencuri atau menodong misalnya. Ya, namanya juga anak tidak ada yang mengurus, wajar kalau perkembangannya kemudian jadi agak tak terkendali.”

Rupanya, perkembangan Dorce ini membuat gundah para orang tua di Kramat Sentiong. Setiap terjadi keributan antara Dorce dan sepupunya di rumah itu, Dalimah –bibi Dorce– tampak sangat bingung memosisikan diri. Yang satu anak, satunya lagi keponakan. Setiap kali dia menegur anaknya untuk tidak kelewatan menghukum Dedi Yuliardi alias Dorce kecil, langsung dijawab ketus oleh putrinya, “Mak lebih sayang pada Dedi, ya?”
Akhirnya, daripada terjadi keributan terus-menerus, bibi Dorce dan suaminya memutuskan untuk membawa Dorce ke rumah kakak Dorce di Bukittinggi. Dorce pun tak bisa menampik. “Saya sesungguhnya tidak ada keinginan sedikit pun untuk pergi ke Bukittinggi,” tandas Dorce. “Saya seperti dipaksa karena saya dianggap beban bagi mereka. Hati saya, terus terang, berontak ketika itu. Kalau saat itu saya bisa melawan, saya akan melawan. Atau, kalau saja Nenek mampu untuk berjalan sendiri, maka saya akan membawa nenek saya keluar dari rumah itu. Tapi, saat itu Nenek sudah tak berdaya. Akhirnya saya pasrah, siapa tahu nasib saya nantinya lebih baik. Ya, akhirnya saya pun pamit pada Nenek, ‘Mak, Dedi balik ke Padang saja, ya. Siapa tahu Dedi kerasan tinggal di sana.’”
Neneknya tak menjawab. Namun, dari gurat-gurat wajahnya yang makin banyak, wanita tua ini tampak sangat keberatan ditinggal oleh cucunya yang satu ini. Dorce juga demikian. Meski keadaan sehari-harinya sangat tersiksa, Dorce sesungguhnya enggan meninggalkan rumah ‘penuh kisah’ itu. Masalahnya, ia sangat kasihan pada nasib neneknya. Selain sudah makin tua dan sakit-sakitan, neneknya itu acap kali mendapat perlakuan kasar dari salah seorang anggota keluarga itu.
MELARIKAN DIRI
Akhirnya, usai kenaikan kelas 3, Dorce pun diantar oleh pamannya ke rumah kakak Dorce (satu ibu lain ayah) di Bukittinggi. Kakaknya ini bekerja sebagai pegawai negeri dan sudah mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil. Dorce kemudian dimasukkan ke kelas 3 SD Negeri, tak jauh dari rumah kakaknya itu. Namun, di rumah ini pun Dorce tak menemukan kedamaian. Lagi-lagi kehadiran Dorce di rumah ini seakan tak diharapkan, sehingga bocah ini pun diperlakukan kurang baik. Secara fisik ia memang tidak disakiti, tapi, dengan sikap dan perlakuan orang-orang di rumah itu membuat jiwanya sangat tersiksa. Ia tidak pernah ditegur, apalagi diajak bicara dan bercanda. Padahal, seperti di Jakarta, ia juga bekerja apa saja di rumah itu.
Makin lama ia makin tidak betah tinggal di rumah. Pulang sekolah, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke Pasar Mandi Angin, yang lokasinya tak jauh dari sekolahnya. Di pasar ini ia mendengarkan musik atau main apa saja dengan anak-anak pasar.
Dorce pun akhirnya ‘mengaku kalah’. Saat kelas 4 SD, ia kabur dari rumah kakaknya itu. Ia langsung pergi ke rumah salah seorang pamannya di Padang. Namun, ibarat lepas dari mulut buaya dan masuk ke mulut singa, lagi-lagi Dorce harus mendapati kenyataan pahit. Di rumah itu ia acap kali mendapat perlakuan buruk dan kasar oleh anak-anak pamannya. Tak jarang ia dipukul dan dilempar dengan benda keras. Padahal, seperti kebiasaannya selama ini, selain sekolah ia juga bekerja keras, seperti layaknya seorang pembantu rumah tangga. Ia pernah disuruh mengangkat pasir dan melakukan pekerjaan yang lebih berat lainnya.
Dorce pun akhirnya banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Ia pergi bermain dengan teman-teman seusianya atau berdagang. Sepulang sekolah ia langsung menjajakan telur asin atau pisang goreng, agar-agar, tebu, dan sebagainya.
Suatu hari Dorce mendengar kabar bahwa neneknya sakit keras dan pamannya akan segera berangkat ke Jakarta untuk menengok. Kabar ini tentu saja sangat merisaukannya. Baginya, satu-satunya orang yang masih hidup yang mengasihinya dengan tulus hanyalah neneknya. Kini wanita itu terkapar sakit tanpa daya. Ia yakin neneknya pasti sangat menunggu kehadirannya. Sayangnya, sang paman tidak bisa memahami betapa antara dirinya dengan neneknya memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Pamannya tak mengizinkan Dorce ikut serta pergi dengannya ke Jakarta. Dorce sangat sedih dan tidak mau menerima keputusan itu. Ia pun berontak dan menangis keras-keras sehingga paman dan keluarganya pun jengkel. Dorce akhirnya diikat di sebatang pohon pisang sampai tangisnya berhenti.
Kali ini Dorce tidak mau menyerah. Meski usianya baru sembilan tahun lebih, ia sudah memiliki keberanian yang luar biasa untuk berbuat sesuatu. Demi neneknya tercinta, ia pun nekat kabur dari rumah pamannya tanpa membawa uang sepeser pun. Dengan hanya berbekal baju yang melekat di tubuhnya, ia pun langsung menuju Pelabuhan Teluk Bayur. “Siapa tahu saya bisa menyelinap masuk kapal tanpa tiket,” pikirnya.
Kali ini tangan Tuhan membelai Dorce. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ia digandeng oleh seorang ibu yang berpakaian seperti seorang haji, menaiki tangga kapal Batang Hari yang akan menuju ke Jakarta. Entah kenapa semua petugas kapal itu seolah tak melihat bahwa ada seorang bocah yang naik kapal tanpa tiket dan membiarkan ibu haji itu menuntun Dorce memasuki kapal. Selama hampir tiga hari perjalanan dengan kapal, Dorce selalu diberi makan dan minum oleh ibu haji yang baik hati itu.
Setelah semalam menginap di rumah ibu haji, Dorce pun pamit untuk segera menemui neneknya di Kramat Sentiong. Namun, beberapa langkah menjelang rumah bibinya, kebetulan ia bertemu dengan salah seorang anak Dalimah. “Nenek Darama semalam meninggal dan siang ini akan dimakamkan,” katanya kepada Dorce.
Bak petir di siang bolong, kabar itu telah menghempaskan batinnya ke dalam kidung duka yang paling dalam. Wanita malang yang telah memberinya keteduhan batin dan kasih yang tulus itu kini telah tiada. Ia tertidur pulas tanpa pesan dan kata. Begitu menyaksikan jasad beku itu, Dorce langsung melampiaskan dukanya dalam tangis panjang memilukan di tengah tatapan heran bibi dan saudara sepupunya, karena kedatangan Dorce yang tiba-tiba. Tak ada lagi tempat mengadu, tak ada lagi tempat melepas kerinduan. Di benak Dorce, hidup terasa kian terjal dan memilukan
Padahal, meski masih anak-anak, ia maklum akan posisinya. Walaupun tinggal di rumah bibinya, ia tak bisa seenaknya. Karena itu, meski boleh dibilang masih anak-anak. ia pun membantu bekerja apa saja di rumah itu. Antara lain, menyapu, mengepel, mencuci, mengambil air, atau membantu memasak di dapur. Setelah agak besar, kalau ia sudah menyelesaikan tugasnya di rumah, ia pun langsung pergi bermain atau ke jalan besar untuk mencari uang saku. Maklum, ia tentu saja tidak bisa mengharapkan pemberian uang saku dari nenek atau saudaranya karena kehidupan mereka sendiri sangat pas-pasan. Ia menjajakan kue-kue di jalan atau membantu berjualan koran.
Perjalanan hidup Dorce selanjutnya makin kelabu. Sudah sejak lama Dorce merasakan ketidaknyamanan tinggal di rumah bibinya itu. Selain beban pekerjaannya di rumah itu kian berat, ia pun hampir setiap hari dimarahi dan mendapat hukuman dari sepupunya. Setiap hari ada saja tingkah laku atau pekerjaan Dorce yang dianggap salah yang membuat sepupunya itu naik pitam. Selain mulutnya tajam setiap kali marah, tangan sepupunya itu sangat keras kalau memukul atau mencubiti tubuh dan kaki Dorce. “Kaki dan tubuh saya jadi merah-hitam kalau habis dicubiti atau dipukuli oleh kakak sepupu saya itu,” keluh Dorce.
Ia tidak bisa melawan, selain karena takut, selisih usia mereka pun sangat jauh. Saat itu usianya baru sekitar delapan tahun sementara sepupunya sudah berkeluarga dan sudah punya satu anak. “Padahal, setiap hari saya juga membantu memomong anaknya. Kenapa setiap hari dia selalu memarahi dan menghukum saya?” tanya Dorce kesal.
Ada saja kesalahan yang ditimpakan kepadanya sehingga ia pun bingung harus bersikap bagaimana. Saat belajar di malam hari pun, bisa-bisa jadi sumber petaka. Ia menyadari dirinya tidak pintar sehingga untuk mempelajari sesuatu pun menjadi sangat sulit. Akibatnya, Dorce pun menjadi sasaran kemarahan sepupunya itu. “Kalau saya tidak segera bisa menghafal sesuatu, maka kepala saya pun langsung dijedotin ke tembok,” ujar Dorce.
Tidak itu saja! Entah bagaimana, ide menjatuhkan hukuman itu jenisnya bisa bermacam-macam. Dalam kesempatan lain, saat Dorce dianggap bandel atau berbuat kesalahan, jenis hukumannya jadi lain lagi. Suatu hari ia pernah disuruh makan segenggam cabai rawit segar. Ia tentu sangat kepedasan dan perutnya pun jadi sakit. Dorce bahkan mengaku pernah akan diceburkan ke dalam sumur karena dianggap melakukan kesalahan yang fatal. “Kalau hal itu terjadi dan saya pun mati, nama saya langsung ngetop seperti Ari Anggara,” kenang Dorce pahit.
MELARIKAN DIRI
 Akhirnya, usai kenaikan kelas 3, Dorce pun diantar oleh pamannya ke rumah kakak Dorce (satu ibu lain ayah) di Bukittinggi. Kakaknya ini bekerja sebagai pegawai negeri dan sudah mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil. Dorce kemudian dimasukkan ke kelas 3 SD Negeri, tak jauh dari rumah kakaknya itu. Namun, di rumah ini pun Dorce tak menemukan kedamaian. Lagi-lagi kehadiran Dorce di rumah ini seakan tak diharapkan, sehingga bocah ini pun diperlakukan kurang baik. Secara fisik ia memang tidak disakiti, tapi, dengan sikap dan perlakuan orang-orang di rumah itu membuat jiwanya sangat tersiksa. Ia tidak pernah ditegur, apalagi diajak bicara dan bercanda. Padahal, seperti di Jakarta, ia juga bekerja apa saja di rumah itu.
Akhirnya, usai kenaikan kelas 3, Dorce pun diantar oleh pamannya ke rumah kakak Dorce (satu ibu lain ayah) di Bukittinggi. Kakaknya ini bekerja sebagai pegawai negeri dan sudah mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil. Dorce kemudian dimasukkan ke kelas 3 SD Negeri, tak jauh dari rumah kakaknya itu. Namun, di rumah ini pun Dorce tak menemukan kedamaian. Lagi-lagi kehadiran Dorce di rumah ini seakan tak diharapkan, sehingga bocah ini pun diperlakukan kurang baik. Secara fisik ia memang tidak disakiti, tapi, dengan sikap dan perlakuan orang-orang di rumah itu membuat jiwanya sangat tersiksa. Ia tidak pernah ditegur, apalagi diajak bicara dan bercanda. Padahal, seperti di Jakarta, ia juga bekerja apa saja di rumah itu.
Makin lama ia makin tidak betah tinggal di rumah. Pulang sekolah, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke Pasar Mandi Angin, yang lokasinya tak jauh dari sekolahnya. Di pasar ini ia mendengarkan musik atau main apa saja dengan anak-anak pasar.
Dorce pun akhirnya ‘mengaku kalah’. Saat kelas 4 SD, ia kabur dari rumah kakaknya itu. Ia langsung pergi ke rumah salah seorang pamannya di Padang. Namun, ibarat lepas dari mulut buaya dan masuk ke mulut singa, lagi-lagi Dorce harus mendapati kenyataan pahit. Di rumah itu ia acap kali mendapat perlakuan buruk dan kasar oleh anak-anak pamannya. Tak jarang ia dipukul dan dilempar dengan benda keras. Padahal, seperti kebiasaannya selama ini, selain sekolah ia juga bekerja keras, seperti layaknya seorang pembantu rumah tangga. Ia pernah disuruh mengangkat pasir dan melakukan pekerjaan yang lebih berat lainnya.
Dorce pun akhirnya banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Ia pergi bermain dengan teman-teman seusianya atau berdagang. Sepulang sekolah ia langsung menjajakan telur asin atau pisang goreng, agar-agar, tebu, dan sebagainya.
Suatu hari Dorce mendengar kabar bahwa neneknya sakit keras dan pamannya akan segera berangkat ke Jakarta untuk menengok. Kabar ini tentu saja sangat merisaukannya. Baginya, satu-satunya orang yang masih hidup yang mengasihinya dengan tulus hanyalah neneknya. Kini wanita itu terkapar sakit tanpa daya. Ia yakin neneknya pasti sangat menunggu kehadirannya. Sayangnya, sang paman tidak bisa memahami betapa antara dirinya dengan neneknya memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Pamannya tak mengizinkan Dorce ikut serta pergi dengannya ke Jakarta. Dorce sangat sedih dan tidak mau menerima keputusan itu. Ia pun berontak dan menangis keras-keras sehingga paman dan keluarganya pun jengkel. Dorce akhirnya diikat di sebatang pohon pisang sampai tangisnya berhenti.
Kali ini Dorce tidak mau menyerah. Meski usianya baru sembilan tahun lebih, ia sudah memiliki keberanian yang luar biasa untuk berbuat sesuatu. Demi neneknya tercinta, ia pun nekat kabur dari rumah pamannya tanpa membawa uang sepeser pun. Dengan hanya berbekal baju yang melekat di tubuhnya, ia pun langsung menuju Pelabuhan Teluk Bayur. “Siapa tahu saya bisa menyelinap masuk kapal tanpa tiket,” pikirnya.
Kali ini tangan Tuhan membelai Dorce. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ia digandeng oleh seorang ibu yang berpakaian seperti seorang haji, menaiki tangga kapal Batang Hari yang akan menuju ke Jakarta. Entah kenapa semua petugas kapal itu seolah tak melihat bahwa ada seorang bocah yang naik kapal tanpa tiket dan membiarkan ibu haji itu menuntun Dorce memasuki kapal. Selama hampir tiga hari perjalanan dengan kapal, Dorce selalu diberi makan dan minum oleh ibu haji yang baik hati itu.
Setelah semalam menginap di rumah ibu haji, Dorce pun pamit untuk segera menemui neneknya di Kramat Sentiong. Namun, beberapa langkah menjelang rumah bibinya, kebetulan ia bertemu dengan salah seorang anak Dalimah. “Nenek Darama semalam meninggal dan siang ini akan dimakamkan,” katanya kepada Dorce.
Bak petir di siang bolong, kabar itu telah menghempaskan batinnya ke dalam kidung duka yang paling dalam. Wanita malang yang telah memberinya keteduhan batin dan kasih yang tulus itu kini telah tiada. Ia tertidur pulas tanpa pesan dan kata. Begitu menyaksikan jasad beku itu, Dorce langsung melampiaskan dukanya dalam tangis panjang memilukan di tengah tatapan heran bibi dan saudara sepupunya, karena kedatangan Dorce yang tiba-tiba. Tak ada lagi tempat mengadu, tak ada lagi tempat melepas kerinduan. Di benak Dorce, hidup terasa kian terjal dan memilukan!
Sepeninggal neneknya, April 1972, Dorce seperti orang linglung. Ia bingung dan pikirannya gelap. Hampir setiap hari ia mendatangi  makam neneknya itu di Pemakaman Kawi-Kawi di daerah Kramat Sentiong. Ia merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi karena wanita yang sangat disayanginya telah tiada.
makam neneknya itu di Pemakaman Kawi-Kawi di daerah Kramat Sentiong. Ia merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi karena wanita yang sangat disayanginya telah tiada.
Hidup jadi makin hambar dan tandus, sehingga kadang-kadang terpikir untuk secepatnya menyudahi hidupnya dan menyusul orang-orang yang sangat disayanginya: nenek, ibu, dan ayahnya! “Saya benar-benar sangat shock. Saya nekat kabur dari Padang, hanya ingin bertemu dengan Nenek. Ternyata, sampai di Jakarta saya hanya bisa bertemu jenazahnya. Bagaimana saya tidak terpukul sekali?” kenangnya sembari mengusap matanya.
Sebelumnya, ketika tinggal di rumah pamannya di Padang, selama berbulan-bulan ia diliputi kegundahan dan kedukaan yang sangat dalam. Anehnya, perasaan bingung dan sedih ini ternyata juga dirasakan oleh Nenek Darama. Menurut Solwani, beberapa bulan menjelang ajalnya tiba, Nenek selalu mencari-cari Dorce, cucunya yang sangat disayanginya itu. “Ketika Mak sakitnya makin berat, dia sering menangis dan terus-menerus menanyakan kabar dan nasib Dedi,” kata Solwani, yang memanggil Dorce dengan panggilan Dedi, nama kecil Dorce. “Saat itu saya bilang sama Mak, ‘Mak, tak usahlah berat-berat pikirkan Dedi. Dia kan anak laki-laki, jadi tak mungkin dia hamil atau berlaku yang tak senonoh. Siapa tahu Dedi nanti kalau sudah besar malah jadi ‘orang’, yang mampu mengangkat harkat keluarga,’” tutur Solwani.
“Dia kan masih terlalu kecil, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Mak dengar dia pergi tanpa membawa uang sepeser pun. Bagaimana dia makan? Mak sangat khawatir jangan-jangan dia saat ini kelaparan,” sergah Nenek Darama.
“Mak, Dedi tak mungkin kelaparan. Dia itu kan anaknya rajin, pasti akan banyak orang yang mengasihinya dan memberinya makan. Yakinlah Mak, pasti banyak orang yang mau menolong Dedi. Karena itu, Mak jangan terlalu panjang mikirin dia. Mak sendiri nanti yang susah!”
HIDUP MENGGELANDANG
Setelah beberapa hari neneknya dimakamkan, Dorce melanjutkan sekolahnya di kelas 5 SD Salmin, tempat dulu Dorce pernah sekolah. Ia kembali tinggal di rumah bibinya di Kramat Sentiong. Seperti sebelumnya, sepulang sekolah ia membantu pekerjaan yang ada di rumah itu.
“Ya, seperti dulu ketika tinggal di situ, saya mengerjakan pekerjaan apa saja yang ada di rumah itu. Menyapu, mengepel, membereskan tempat tidur, mencuci, menimba air, dan sebagainya,” kata Dorce.
Hari-hari kelabu pun mulai terulang lagi. Setiap kali Dorce dianggap salah, cacian dan hukuman itu akan menderanya lagi. Berbeda dengan dulu, kali ini Dorce berani bersikap atau bahkan agak melawan. Bukan dengan melawan atau membantah langsung, tapi dengan cara lain. Setiap kali mendapat perlakuan buruk, ia langsung kabur dari rumah itu. Kalau tidak menginap di rumah tetangga, ia biasanya menginap di rumah teman-teman sekolahnya. Biasanya, bibinya akan datang menyusul dan menyuruhnya segera pulang. “Di, sudahlah… tak usah kamu pikirkan perlakuan kakakmu. Ayo, kita pulang. Besok kamu kan sekolah, nanti belajarmu terlambat,” bibinya berusaha merayu Dorce. Dorce pun pulang.
Belakangan, Dorce tidak tahan lagi atas perlakuan sepupunya itu. Ia pun kabur dari rumah itu dan tidak mau pulang lagi, meski dijemput oleh bibinya. Ia tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Saat itu sempat terlintas untuk menjadi seorang penjahat. Maklum, lingkungan pergaulannya kebetulan anak-anak nakal dan jahat. Hampir semua obat-obatan yang membuat orang teler, seperti megadon, ia coba. Setiap hari ia mabuk akibat minuman keras yang dicampur-campur. “Efeknya ternyata sangat dahsyat. Saya bisa bertahan tidak tidur selama tiga hari tiga malam,” kata Dorce. “Saat itu hidup saya sudah benar-benar kacau, sehingga saya sudah tidak berpikir lagi akibatnya.”
Saat itu Dorce pernah bermaksud melukisi dirinya dengan tato agar tampak lebih macho, tapi diurungkannya. Hari demi hari hidupnya makin liar karena ia banyak hidup menggelandang. “Tapi, kehidupan saya menggelandang itu tidak seperti gembel,” sergah Dorce. “Pakaian saya masih rapi. Saya tidak pernah minta-minta di jalan atau di rumah-rumah, apalagi menodong. Tidak pernah! Saya bisa makan dan membiayai sekolah karena saya bekerja. Entah berjualan koran, kue, atau menjadi kondektur bus. Kalau lapar dan tidak punya uang, barulah saya terpaksa pergi ke rumah saudara, tetangga, teman-teman, atau ke rumah Titiek Puspa untuk minta makan. Sikap menggelandang saya itu hanya cara hidup saya yang semau gue. Saya tinggal dan menginap di mana pun, sesuka saya. Kadang-kadang saya tinggal di rumah saudara-saudara saya, di rumah tetangga yang bernama Ibu Jaja, di rumah teman-teman sekolah, atau di gerobak soto kaki Betawi di depan masjid di Kramat Sentiong. Saya juga pernah tidur di pul bus Damri di Kemayoran.”
Selain di daerah Kramat Sentiong, wilayah Dorce bermain adalah Gang Lontar, Kramat Sawah, Kramat V/VI/VII, Gang R, Rivoli, Salemba Bluntas, dan sebagainya. Kendati hidupnya sedemikian kacau, ia masih terus masuk sekolah, walau sering kali membolos. Ia sudah tidak mau lagi pulang ke rumah bibinya, kendati berulang kali disusul oleh bibinya untuk pulang. Kadang-kadang ia membantu para pedagang nasi di pinggir jalan dengan mencucikan piring, gelas, dan pekerjaan lainnya. Ia bahkan pernah jadi kondektur bus kota jurusan Lapangan Banteng-Blok M dan Lapangan Banteng-Grogol. Dalam kesempatan tertentu, kadang-kadang sifat usilnya muncul. Dulu, kalau hari sudah mulai larut malam, banyak waria yang beraksi di depan Hotel Indonesia. Sambil bergelantungan di pintu bus, Dorce pun berteriak-teriak di depan mereka, “E, bencong-bencong… ngapain lu di situ!”
KENAL DENGAN TITIEK PUSPA
Suatu hari, saat ia menginap di rumah salah seorang saudaranya di Menteng Wadas, Manggarai, ia melihat Titiek Puspa bersama suaminya, Mus Mualim, mengendarai mobilnya lewat di depan rumah saudaranya. Dari informasi saudaranya ia akhirnya mengetahui bahwa rumah pasangan suami-istri seniman itu ternyata di Jalan Sukabumi, tidak jauh dari rumah saudaranya. “Saat itu ada dua penyanyi Indonesia yang menjadi favorit saya, yaitu Titiek Puspa dan Elly Kasim. Sudah sejak lama saya ingin kenal mereka!” papar Dorce.
Dorce menyadari, tidak mudah untuk mengenal artis yang sangat terkenal seperti mereka. Karena itu, harus ada cara khusus untuk bisa bertemu mereka. Setelah memeras otak, ia pun akhirnya menemukan caranya. Dari rumah saudaranya ia berjalan menuju ke rumah Titiek Puspa. Setelah yakin bahwa sang artis pujaannya berada di rumah, ia pun segera beraksi. Ia berjalan mondar-mandir di depan rumah itu, lalu ia nyanyikan keras-keras lagu-lagu artis favoritnya, seperti Minah Gadis Dusun, Bimbi, Bing, Cinta, dan sebagainya.

Pancingan Dorce ternyata berhasil. Titiek Puspa keluar dari pintu rumahnya bersama Mus Mualim, lalu memanggil Dedi Ashadi alias Dorce kecil (saat itu berusia 10 tahun) masuk ke rumahnya. Setelah berkenalan, Dorce kemudian diberi minum dan makan oleh Titiek. Sejak itu ‘pertemanan’ Dorce dan Titiek pun berlanjut terus. Dorce memanggil pasangan suami-istri itu dengan panggilan Tante Titiek dan Oom Mus. Hari-hari selanjutnya pasangan suami-istri itu tahu bahwa setiap kali Dorce datang, ia tengah kelaparan sehingga disuruhnya langsung ke dapur mencari makanan sendiri.
Sebaliknya, Dorce juga tahu diri. Setiap kali selesai makan, ia mencuci piring dan semua peralatan yang ada di dapur, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Belakangan, ia bahkan tinggal di situ berbulan-bulan dan tidur bersama Mbah Nah, pembantu Titiek Puspa, di lantai dua. Belakangan Dorce sering diajak pergi Titiek Puspa ke studio rekaman, ke kantor Papiko (Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota), dan sebagainya.
Selanjutnya, dengan caranya sendiri Dorce juga berhasil mengenal Elly Kasim. Belakangan ia juga berhasil mengenal artis cilik di masa itu, seperti Adi Bing Slamet, Iyut Bing Slamet, Chicha Koeswoyo, Santi Sardi, dan sebagainya. Dengan mengenal mereka, ia berharap cita-citanya untuk menjadi penyanyi akan segera bisa terwujud. Namun, rupanya mereka kelewat sibuk sehingga Dorce tidak bisa menggantungkan cita-cita itu pada mereka. “Kalau ingin berhasil, saya harus berusaha sendiri!” tekadnya pada diri sendiri.
DITOLAK NAIK PANGGUNG
Jauh hari sebelum mengenal para penyanyi papan atas Indonesia itu, berbagai upaya untuk menjadi seorang penyanyi terus ia lakukan. Suatu hari, ketika ia masih kelas 2 SD, ada acara perayaan peringatan HUT Kemerdekaan RI di depan rumah bibinya di Kramat Sentiong, yang salah satu acara hiburannya adalah band lengkap dengan penyanyinya. Saat itu Dorce memberanikan diri menghubungi pimpinan band itu untuk bisa menyumbangkan satu-dua lagu. Tapi, tawarannya ditolak karena pimpinan band itu melihat Dorce tidak layak untuk ditampilkan. “Tidak, kamu tak boleh nyanyi di atas panggung. Emangnya kamu bisa nyanyi?” kata pimpinan band itu.
Dorce sangat sedih dan sakit hati, tapi ia tidak ingin tenggelam dalam kepedihan itu. Ia tidak ingin menyerah sampai di situ. Suatu hari ia mendengar bahwa di Kolam Renang Cikini dan Senen, setiap liburan ada acara pentas musik. Ia datangi tempat-tempat itu. Selain menyaksikan pertunjukan musik, secara diam-diam ia mengadakan pengamatan pada para penyanyi dan pemusik yang tampil, seperti band Panbers, Arya Yunior, Bambang Brothers, dan sebagainya.
Dalam suatu kesempatan, pembawa acara Bambang Brothers menawarkan kepada penonton dan mereka yang tengah berenang untuk menyanyi. “Bagi para penonton dan yang sedang berenang yang ingin menyumbangkan lagu, kami persilakan,” kata pembawa acara.
Tanpa malu-malu Dorce yang sedang berenang segera mengenakan baju dan menemui pembawa acara itu. “Saya ingin membawakan lagu, Oom,” kata Dorce. Ia pun akhirnya naik panggung untuk menyumbangkan lagu. Meski usianya saat itu baru sekitar sembilan tahun, ia tidak menyanyikan lagu anak-anak. Ia justru menyanyikan lagu orang dewasa yang dibawakan oleh Edi Silitonga yang berjudul Bunga Mawar. Padahal, saat itu banyak lagu anak-anak, seperti lagu-lagu Adi Bing Slamet, yang sedang di puncak tangga.
Rupanya, Bambang, pimpinan band Bambang Brothers tertarik pada penampilan Dorce. “Saya ditawari Mas Bambang untuk bergabung,” kenangnya. “Saya pun langsung mengiyakannya. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan baik ini, sebab bagaimanapun saya harus banyak belajar dan berlatih agar bisa maju.”
Sejak itu Dorce memberanikan diri untuk menyewa tempat kos sendiri. Setiap kali tampil ia diberi honor seribu rupiah oleh Bambang. “Saya merasa sangat bangga sehingga tidak terlalu mikirin mau dibayar berapa. Karena itu, dibayar seribu perak pun senangnya bukan main. Tapi, nilai itu pun sudah lumayan, karena harga semangkuk bakso saat itu hanya lima perak!” ujarnya sambil tertawa.
Bambang kemudian membawa Dorce ke night club yang di tahun ‘75-an itu tengah menjamur di Jakarta dan kota besar lainnya. Ia diperkenalkan pada Abul Hayat, bos night club Latin Quarter di Harmoni. Dorce diterima sebagai penyanyi tetap di kelab malam itu. “Agar lebih irit, setiap kali mau menyanyi di Latin Quarter, sehabis magrib saya berjalan kaki dari rumah kos saya di daerah Kramat Sentiong ke Harmoni,” kenangnya.
Tidak mudah untuk bisa tampil di tempat itu kalau Dorce yang usianya belum genap 12 tahun saat itu tidak memiliki keistimewaan khusus. Akhirnya, selain manggung bersama Bambang, ia pun mulai tampil bersolo karier di kelab-kelab malam bergengsi yang lain, seperti LCC, Bloe Moon, Copacabana, dan sebagainya.
Lewat Bambang itu pula akhirnya ia mengenal Myrna, adik Bambang, yang menjadi pimpinan grup penyanyi dan penari Fantastic Dolls. Saat pertama kali melihat penampilan Myrna di panggung, Dorce berdecak kagum. “Buset, bencong-bencong ini menyanyinya bagus amat,” ujarnya penuh keheranan. “Awalnya saya merasa serem melihat mereka itu. Tapi, begitu melihat Myrna dan teman-temannya beraksi di atas panggung, saya baru merasa kagum. Mereka bisa berganti-ganti suara, dandanannya sangat fantastik, dan atraksi panggungnya pun sangat bagus!”
JADI MAKIN ’WANITA’
Meski tertatih-tatih, Dorce masih terus melanjutkan sekolahnya. Namun demikian, ia berhasil merampungkan pendidikan SD-nya tahun 1976 dan langsung melanjutkan ke SMP Kartini di daerah Kemayoran. Di sekolah inilah ia merasa sangat berat, baik dari segi biaya maupun kemampuan otaknya. Pertengahan kelas 2 di sekolah menengah pertama itu, ia berhenti melanjutkan belajarnya.
Selain masalah biaya dan kemampuan otak, ada lagi yang membuat Dorce makin tidak bisa konsentrasi belajar. Setelah mengenal Myrna lebih dekat, Dorce akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dorce makin sibuk sehingga ia acap kali mangkir dari bangku sekolah. Bersama grup Bambang dan Myrna ini langkah Dorce makin panjang lagi dan tampil ke berbagai kota di tanah air. Honornya pun sudah meningkat, lima ribu rupiah. “Saat itulah untuk pertama kali saya merasakan naik pesawat, dari pesawat Hercules sampai pesawat komersial yang terbagus saat itu,” tuturnya.
Selain pengetahuan bermusik dan pengalaman naik-turun panggung di berbagai kota di Indonesia, saat bergabung dengan Myrna dan teman-temannya, Dorce merasa menemukan jati dirinya. “Jati diri saya sebagai wanita makin eksis,” paparnya berterus terang. “Meski fisik saya lelaki, sejak kecil saya merasakan jiwa saya bukan lelaki. Saat masih kanak-kanak dan suka mengaji di Al-Wasliyah, saya bahkan jealous saat teman mengaji saya, seorang gadis yang bernama Siti, ditaksir oleh seorang cowok yang ganteng. Kenapa? Karena saya juga naksir pada cowok itu. Jadi, sejak kecil saya tidak pernah tertarik pada wanita. Saya bahkan jijik dan geli kalau tanpa sengaja melihat buah dada wanita.”
Dorce mengaku, meski dia bandel, sejak kecil perasaannya sangat halus. Ia lebih suka bermain dengan anak-anak wanita dan jenis permainannya untuk anak-anak perempuan, seperti main congklak, bola bekel, karet gelang, dan sebagainya.
Sekali waktu, godaan untuk merasakan menjadi seorang wanita itu datang tak tertahankan lagi. Apa yang harus dilakukan agar batin terpuaskan, tapi di sisi lain orang tidak curiga pada sikapnya? Salah satu ide di antaranya adalah membuat lucu-lucuan di rumah itu. Suatu malam ia mengambil rok Bibi Dalimah dengan dalih berpura-pura jadi setan untuk menakut-nakuti orang-orang di rumah itu. Hal ini tentu saja membuat semua orang di rumah itu tertawa.
Dalam kesempatan lain ia berusaha menghibur neneknya dengan sengaja mengenakan baju sang nenek. Selain merasa nyaman mengenakan baju-baju itu, ia juga berhasil menghibur neneknya. “Pada saat-saat Mak sedih, hanya Dorce yang bisa menghiburnya,” ujar Solwani, bibi Dorce.
Menurutnya, ada saja cara Dorce menghibur neneknya itu. Katanya, “Dia ambil kain, baju, dan kerudung Mak, lalu dia pakai. Setelah itu, ia pun berlenggak-lenggok sambil menyanyi atau melawak di depan Mak. Tentu saja Mak terpingkal-pingkal dibuatnya.
Dalam kesempatan lain, ia menghibur Mak dengan berjalan seperti seorang wanita yang lemah gemulai atau gadis yang centil. Hebatnya, ia juga bisa melawak dengan mengubah-ubah suaranya. Bisa seperti seorang gadis, nenek-nenek, atau bapak-bapak.
“Sejak dulu anak itu memang memiliki bakat yang sangat besar untuk menghibur orang,” tambah Solwani. “Tapi, kami semua tidak ada yang memperkirakan Dorce akan menjadi artis seperti sekarang. Kakak saya sempat bertanya-tanya, ‘Anak ini gedenya akan jadi apa,sih, kok, bisa mengubah-ubah suaranya seperti itu?’”
Sementara banyak saudara lain kagum, salah seorang anak Dalimah justru memarahi Dorce habis-habisan, “Ded, lu ngapain pakai pakaian Nenek seperti itu. Lu ini pengin jadi banci, ya!”
Apa pun kata orang terhadap Dorce saat itu, baginya yang terpenting neneknya bisa terhibur olehnya. Pada saat-saat seperti itu ne-neknya bisa tertawa terkekeh-kekeh dan tampak sangat bahagia. Meski cucu lelakinya itu mengenakan baju-bajunya, ia tak pernah memarahinya. Ia bahkan pernah mengajari cucunya itu mengenakan taluak, penutup kepala dari kain selendang yang dilipat sedemikian rupa khas Sumatra Barat. Neneknya baru menegur Dorce kalau cucunya itu keseringan mengenakan baju-bajunya. Itu pun dengan gaya bercanda, “Ka jadi padusi wa angko (kamu memangnya ingin jadi wanita)!”
Sebagai orang tua, Dalimah, bibinya, diam-diam juga sudah memaklumi kelainan yang terjadi pada keponakannya itu. Ia pernah marah ketika mengetahui beberapa bajunya sering kali disembunyikan dan dipakai oleh Dorce. Namun, Dorce pintar membuat alasan yang masuk akal. Yaitu, sebagai seorang penyanyi, dia harus bisa menghibur orang dengan hal-hal yang lucu. Lebih-lebih ketika bibinya itu pernah menyaksikan Dorce mengenakan bajunya saat di panggung. Saat mengisi acara peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus itu, Dorce tampil sebagai nenek-nenek. Lama-kelamaan bibinya pun maklum dan akhirnya membiarkannya keponakannya itu bergaya layaknya wanita.
Dorce mendapatkan banyak ‘pelajaran’ kehidupan saat bergabung dengan Bambang Brothers dan kelompok nyanyi dan tari Fantastic Dolls pimpinan Myrna yang beranggotakan para waria ibu kota. Selain ilmu bagaimana cara-cara menghibur penonton, ia pun mendapatkan nama baru yang diberikan oleh Myrna, yaitu Dorce Ashadi. Sejak itu, nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya, Dedi Yuliardi Ashadi, ia kubur dalam-dalam.
Nama barunya itu ternyata membawa hoki yang luar biasa untuknya. Hingga saat ini nama Dorce ini terus ‘berkibar’. Wajah dan kisahnya terus menghiasi layar-layar teve, majalah, tabloid, koran, dan berbagai media lain. Hebatnya lagi, Dorce seakan mampu membuai para penggemarnya untuk melupakan jati diri masa lalunya sebagai seorang bocah lelaki yang bernama Dedi. Dengan gaya panggungnya yang memikat, ia mampu menghibur para penonton yang menyaksikan pertunjukannya.
Dorce memang tergolong fenomena panggung. Sebagai penyanyi, ia mengaku tak ada yang mengajarinya, alias otodidak. Dia menyadari suaranya pun biasa-biasa saja, sehingga ia lebih suka disebut sebagai penghibur. “Saya juga heran kenapa job saya, kok, jalan terus,” ujarnya sembari terkekeh.
JADI KULI BANGUNAN
Dorce bersyukur bisa bergabung dengan Fantastic Dolls sehingga ia bisa mengembangkan bakatnya sebagai entertainer. “Kalau saya tidak bergabung dengan mereka, bisa-bisa hidup saya lebih liar,” Dorce berbicara terus terang. “Bukan tidak mungkin saya jadi pelacur yang setiap malam ngeceng di Taman Lawang atau berkeliaran di jalanan. Karena tak memiliki wadah untuk berekspresi dan hasrat saya sebagai wanita tidak bisa tersalurkan, maka hidup saya makin jalang dan tak terkendali. Dengan ikut Myrna, tanpa melacurkan diri pun saya bisa mengembangkan bakat saya sebagai penyanyi, pelawak, dan presenter.”
Namun, memasuki usia 15 tahun, hati Dorce mulai gelisah. Keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi solo makin menggebu-gebu. Niat bulat ini pun ia sampaikan kepada Bambang pimpinan Bambang Brothers dan Myrna pimpinan Fantastic Dolls, tempat dia bergabung sebagai penyanyi selama ini. Namun demikian, sebagai penyanyi solo pemula, ia tidak berani mengadu nasib di Jakarta, mengingat di kota ini sudah dipadati oleh penyanyi-penyanyi kenamaan papan atas dan menengah.
Tempat pertama yang dituju adalah Pulau Bali, pulau yang banyak didatangi wisatawan mancanegara. Saat itu di Bali sedang menjamur pub dan kelab malam. Suasana ‘mandi dolar’ inilah yang menggelitik Dorce untuk mengadu nasib di pulau itu. Dengan modal sejumlah uang yang dirasanya cukup, ia pun langsung berangkat ke Pulau Dewata dengan harapan bisa menangguk uang sebanyak-banyaknya.
Namun, harapan tinggallah harapan. Usaha untuk mendapatkan peluang job menyanyi di kelab-kelab malam maupun pub di Bali tak kunjung berhasil, sehingga ia akhirnya terdampar di Surabaya. Lama-kelamaan bekal yang dibawanya makin menipis, sementara ia tak memiliki saudara atau teman tempat untuk menumpang hidup. Padahal, dia harus bertahan hidup. Untuk kesekian kalinya ia harus menghadapi kehidupan yang paling sulit. Ia tak mempunyai uang lagi untuk makan, apalagi membayar kos. Apa boleh buat, lagi-lagi ia harus hidup menggelandang seperti yang pernah dialaminya lima-enam tahun yang lalu di Jakarta.
Namun, Dorce tak mau menyerah. Ia tidak ingin mati hanya karena tidak bisa makan. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak mendapatkan uang dari panggung musik, ia pun tidak malu-malu untuk mencari peluang pekerjaan lain. Ketika ada seseorang mengajaknya untuk menjadi kuli bangunan, ia pun tak menampik. Dorce remaja akhirnya bekerja sebagai kuli bangunan yang tugasnya mengaduk semen-pasir, mengangkatnya ke tempat bangunan, mengangkat bata, dan sebagainya. “Saya menjadi kuli bangunan itu hanya untuk bisa bertahan hidup. Dan itu pun tidak lama,” ujar Dorce tanpa menyebut waktu yang pasti.
Di lain pihak Dorce tetap kokoh dalam keinginannya. Tujuan utamanya keluar dari Jakarta adalah agar ia bisa menyanyi. Walaupun sampai menjadi kuli bangunan itu ia belum berhasil menjadi penyanyi, keinginannya tetap tidak surut. Siang hari jadi kuli bangunan, malam hari ia pergi dari kelab ke kelab. Di antara kelab malam itu, yang paling sering dikunjunginya adalah Kelab Malam Shinta. Di tempat inilah ia berkenalan dengan Mas Yoyok, seorang musisi di kelab malam itu. Meski berbeda agama, hubungan di antara keduanya makin dekat. Belakangan Dorce bahkan diangkat sebagai anak oleh Yoyok dan dicarikan pekerjaan yang sesuai keinginannya.
Dorce akhirnya berhasil dikontrak sebagai penyanyi di kelab malam. Di Kota Buaya ini pula Dorce makin berani menunjukkan identitasnya sebagai wanita. Setiap kali tampil sebagai penyanyi, ia sudah berani muncul dengan mengenakan rok. Yoyok kebetulan sangat baik dan sikapnya moderat. Sebagai musisi, ia sudah sering kali bergaul dengan orang-orang yang memiliki kelainan seks seperti Dorce, sehingga ia pun menyadari kelainan yang terjadi pada diri anak angkatnya itu. Karena itu, ketika dilihatnya Dorce tampil dengan mengenakan rok, ia pun diam saja. Ia tidak menegur, apalagi menertawakannya. Dan ternyata, tidak hanya keluarga Yoyok yang bersikap seperti itu. Para tetangga dan masyarakat Surabaya pun umumnya tak acuh saja pada perubahan yang terjadi pada dirinya. Mereka tetap ramah dan tak ada yang mencemooh maupun menghinanya.
Namun, apa yang dibayangkan ternyata jauh dari kenyataan. Untuk mencari uang lewat panggung di kota itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Suatu hari, pernah, ketika dia mendapat job menyanyi di suatu tempat, band pengiringnya ternyata tak bersedia mengiringinya. Dia tentu saja sangat tersinggung dan marah besar. Dengan gaya jailnya, Dorce pun naik ke atas organ band tersebut dan langsung menginjak-injak alat musik itu. Tentu saja pimpinan band itu kalang kabut dan akhirnya bersedia mengiringinya.
Berbagai pengalaman manis dan pahit didapatkan Dorce saat mencoba keberuntungan hidup di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu. Dorce akhirnya harus menentukan pilihan. Ia menyadari bahwa mengais rezeki di luar kota Jakarta hasilnya sangat terbatas. Ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan bergabung lagi dengan Bambang dan Myrna dalam kelompok Bambang Brothers dan Fantastic Dolls. Selain bersama mereka, di kota metropolitan ini Dorce masih bisa tampil di berbagai pentas musik yang lain, seperti di kelab malam atau tampil bersama Yan Berlin, Peter Hutabarat, atau penyanyi lain di Lory Organ di Glodok. Saat itu ia lebih sering mengenakan celana panjang, tapi terkesan centil.
SILIH BERGANTI PACAR
Meski tidak terlalu lama tampil sebagai penyanyi di Surabaya, diam-diam Dorce sudah memiliki penggemar sendiri. Terbukti, ketika dia kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Bambang Brothers maupun Fantastic Dolls, tahun 1982 ia kembali mendapat tawaranmanggung di Surabaya dan sekitarnya. Ia diminta menyanyi solo dan hanya mengajak dua rekannya penari latar dari Fantastic Dolls. Salah seorang yang diajaknya itu adalah Jacky Timortius, rekan mainnya saat ia masih anak-anak di Gang Sentiong yang hingga kini menjadi juru rias Dorce.
Setelah dua minggu tampil di berbagai tempat di kota itu, dua rekannya kembali ke Jakarta. Sedangkan Dorce, untuk sementara menetap di Kota Buaya itu. Selain tampil di beberapa kelab malam dan di berbagai acara, Dorce pernah juga diminta tampil menyanyi di atas kapal penumpang. Rute kapal itu umumnya dari Tanjung Perak, Surabaya, menuju ke berbagai kota besar di Indonesia Timur.
Sayangnya, kemesraan memadu karier bersama Bambang Brothers maupun dengan sesama rekannya sewaria di Fantastic Dolls yang kedua kalinya itu, akhirnya harus berhenti. Dorce bergabung pertama kali tahun 1973, lima tahun kemudian ia ‘terdampar’ di Surabaya hingga tahun 1980. Tahun 1983 ia benar-benar menyampaikan ‘selamat berpisah’ dengan kelompok yang dianggapnya telah menyelamatkannya dari dunia hitam. Ia merasa kariernya di kelompok sejenisnya ini sudah mentok. “Saya merasa nasib saya tidak akan berubah kalau saya bertahan terus di Fantastic Dolls. Selamanya saya tidak akan menjadi seorang bintang!” ujarnya. “Untuk menguji kemampuan, saya harus berani bersolo karier. Walaupun belum tentu berhasil, saya harus berani mengambil sikap!”
Selain itu, ada beberapa pertimbangan lain yang sifatnya sangat pribadi yang akhirnya mendorongnya untuk segera ‘lari’ ke Surabaya. Solwani, bibi Dorce, menceritakan bahwa beberapa minggu sebelum berangkat ke Surabaya, keponakannya itu datang ke rumahnya di Jalan Teluk Betung Ujung, Jakarta. Saat itu Dorce mengeluh bahwa dia sering diancam oleh pacarnya, seorang laki-laki. Setiap kali mendapat duit honor menyanyi, pacarnya itu selalu memaksa Dorce untuk menyerahkan semua honornya. Kalau tidak mau menyerahkan uang itu, Dorce diancam akan dipukuli.
Dorce tampak bergairah ketika diajak bicara tentang pacar-pacarnya. “Sejak usia 10 tahun saya sudah tertarik sama cowok, tapi baru di usia 15 tahun saya berani pacaran,” kenangnya sembari tersenyum. “Saya pacaran pertama kali dengan cowok dari Sumatra. Saat itulah untuk pertama kalinya saya merasakan nikmatnya dicumbu dan dicium oleh seorang pria. Saya sangat menikmatinya karena ternyata rasanya, wah… asyik betul.”
Ibarat bunga yang tengah mekar, Dorce tumbuh menjadi ‘gadis’ remaja yang dihampiri banyak perjaka. Bak seorang ‘gadis penakluk’, pacar Dorce pun silih berganti datang. Lepas dari pacar pertama, muncul pacar kedua, ketiga, dan seterusnya. “Pacar saya ada 12 orang dan semuanya ganteng-ganteng, lho…,” kenangnya sembari tertawa lebar. “Di antara mereka ada seorang polisi dan seorang anggota TNI. Tapi, hubungan kami tidak lama.”
Hubungan dengan pacar-pacarnya itu, ada yang manis, tapi banyak pula yang menyakitkan. Dorce mengaku pernah pacaran dengan seorang pria pemabuk dan suka main pukul. “Saya tak kuat dan kami pun berpisah,” ujarnya. “Saya kemudian pacaran lagi dengan anak yang masih sekolah di SMA yang tinggalnya di daerah Setiabudi. Ia bukan seorang pemabuk, tapi maling. Selain suka mengambil uang, sepatu mahal merek Kickers yang baru saya beli ternyata dicolong juga. Saat itu juga ia saya putuskan. Setelah itu, saya pacaran dengan anak kampus. Uang kuliahnya saya yang membayari, tapi ternyata dia masih selalu minta uang macam-macam. Saya terus-menerus diporotin sampai akhirnya uang saya ludes. Kalau tidak dikasih, dia suka mukulin. Saya tak tahan, dan saya pun kabur ke Surabaya.”
Selain urusan pacar, ada alasan lain yang paling utama bagi Dorce untuk segera berangkat ke Surabaya. “Saya ingin mencari status yang lebih jelas,” jelasnya. “Tekad saya sudah bulat dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya ingin menjalani operasi kelamin agar jati diri saya sebagai wanita sejati bisa segera terwujud. Saya tidak ingin batin saya terus-menerus tersiksa karena fisik saya yang pria sementara jiwa saya wanita. Saya masih ingat ketika almarhum Benyamin S. dulu manggung bersama saya. Ia selalu mencandai saya dengan sebutan Dorce LKPR. Maksudnya, Dorce yang laki-laki dan perempuan.”
Candaan seperti itu, bagi Dorce, hal yang biasa, karena kebetulan penyanyi Betawi itu membawakannya dengan cara yang manis dan enak didengar. Namun, di lubuk hati yang paling dalam, Dorce merasa tidak ingin hidup di dua kutub kehidupan yang terus-menerus membuatnya gundah. “Sejak kecil saya merasakan keganjilan pada diri saya,” ujarnya kecut. “Saya tidak ingin menipu diri saya sendiri atau orang lain. Wujud saya pria, tapi saya tidak pernah merasa sebagai pria. Saya merasa diri saya wanita, tapi wujud saya bukan wanita. Saya itu mungkin seperti wanita yang tomboi. Saya tidak ingin selamanya menjadi seseorang yang ‘seperti wanita’, tapi saya ingin menjadi seorang wanita yang seutuhnya wanita. Lahir-batin wanita!”
Untuk lebih menampilkan dirinya sebagai wanita, salah satu cara yang ditempuh Dorce adalah dengan membesarkan payudaranya, yaitu dengan cara meminum berbagai ramuan atau obat-obatan. Salah satu obat yang diminumnya adalah Lindiol. “Dulu, usai minum obat itu, hormon kewanitaan saya rasanya langsung naik ke ubun-ubun. Rasanya, wah, tak terbayangkan,” tuturnya kenes.
Dorce merasa saat itulah saat yang paling tepat untuk menemukan jati dirinya. Selain siap secara fisik dan mental, secara kebetulan ia sudah memiliki uang yang cukup untuk biaya operasi. Ia tahu, operasi ini bisa dilakukan di Jakarta, tapi, katanya, “Saya tidak tahu kenapa langkah kaki saya harus melangkah ke Surabaya. Mungkin Tuhan sudah menentukan di kota itulah saya menemukan jati diri saya sebagai wanita sejati!”
OPERASI KELAMIN
“Bodoh! Kamu ini laki-laki, ngapain pengin jadi wanita? Enakan juga tetap jadi laki-laki. Kalau kamu mau, kamu masih bisa diobati untuk menjadi seorang laki-laki sejati!” Demikian gertak seorang petugas medis kepada Dorce saat menyampaikan niatnya untuk operasi kelamin pada tahun 1983.
Dorce tentu saja sangat kaget. Di luar dugaannya, usaha untuk berganti kelamin itu ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dia pikir, kalau memiliki uang cukup, siapa pun bisa dengan mudah melakukan operasi kelamin. Saat mendatangi ruang praktik dr. Djohansyah Marzuki, SpBP, salah seorang dokter ahli bedah kenamaan di Surabaya, ia mengira proses menjalani operasi itu tidaklah sulit. Ternyata, sangat sulit dan lama! Ia harus menjalani berbagai pemeriksaan medis dan psikis yang panjang dan melelahkan.
Menurut dr. Dwidjo Saputro, SpKJ, prosedur untuk menjalani operasi kelamin itu tidak mudah. Ada surat keputusan dari Menteri Kesehatan yang mengatur untuk melakukan operasi-operasi seperti itu. Cara melakukan tindakan operasinya pun ada prosedurnya, di mana memerlukan berbagai disiplin ilmu. Antara lain, ahli bedah, ahli andrologi, ahli jiwa, ahli urologi, dan sebagainya. Selain medis, juga ada aspek hukum, sosial, dan sebagainya. Setelah melewati pemeriksaan yang ketat, barulah bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan memang mengalami atau tidak gangguan transeksual, sehingga orang tersebut dianggap memenuhi syarat atau tidak untuk menjalani operasi.
Setelah empat bulan menunggu, Dorce secara medis dinyatakan layak menjalani operasi pergantian kelamin. Tekad Dorce sudah bulat dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk mundur. Namun, saat mulai dirawat di rumah sakit, tiba-tiba ia kabur. “Saya sengaja pulang. Saya cukur semua rambut saya agar operasi itu berjalan lancar,” ujarnya tertawa.

Akhirnya, detik-detik paling menentukan dalam sejarah kehidupan Dorce pun mulai berlangsung. Kalau saja saat operasi itu ia tidak dibius total, bisa dibayangkan betapa menegangkannya peristiwa itu. Sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya kini harus menjalani perubahan total.
Semua ini tentu akan sangat mempengaruhi warna dan kehidupan selanjutnya. Beberapa saat sebelum menjalani operasi, ia pun berdoa, “Ya, Allah, kalau Engkau mengizinkan aku menjalani operasi menjadi seorang wanita, aku memohon selamatkan diriku dan lancarkanlah proses operasi ini. Aku ingin menjadi seorang wanita seutuhnya yang bisa menikah dengan seorang pria. Tapi, jika Engkau tidak rida, matikanlah aku seketika saat ini juga!”
Operasi kelamin dan payudara itu sendiri berjalan lancar dan sukses. Selama hampir empat jam Dorce mengalami mimpi yang sangat panjang. Begitu terbangun, Dorce langsung meraba dadanya dan bagian intimnya. “Saya bahagia sekali saat itu. Apa yang saya cita-citakan sejak lama akhirnya berhasil juga saya lakukan!” katanya bersemangat.
Heboh! Itulah yang terjadi kemudian setelah berbagai media tahu bahwa Dorce operasi kelamin. Meski bukan orang pertama yang melakukan operasi seperti itu (orang Indonesia pertama yang melakukan operasi kelamin adalah Vivian- Red), tak urung hal itu mengundang kehebohan yang luar biasa di berbagai media massa. Maklum, Dorce sedikit banyak sudah mulai dikenal sebagai artis panggung, sehingga tak urung mengundang berbagai polemik. Dan sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah, menanggapi hal yang kontroversial seperti ini tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra.
Anjing menggonggong kafilah berlalu. Dorce membiarkan pergunjingan tentang dirinya itu ditelan oleh waktu. Meski hati jengkel dan kuping panas, ia terus berjalan menapaki hari-harinya dengan penuh ketabahan. Ia terus pula naik turun panggung hiburan, memberi senyum manis terhadap penonton, dan meneriakkan tangis hatinya dalam lagu. Ada tepukan, ada tawa riang, ada gemuruh sukacita, tapi juga tidak sedikit cemooh dan teriakan penuh kedengkian. Semua itu dihadapinya dengan tabah, dengan gagah, dan dengan senyum merekah.
Waktu-waktu selanjutnya yang dilalui Dorce memang tidak mudah. Tapi, berkat hati lapang yang dimilikinya, petaka buruk itu justru membuahkan berkah yang luar biasa bagi Dorce. Berita-berita baik atau buruk, yang mendukung maupun menyerang, yang memuja atau mencela, setiap hari memenuhi halaman-halaman koran, majalah, maupun media elektronik. Hal itu ternyata malah menjadi promosi gratis bagi Dorce. Berita-berita itu justru melambungkan namanya.
Akhirnya, buah yang dipetik Dorce kemudian, selain jadwal manggungnya makin padat, ‘harga jual’nya pun jadi berlipat ganda. “Saya jadi kaget! Mereka yang selama ini memberi honor kepada saya hanya 250 ribu rupiah tiba-tiba jadi 500 ribu rupiah, sementara yang biasa memberi honor 500 ribu mendadak menjadi satu juta rupiah. Buah hikmah yang saya terima ternyata luar biasa!” ujar Dorce.
BERKAH TVRI
Berkah lain adalah ketika ia secara rutin tampil di TVRI Surabaya, sehingga namanya pun mulai dikenal banyak orang. Dari situlah ia diboyong oleh seorang pengusaha, Bernardi Halim, keliling Amerika untuk show dan menikmati keindahan negeri Paman Sam. Tahun 1987 ia diundang oleh SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) Indonesia untuk tampil di Ancol, Jakarta. Hadir dalam acara ini Menteri Penerangan Harmoko. Dua tahun kemudian ia diminta tampil selama satu jam di TVRI Pusat, Jakarta. Saat acara itu ditayangkan, Dorce tengah berada di Irian Jaya bersama Camelia Malik. Usai menyaksikan acara tersebut, istri Hary Capri itu langsung berkomentar di depan Dorce, “Wah, Dorce, acara ini bakalan meledak,deh!”
 Ramalan Camelia Malik ternyata tepat. Banyak orang menilai, penampilan Dorce saat menyambut HUT TVRI itu sangat sukses. Semua orang terkesima, sampai-sampai orang TVRI pun salah membayar honor Dorce. “Seharusnya honor saya hanya dua juta rupiah, tapi ternyata saya dibayar lima juta rupiah,” ujar Dorce sembari cekikikan. “Mungkin karena sudah telanjur, sisa honor itu tidak diminta kembali. Ya, memang sudah rezeki saya barangkali!”
Ramalan Camelia Malik ternyata tepat. Banyak orang menilai, penampilan Dorce saat menyambut HUT TVRI itu sangat sukses. Semua orang terkesima, sampai-sampai orang TVRI pun salah membayar honor Dorce. “Seharusnya honor saya hanya dua juta rupiah, tapi ternyata saya dibayar lima juta rupiah,” ujar Dorce sembari cekikikan. “Mungkin karena sudah telanjur, sisa honor itu tidak diminta kembali. Ya, memang sudah rezeki saya barangkali!”
Sejak itu tawaran manggung di seluruh kota di Indonesia untuk Dorce terus mengalir. Kadang-kadang sehari ia bisa tampil di tiga sampai lima panggung. Menurut rekan Dorce di Fantastic Dolls yang kini menjadi juru riasnya, Kiki, Dorce sangat berani gambling. “Dalam dua hari ia berani menerima tawaran di tiga kota yang sangat berjauhan, seperti Medan, Surabaya, dan Jakarta,” katanya.
Tahun 1990 ia pindah kembali ke Jakarta karena belakangan tawaran paling banyak justru datang dari Jakarta. Dorce kemudian mendapat tawaran main film. Tanpa disadarinya, ia menandatangani kontrak di dua film sekaligus sehingga nyaris membuatnya masuk pengadilan. Untunglah di antara kedua produser (Parkit Film dan Bola Dunia Film) bersedia diajak damai, sehingga bisa diselesaikan secara baik-baik. Kedua perusahaan tersebut bekerja sama membuat dua film sekaligus dengan pemeran utamanya Dorce, yaitu Dorce Sok Akrab dan Dorce Ketemu Jodoh.
Dorce juga masuk ke dapur rekaman Billboard dengan judul Cintaku Kendur di Jalan. Tapi, ternyata kurang laku. “Rupanya rezeki saya memang hanya dari panggung. Kecil saya terima, besar alhamdulillah,” ujarnya.
Selain itu, Dorce terus berusaha ‘mencuri’ ilmu dari para seniornya. Dorce mengaku bahwa pada awal penampilannya sebagai penyanyi, dia hanya menyanyi, tidak melawak dan tak menjalin hubungan dengan penontonnya. Setelah sering kali menyaksikan penampilan Titiek Puspa dan Benyamin S., ia pun berusaha menirunya. Sambil menyanyi ia berusaha ‘menggoda’ penonton dengan lawakan dan humor-humornya. Ternyata, suasana pertunjukan menjadi lebih cair dan jalinan komunikasi dengan penonton pun bisa lebih hidup.
Belakangan ia bahkan tidak hanya menampilkan guyonan-guyonan itu di saat-saat jeda menyanyi, tapi bahkan saat menyanyi. Cara itu pertama kali ia lakukan karena ia lupa pada lanjutan lagu yang sedang ia nyanyikan, dan secara spontan langsung ia pelesetkan. “Tapi, ternyata orang-orang suka, jadi cara-cara seperti itu saya lakukan hingga saat ini. Bagi saya, kesalahan ternyata membawa hikmah! Sekarang saya berani membawakan lagu apa pun, walaupun saya tidak hafal lagu itu.”
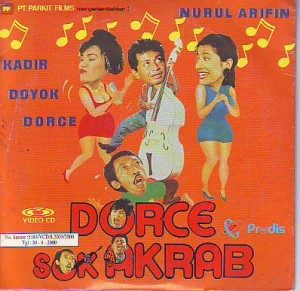
Namun, bukan berarti Dorce tidak bisa menyanyi dengan benar. Selain mampu menyanyikan berbagai lagu yang benar dalam berbagai irama (jazz, cha-cha, rock, pop, dangdut, dan sebagainya), ia juga fasih membawakan lagu dalam berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Cina, Balanda, Jerman, Prancis, Arab, India, dan sebagainya. Namun, ia merasa lebih sreg kalau disebut sebagai penghibur, bukan penyanyi. “Kalau yang namanya penyanyi itu adalah seperti Krisdayanti, Titi DJ, Melly Goeslaw, dan sebagainya. Saya tampil di panggung itu hanya sebagai penghibur,” ujarnya merendah.
Ia menyadari kekuatannya di panggung adalah karena spontanitas-spontanitasnya, baik dalam menyanyi, melawak, beraksi, maupun dalam melakukan olah gerak panggung. Itu sebabnya, setiap kali akan tampil di panggung, ia paling tidak mau kalau harus melakukan geladi bersih. “Saya lebih baik tidak manggung kalau harus ikut geladi bersih dulu!” tandasnya. “Bagaimana mungkin penampilan saya yang spontan kualitasnya sama saat geladi bersih dan saat pentas beneran?”
BERTEMU PRIA SEJATI
Usai menjalani operasi kelamin yang sukses itu, Dorce merasa seperti seorang bayi yang baru lahir. Saat itu mulai terpikir olehnya untuk menyempurnakan nama Dorce itu dengan nama komersial yang lain. Selama menjadi orang panggung, berbagai nama tambahan telah diberikan oleh rekan-rekannya sesama artis atau para penggemarnya. Almarhum Benyamin Sueb pernah menjulukinya Dorce LKPR, alias Dorce Pria Perempuan. Dorce juga pernah mendapat julukan Dorce Orang Aring dan Dorce Emco. Tapi, semua itu rupanya tak berhasil melambungkan namanya sehingga kemudian sirna dengan sendirinya.
Perjalanan waktu jualah yang akhirnya memunculkan ide nama itu. Suatu hari ia diundang untuk menyanyi di Ternate bersama Benyamin S. Dalam perjalanan itu ia melihat Gunung Gamalama yang tampak cantik dan tegar sendirian. Dorce merasa, nama gunung itu terdengar feminin tapi juga mencerminkan kekuatan. Akhirnya Dorce pun memutuskan nama baru untuk ‘kelahiran’ keduanya: Dorce Gamalama Ashadi! Nama Ashadi di belakangnya itu adalah nama ayahnya yang telah mewariskan darah seni pada dirinya.
Tahun 1990, pulang dari menunaikan ibadah haji di Mekah, Dorce menambahkan lagi nama Arab di belakang namanya. Nama lengkap Dorce terakhir menjadi Hajah Dorce Halimatussa’diyah Gamalama Ashadi. Nama Halimatussa’diyah tersebut diambil Dorce dari nama ibu susu Nabi Muhammad.
Program Dorce selanjutnya setelah menjadi wanita adalah menemukan suami ideal. Hati Dorce pernah tertambat pada berbagai tipe pria dari bermacam-macam suku. Meski belum lama di Surabaya, ia ternyata sudah menjalin hubungan dengan empat pria. “Tapi, saya hanya pacaran begitu-begitu saja,” sergahnya. “Berbeda dengan teman-teman lain yang suka membawa tamu night club ke rumah. Saya sama sekali tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melacurkan diri. Saya akui, waktu di Jakarta saya pernah ngecengmalam-malam bersama teman-teman waria di jalanan. Tapi, hanya satu-dua kali dan sifatnya iseng belaka,” lanjutnya.
Setelah operasi kelamin dan secara hukum resmi menjadi seorang wanita, Dorce tampak sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. “Dengan status saya sekarang sebagai wanita lahir-batin, saya berusaha mengubah sikap hidup diri saya secara total. Sesuai tuntunan agama, saya berusaha menjaga diri saya sebaik mungkin,” tegasnya.
Beberapa bulan sebelum menjalani operasi, Dorce berkenalan dengan arek Suroboyo yang kemudian menjadi pacarnya. Perkenalan dengan pria itu cukup unik. Sebelumnya Dorce mengenal ibu pria itu yang sehari-hari berjualan minyak wangi. Si ibu sering mengajak anak lelakinya itu ke rumah Dorce. Awalnya, di antara keduanya tidak saling tertarik. “Witing tresno jalaran soko kulino. Kami akhirnya saling jatuh cinta setelah kami sering bertemu,” tutur Dorce.
Berbeda dengan pria-pria yang pernah menjadi kekasihnya, pria yang satu ini selain tidakmatre juga penuh perhatian. Saat Dorce menyampaikan niatnya untuk operasi kelamin, pria itu hanya tersenyum dan berkata singkat, “Terserah awakmu (terserah kamu)!”
Saat akan menjalani operasi, pria itulah yang mengantarnya ke RS Dr. Sutomo Surabaya. “Sikap dan perhatiannya selama di rumah sakit membuat saya makin jatuh hati dan sulit melupakannya,” kenang Dorce.
Usai menjalani operasi, hubungan Dorce dengan pria itu terus berlanjut dan cenderung makin akrab. Tapi, kali ini ia berharap agar hubungannya itu tidak sekadar pacaran. Seperti wanita lain, ia ingin segera menikah karena secara lahir-batin ia sudah menjadi seorang wanita. Saat harapannya itu disampaikan kepada sang kekasih, pria itu agak kaget. Maklum, selain yang bakal dihadapi tantangan dari keluarganya yang pasti tidak ringan, saat itu ia masih mempunyai kekasih seorang wanita asli. “Ternyata ia memilih saya,” kenang Dorce sembari tersenyum.
Secara prinsip pria itu tidak keberatan untuk menikahi Dorce. Masalahnya, ada anggota keluarganya yang tidak setuju dan menentang rencana perkawinan itu. Kemarahan mereka pun sempat memuncak. Saat Dorce akan bersilaturahmi ke rumah keluarga pria itu, ia nyaris digebuk dengan stik golf. Untunglah, hal itu tidak sampai terjadi. Dan Dorce dapat melaksanakan impian terbesarnya: menikah dengan seorang pria!
DIAKUI SEBAGAI MENANTU
“O… niku mantu kulo (o… itu menantu saya),” jawab seorang ibu kepada tamunya yang menanyakan keberadaan Dorce di rumah itu. Ibu itu adalah mertua Dorce, ibu dari seorang pria yang secara resmi telah menikahinya. Bagi wanita lain, kalimat itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi, tidak bagi Dorce. Baginya, diakui sebagai menantu oleh keluarga itu adalah pengakuan yang sangat mengentak batinnya. Dirinya merasa sangat tersanjung dan hatinya pun langsung berbunga-bunga. Ia sangat bangga dan bahagia karena ibu mertuanya telah dengan tulus mengakuinya sebagai menantu.

Pengakuan mertuanya itu merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi sejarah kehidupan pribadi Dorce. Ia sangat memaklumi betapa ucapan itu sangatlah tidak mudah keluar dari mulut orang tua yang mengetahui asal-usulnya. Sebagai seorang wanita mantan pria, ia sadar betul posisinya. Karena itu, ketika usai operasi ada seorang pria yang datang melamar untuk menikahinya, dirinya serasa dinaikkan ke langit yang ketujuh. Dahsyat dan sangat menyentuh kalbunya!
Cerita di atas adalah klimaks dari kisah kasih Dorce karena sebelumnya sempat terjadi ketegangan yang luar biasa antara Dorce dengan keluarga suaminya. Akhirnya, pada 1986 Dorce berhasil menikah secara resmi dengan pria idamannya itu (Dorce kemudian memperlihatkan sehelai fotonya saat melangsungkan upacara ijab-kabul kepada femina, tapi ia keberatan kalau foto itu dimuat). Kehidupan awal pernikahannya sangatlah tidak mudah, terutama dalam menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya, khususnya kedua orang tua suami. Sempat terjadi ketegangan yang sangat hebat, tapi untunglah tidak berlangsung lama.
Dorce bisa memaklumi keadaan itu. Ia terus berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya sekarang sudah menjadi wanita sejati dan mampu menjadi seorang istri. Usahanya tidak sia-sia, karena belakangan Dorce bahkan diminta tinggal di rumah mertuanya. Kebahagiaan Dorce terasa lengkap ketika kedua orang tua itu mengakui dirinya sebagai menantunya. “Semua itu juga berkat dorongan suami saya,“ tutur Dorce.
Sayangnya, belakangan kebahagiaannya itu mulai terusik. Pasangan muda itu sering kali ribut tanpa jelas penyebabnya. Ada saja biang keributan itu yang membuat di antara keduanya perang mulut hebat. Dorce mengaku penyebab keributan itu sering kali justru datang dari dirinya. Sebagai wanita, ia merasa berdosa karena tidak mampu mempersembahkan anak. Tapi, pelampiasannya justru kebalikannya. Ia menjadi gampang tersinggung dan sangat pemarah.
Untuk meredakan emosinya, Dorce kemudian berusaha mengadopsi anak. Suatu hari, di depan rumahnya lewat seorang wanita yang tengah hamil enam bulan. Wanita itu sudah punya 12 anak dan bayi yang dikandungnya adalah anak ke-13. Dengan nada bercanda, Dorce berkata pada wanita hamil itu, “E, elu ini kayak kucing aja, beranak melulu! Entar, kalau anak ini lahir, untuk gue, ya?”
Ternyata, wanita itu tidak keberatan, begitu juga ketika dia memberitahukan suaminya. Dorce kemudian menanggung biaya perawatan dan kelahiran bayi itu. Anak yang lahir laki-laki dan oleh Dorce kemudian langsung dibawa pulang tanpa disusui ibu kandungnya. Secara resmi Dorce pun mengadopsi bayi itu dan memberinya nama Rizky. Saat itu lengkaplah sudah kebahagiaan Dorce. Ia mempunyai suami yang baik, mertua yang memaklumi keadaannya, dan bayi mungil yang melengkapi kehidupannya. Karena kesibukannya makin padat, Dorce lalu menggaji seorang baby sitter untuk mengurus bayinya.
Namun, di puncak kebahagiaannya itu, ada saja mulut-mulut yang usil. Akhirnya berbagai media pun meramaikannya dan menulis berbagai opini. Dengan status Dorce, mereka umumnya mencurigai kesungguhan Dorce mengadopsi bayi itu. Apa boleh buat, Dorce berusaha menerimanya dengan tabah sampai akhirnya suara-suara sumbang itu mereda.
Merasa senang memiliki anak, Dorce pun ingin mengadopsi anak lagi. Kali ini ia ingin sekali mengadopsi anak perempuan. “Saat itu saya seperti orang ngidam,” kenangnya. “Saking menggebunya keinginan saya itu, sampai terbawa mimpi saat tidur.”

Rupanya, keinginannya yang tulus itu dikabulkan oleh Tuhan. Suatu malam di tahun 1996, saat berada di Masjid Istiqlal Jakarta, ia tiba-tiba melihat seorang bayi perempuan yang terus-menerus menangis. Keadaannya mengenaskan sekali. Tubuhnya kotor, matanya belekan, dan bajunya pun lusuh. Dorce pun merasa trenyuh dan langsung membawa bayi itu bersama ibunya ke rumah sakit. Kesimpulannya, ibu bayi itu kurang gizi sehingga ASI (air susu ibu)-nya tidak keluar.
Setelah mendapatkan obat dan perawatan seperlunya di rumah sakit, bayi bersama ibunya pun langsung diajak Dorce ke rumahnya. Dari pembicaraan dengan ibu bayi itu akhirnya diketahui bahwa wanita itu ditinggal pergi oleh suaminya sehingga ia terpaksa menjadi pengemis di Masjid Istiqlal. Wanita itu tidak keberatan memberikan bayi itu kepada Dorce untuk diasuh dan dididik. Bayi usia setahun itu kemudian diberi nama Fatimah Zahra oleh Dorce. Hari itu makin lengkaplah kebahagiaan Dorce hidup bersama suami tercinta dan anak-anaknya. Belakangan ia mengadopsi satu anak perempuan lagi, yang diberi namaKhadijah.
MENCARI ISTRI BAGI SUAMI
Hari-hari indah penuh bintang itu ternyata harus berakhir. Pada titik puncaknya, Dorce harus menyadari keadaan dirinya. Meski kini lahir-batin sudah menjadi wanita, ia, toh, tidak bisa mempersembahkan keturunan bagi suaminya. Padahal, bagi sang suami, mendapatkan anak dari benihnya sendiri itu sangat dia dambakan. Dorce tidak ingin terus-menerus membelenggu keinginan suaminya itu untuk mempunyai anak. Daripada setiap saat merasa berdosa karena tidak bisa mempunyai anak dari hasil perkawinannya itu, maka lebih baik berpisah.
Pada awalnya perpisahan itu sulit dilakukan karena di antara keduanya masih saling mencintai. Suami Dorce tetap bersikeras untuk tidak menceraikannya, sementara Dorce enggan ditinggal suaminya. Tapi, Dorce terus mencari upaya agar perceraian itu segera terwujud. Ia pun sering kali membuat gara-gara agar suaminya marah. Antara lain, ia seolah-olah pacaran dengan pria lain. Maksudnya, kalau suaminya marah-marah, ia pun bisa langsung minta diceraikannya. “Kalau dia yang menceraikan, saya khawatir saya sendiri yang tidak siap,” keluhnya. “Saya ingin sayalah yang minta diceraikan olehnya sehingga saya tidak terlalu sakit hati!”
Akhirnya, setelah lima tahun berumah tangga, perceraian Dorce dan suaminya pun tak bisa dihindarkan lagi. Tapi, perceraian mereka dilakukan dengan baik-baik. Dorce pun berusaha mencarikan calon istri bagi mantan suaminya. Dia kenalkan mantan suaminya dengan beberapa teman wanitanya. Begitu mulusnya perceraian itu sehingga hubungan Dorce dengan keluarga mantan suaminya pun tetap baik. Selain itu, meski sudah bercerai, di antara keduanya tidak langsung berpisah. Mantan suaminya tidak segera menikah, meski sudah banyak wanita yang sudah dia kenalkan kepadanya.
Dorce pun terpaksa harus pergi meninggalkan rumahnya dalam waktu yang lama, agar mantan suaminya segera meninggalkannya. Akhirnya mantan suaminya pun menikah, tapi tak berlangsung lama. Setelah itu, mantan suaminya menikah dengan wanita yang lain lagi dan bercerai lagi. Baru pada pernikahan ketiga setelah Dorce, perkawinan mantan suaminya agak awet. “Saya dengar, ia mencari wanita yang sifatnya mirip saya. Artinya, saya ternyata bisa menjadi seorang istri yang baik. Buktinya, mantan suami saya pun masih mencari istri yang seperti saya!” ujar Dorce.
Dorce pun demikian juga. Setelah lima tahun berpisah, ia pernah berpacaran dengan seorang pria. Semula ia pikir pacarnya itu seperti mantan suaminya. Ternyata tidak. Sehingga, setelah setengah tahun berpacaran, Dorce pun meninggalkannya. Bagi Dorce, tidak ada pria sebaik mantan suaminya. “Dia memang pria sejati,” kenangnya. “Dia dengan tulus mau memperistriku, membawa masuk ke dalam keluarganya, dan memperlakukanku dengan sangat baik. Sejak itu aku berjanji untuk tidak akan pacaran atau kawin lagi!”

DUA MIMPI DORCE
Dorce mengaku hidupnya saat ini sangat bahagia. Sejak operasi kelamin, menikah, dan ‘mempunyai’ anak, kariernya terus melejit bak meteor. Namanya terus mencuat, tawaran untuk manggung pun nyaris tak pernah berhenti. Alhasil, rezeki pun terus mengalir. Dari hasil ‘ngamennya’ itu, ia bisa memiliki rumah, tanah, mobil, dan sejumlah deposito. Selain berhasil membangun sekolah tiga lantai, yayasan, dan rumah gadang pusat dokumentasi sebagai persembahan terhadap neneknya tercinta, ia juga berhasil membiayai saudara-saudara dan orang-orang terdekatnya menunaikan ibadah haji ke Mekah.
 Sebagai seorang artis, dia juga cukup berhasil. Selain masih terus eksis dan memiliki ‘nilai jual’ tinggi, ia termasuk dari sedikit artis yang mendapat kesempatan tampil di Istana Negara. Itu pun tidak hanya sekali dua kali. Dari lima presiden yang pernah memimpin negeri kita, empat presiden pernah dihiburnya. Yaitu, Presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri.
Sebagai seorang artis, dia juga cukup berhasil. Selain masih terus eksis dan memiliki ‘nilai jual’ tinggi, ia termasuk dari sedikit artis yang mendapat kesempatan tampil di Istana Negara. Itu pun tidak hanya sekali dua kali. Dari lima presiden yang pernah memimpin negeri kita, empat presiden pernah dihiburnya. Yaitu, Presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri.
Namun, kebahagiaan dan kebanggaan Dorce acap kali terusik. Ada dua impian yang sering kali mengganggu kalbunya. Impian yang pertama adalah penghargaan dari pemerintah. Sebagai artis, ia merasa sudah mengabdi pada dunianya secara total dan penuh dedikasi. Ia tampil di daerah yang sangat terpencil, di daerah-daerah konflik, sampai Istana Negara. Ia juga sudah sering diundang ke berbagai negara asing yang tentu saja membawa keharuman bangsa. “Suatu saat saya ingin sekali mendapat penghargaan dari pemerintah, syukur-syukur dari presiden,” tuturnya penuh harap.
Impian kedua lebih bersifat duka lara sebagai anak manusia. Meski saat ini masyarakat nyaris melupakan dirinya sebagai mantan pria, di lingkungan keluarganya ia seolah masih menjadi aib. Banyak di antara para sesepuh dalam keluarganya yang belum dengan tulus menerimanya sebagai wanita, sehingga ia pun sering merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh keluarganya sendiri.
Di hadapan mereka, derita Dorce seolah belum cukup. Padahal, sejak bayi ia sudah yatim-piatu, masa kanak-kanaknya tersiksa serta terlunta-lunta. Hingga kini ia merasa hidupnya sebatang kara. “Entah kenapa, kok, begitu teganya mereka memperlakukan saya seperti ini,” tuturnya dengan nada datar dan mata berkaca-kaca. “Saudara saya banyak, tapi saya seperti tak punya saudara. Dalam keadaan saya seperti sekarang saja, mereka memperlakukan saya seperti ini. Bagaimana nanti kalau saya tidak punya apa-apa lagi?”
Tragisnya, ada saja di antara saudara-saudaranya itu yang belum sepenuhnya menerima keberadaan Dorce. Saat di Tanah Suci, salah satu di antara saudaranya itu justru membuka aib Dorce, si bungsu yang telah membiayai sepenuhnya ke Tanah Suci. “Kepada rekannya sesama jemaah haji, ia memfitnah dan menjelek-jelekkan saya habis-habisan. Ia tidak tahu bahwa orang itu adalah sahabat saya,” ujar Dorce sembari mengusap matanya yang basah menahan dukanya yang dalam.
 Lain di panggung, lain pula keadaan Dorce sehari-hari. Di panggung ia selalu menebar senyum dan membuat jutaan penggemarnya terhibur dan tertawa penuh sukacita. Ia bahagia karena bisa membahagiakan banyak orang. Tapi, bagaimana dengan dirinya? Ia tidak bisa lain, selain menangis dan bersimpuh di hadapan-Nya.
Lain di panggung, lain pula keadaan Dorce sehari-hari. Di panggung ia selalu menebar senyum dan membuat jutaan penggemarnya terhibur dan tertawa penuh sukacita. Ia bahagia karena bisa membahagiakan banyak orang. Tapi, bagaimana dengan dirinya? Ia tidak bisa lain, selain menangis dan bersimpuh di hadapan-Nya.
sumber : http://www.femina.co.id









