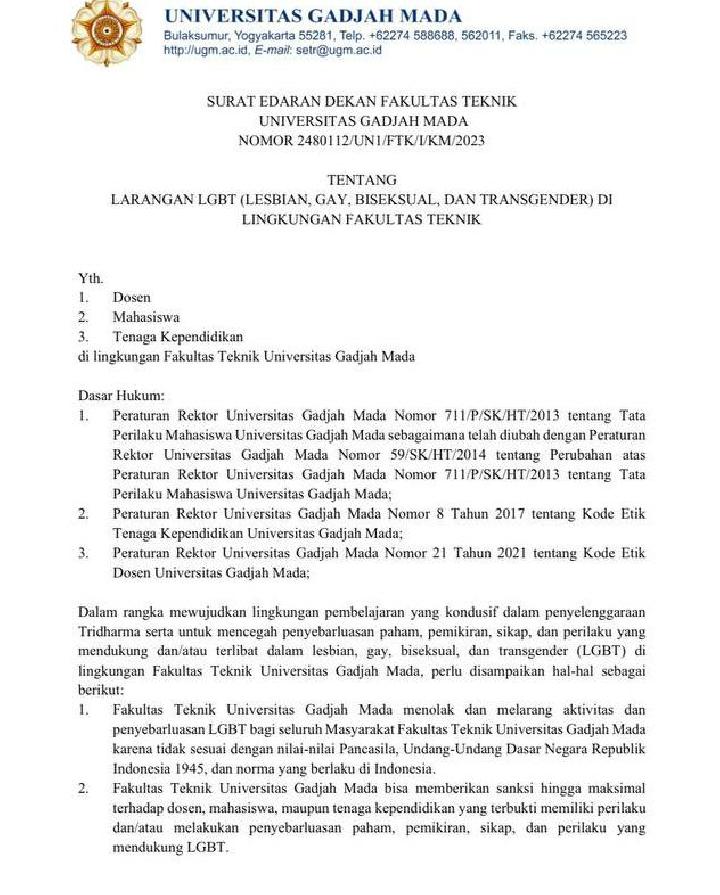Oleh: Hartoyo*
Kasus toilet berbasis gender mulai mengalami banyak persoalan. Ketika ada pemisahan toilet berdasarkan jenis kelamin perempuan dan pria yang sangat buta gender. Bagaimana dengan kelompok transgender? Harus masuk ke toilet mana?
Kelompok transgender bukan kelompok yang menguntungkan secara “politis”, akibatnya pengalaman mereka sering diabaikan. Pengabaian atas realitas itu kemudian menimbulkan masalah baik pada laki-laki, perempuan, maupun kelompok transgender sendiri.
Baru-baru ini terjadi di Fakultas Teknik UGM, kasusnya karena ada perempuan merasa tidak nyaman ketika ada seorang mahasiswi transpuan masuk ke toilet perempuan, akhirnya pihak Fakultas mengeluarkan Surat Edaran yang melarang LGBT. Isunya malah melebar ke persoalan larangan identitas LGBTIQ.
Kembali ke pertanyaan awal, transpuan akan masuk ke toilet mana? Toilet laki-laki, apakah dipastikan bahwa semua laki-laki juga akan nyaman ketika seorang transpuan masuk ke toilet laki-laki? Perlu juga ditanya, apakah setiap transpuan dalam situasi ini, benar-benar nyaman masuk ke toilet perempuan dan laki-laki?
Saya yakin tidak semua transpuan maupun transmen akan merasa nyaman ketika diperhadapkan pada situasi masyarakat atau kebijakan kampus yang tidak mengakui adanya realitas keberagaman gender dan seksualitas manusia. Jangankan transgender, saya sebagai seorang cisgender laki-laki gay sering sekali tidak nyaman masuk ke toilet pria ataupun sekamar tidur dengan seorang teman pria yang sudah mengetahui identitas diriku sebagai gay.
Makanya setiap saya mendapatkan undangan acara yang mengharuskan menginap di sebuah hotel, saya selalu memberi syarat tidak mau sekamar berdua, baik dengan perempuan maupun laki-laki. Syarat ini buat kebaikan untuk diriku maupun pihak lain yang akan sekamar denganku. Jika syarat itu tidak dibolehkan oleh panitia, saya biasanya akan lebih memilih tidak menginap atau mencari penginap lain dengan biaya sendiri.
Dewasa ini, program atas nama inklusi kian bermunculan. Seperti gerakan atau kebijakan keharusan menyediakan bangunan, khususnya toilet yang ramah disabilitas. Toilet disabilitas biasanya bersifat “netral gender”. Dimana toilet itu sifatnya unisex, bisa dipakai oleh gender dan jenis apapun dari individu disabilitas. Kenapa pada toilet disabilitas tidak memasukkan pertimbangan perbedaan jenis kelamin?
Kalau melihat persoalan yang terjadi di Fakultas Teknik UGM, apakah solusinya menggabungkan toilet disabilitas dengan toilet untuk transgender? Apakah jika upaya itu dilakukan akan menjawab persoalan? Bagaimana dengan toilet komunitas gay dan lesbian? Padahal mahasiswa/i yang lesbian, biseksual atau gay jumlahnya dipastikan lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa/i transgender.
Masalahnya, karena tidak banyak orang terbuka, tidak tahu, atau cuek dengan identitas gay dan lesbian. Maka dianggap ini bukan persoalan bagi publik. Untuk itu tawaran yang paling praktis, membangun atau mendesain toilet perspektif inklusi.
Fakultas Teknik UGM banyak ahli design, baik teknik arsitektur maupun teknik sipil yang dapat menawarkan satu rancangan “Toilet Inklusi”. Dimana sebuah toilet yang dapat digunakan, aman, dan nyaman oleh setiap individu. Baik laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, orang tua, transgender, maupun ragam identitas gender dan orientasi seksual.
Jika rancangan “toilet inklusi” itu mampu “diciptakan” oleh para ahli teknik di UGM, bukankah ini akan memberikan dampak baik pada semua orang? Apalagi ketika desain toilet itu dapat diterapkan di semua kantor pemerintah, swasta maupun rumah.
Desain toilet inklusi bukan hanya memunculkan estetika baru tetapi juga memberikan sumbangsih pada peradaban manusia yang leb
Jakarta, 16 Desember 2023
*Penulis adalah Anggota Perkumpulan Suara Kita. Penulis juga adalah Koordinator advokasi hak Adminduk dan Jamsos bagi Kelompok Transgender di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui WhatsApp 087738849584.